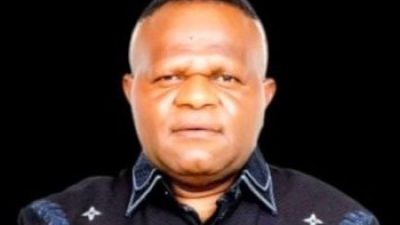![]()
Oleh Anselma Doo
Mahasiswi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua
PENDIDIKAN merupakan investasi dasar sumber daya manusia, based investment of human capital, bagi sebuah bangsa di masa kini dan akan datang. Bila dilihat dari aspek filosofis maupun historis, pendidikan berperan strategis ikut mewarnai perjalanan sebuah bangsa dan menjadi basis atau landasan moral dan etika dalam proses pembentukan jati diri anggota komunitas bangsa bersangkutan.
Tujuan pendidikan nasional adalah tercapainya manusia Indonesia seutuhnya. Ciri utamanya adalah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawa, dengan berbagai atribut yang menyangkut cipta, rasa, dan karsa (kognitif, afektif, dan psikomotorik).
Upaya pendidikan yang berkaitan dengan budaya dapat dilakukan melalui program di sekolah mengingat sekolah merupakan wahana pendidikan formal yang dilalui oleh setiap warga negara. Namun, tidak semua sekolah yang menerapkannya. Pendidikan di wilayah Papua, khusus di wilayah adat Meepago belum menyentuh pada pendidikan yang diharapkan secara nasional.
Dalam konteks pendidikan di Deiyai, sepintas belum menciptakan iklim pendidikan yang berciri khas pada kecintaan pada budaya lokal. Padahal, dengan wajah pendidikan ramah budaya lokal dapat membuat para peserta didik nyaman dengan budayanya sendiri. Generasi muda sekarang terkesan belum mengenal budayanya.
Hal ini beralasan karena sekolah belum seluruhnya menjadikan khasana budaya dan adat-istiadat lokal warisan leluhur dalam pelajaran muatan lokal (mulok) secara efektif di sekolah. Akibatnya, saat ini banyak anak usia sekolah kelompok milenial tidak tahu bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu. Tidak semua anak Papua suka membawa noken, tas hasil rajutan khas dari Papua. Padahal, noken adalah suatu warisan leluhur Papua yang sudah mendunia.
Publik Tanah Air dan Papua khususnya tahu. Pada 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Bergerak (Intangible Cultural Heritage) dalam Sidang Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebuadayaan (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Unesco) di Paris, Prancis.
Penetapan ini tentu melalui proses panjang memenuhi berbagai kriteria sebagai upaya perlindungan terhadap warisan budaya tak benda sesuai konvensi perlindungan warisan budaya tak benda oleh Unesco tahun 2003. Penetapan ini berdasarkan hasil usulan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Tidak semua anak Deiyai berani pakai pakaian tradisional (koteka dan moge) sebagai simbol pakaian adat. Tidak semua anak Mee dapat bernyanyi lagu daerah, misalnya Tupee, Komaugaa, Gowai dan beberapa lagu tradisonal lainnya.
Kenyataanya siswa tidak mampu lagu bahasa daerah hingga tidak diminati namun sekolah tidak mengajarkannya. Hal lain tentang budaya lokal berpakaian tradisional koteka moge. Tidak semua anak muda sekarang membiasakan diri mengenakan pakaian tradisionalnya dalam acara-acara formal. Hal seperti ini dapat dijumpai pada anak-anak sekolah khususnya pada anak laki maupun perempuan generasi muda.
Namun demikian, masih juga kita jumpai anak muda Papua mengenakan pakaian adat. Begitu juga terkait dengan bahasa daerah. Tidak banyak anak muda yang tahu serta memahami dengan benar bahasa ibunya. Fenomena yang terjadi, sebagian besar anak muda cara berbahasa atau berkomunikasi dengan orang lain tidak sesuai dengan basaha tutur daerahnya.
Hal ini terjadi karena sebagian mereka kurang memahami nilai dan falsafah berbahasa yang terkandung di dalam bahasa Mee. Padahal, memahami makna dan simbol bahasa daerah dengan baik dan benar dapat menunjukkan jati diri, tata krama, sopan santun dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah dan semua wadah pendidikan saatnya memandang perlunya mentransfer pengetahuan tentang budaya lokal kepada anak-anak.Dengan demikian, mereka tidak kehilangan identitas, jati diri sebagai sebuah suku bangsa. Salah satunya pintu masuk adalah memasukkan program pelajaran mulok di sekolah, di mana di dalamnya guru dapat berkreasi mengemas pengetahuan yang digali dari kekayaan nilai-nilai budaya lokal peserta didik.
Mengemas pengetahuan yang bersifat memperkenalkan dan memperagakan budaya lokal. Misalnya soal bahasa, falsafah hidup, lagu-lagu, tata krama, pakaian tradisional, tari-tarian, lagu-lagu dan kesenian setempat, kerajinan daerah seperti ukiran, dan lain-lain. Pengetahuan seperti ini dapat diajarkan kepada siswa di sekolah agar rasa cinta akan budaya setempat tumbuh sejak dini. Akan lebih baik lagi jika kepemimpinan sekolah ditata menjadi sekolah yang ramah budaya lokal.
Program pendidikan dapat disesuaikan dengan potensi daerah, minat, kebutuhan peserta didik, dan kebutuhan daerah agar peserta didik dapat mengenal budaya lokal dan lingkungan tempat tinggalnya. Dengan demikian, kelak dapat mengembangkan dan melestarikan sumber daya lokal di sekitarnya.
Landasan kurikulum mulok diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Karena itu,di tingkat lokal seperti wilayah adat Meepago dan Papua umumnya, mulok menjadi sangat penting diajarkan di sekolah-sekolah.
Sedangkan terkait kepemimpinan sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Menurut Permendikbud tersebut, yang dimaksud kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Kepala sekolah menjadi pemimpin pendidikan.
Dalam Kepemimpinan Pendidikan (2021), Mataputun menjelaskan bahwa dalam kepemimpinanya selain bertanggungjawab terhadap operasionalnya kegiatan sekolah, kepala sekolah juga menentukan tujuan sekolah. Sejalan dengan itu pendidikan ramah budaya berbasis mulok dapat dimasukkan menjadi salah satu dari tujuan sekolah. Mengapa? Kepala sekolah merupakan orang yang secara legal formal mempunyai otoritas untuk mengelola dan memimpin sekolah.
Ramah budaya
Term “ramah” merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KUBI) berrarti baik hati dan menarik budi bahasanya. Sedangkan “budaya” adalah adat istiadat yang dimiliki dan dihidupi suatu suku bangsa. Adat istiadat itu berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap baik dan diwariskan nenek moyang turun-temurun. Hal yang diyakini ada dan sangat melekat dalam kehidupan manusia sebelum dipengaruhi oleh budaya lain. Karena itu, ramah budaya maksudnya adalah adat istiadat, norma-norma hidup warisan leluhur yang menarik, dipelajari, dan diterapkan bagi sebuah komunitas masyarakat.
Belajar budaya melalui kurikulum muatan lokal merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan pendidikan yang ramah budaya lokal. Pendidikan yang menghargai budaya lokal baik secara ilmu, kegiatan kokurikuler, maupun tata lakunya oleh warga sekolah dalam komunitas sekolah. Pembelajaran budaya memuat tiga unsur.
Pertama, belajar tentang budaya yang menempatkan budaya sebagai bidang ilmu). Kedua, belajar dengan budaya seperti metode pemanfaatan budaya. Ketiga, belajar melalui budaya yang mencakup pemahaman makna yang diciptakan baik melalui kreativitas maupun imajinasi dalam ragam perwujudan budaya, yang berkaitan langsung tentang nilai-nilai yang terkandung dalam budaya. Tiga unsur ini perlu diwujudkan dalam komunitas sekolah.
Pendidikan dan budaya memiliki hubungan yang erat. Pada hakekatnya keduanya saling melengkapi. Melalui pendidikan segala sesuatu yang terkandung di dalam kebudayaan dari satu generasi dapat ditransfer kepada generasi berikutnya. Pendidikan yang diajarkan kepada peserta didik tidak hanya berupa pengetahuan budaya tetapi juga pendidikan nilai yang terkandung di dalam budaya.
Pendidikan yang diterima peserta didik tidak hanya pengetahuan dalam mulok tetapi makna dan nilai yang terkandung dalam budaya setempat. Makna dan nilai-nilai budaya yang dipelajari peserta didik tidak hanya sebatas pengetahuan tetapi diterapkan seluruh warga dan komunitas sekolah.
Sekolah melalui kepemimpinan kepala sekolah dapat menciptakan iklim Sekolah ramah Budaya. Kepala Sekolah sebagai pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinanya, dapat melakukan tata kelola pendidikan, menciptakan iklim pendidikan yang ramah budaya melalui kurikulum muatan lokal.
Hal itu tidak hanya bersifat suatu mata pelajaran tetapi lebih dari pada itu dapat menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga sekolah. Suatu iklim pendidikan yang terus menantang setiap warga sekolah untuk melaksanakan nilai-nilai budaya di lingkungan sekolah.
Kepala sekolah dalam kepemimpinannya dapat memberi ruang khusus kepada peserta didik untuk berekspresi. Perlu ada hari khusus dalam minggu ditentukan sebagai hari budaya. Ekspresi budaya dapat berupa hari wajib membawa noken, menggunakan bahasa daerah atau mengenakan busana tradisional. Ekspresi budaya dapat juga berupa menata ruangan kelas dengan ukiran-ukiran khas daerah. Mewajibkan seluruh anggota komunitas menata lingkungan sekolah asosori bernuansa lokal. Menjaga tata krama dan sopan-santun setempat.
Selain itu masih banyak hal dalam budaya yang dapat digali, diajarkan dan terus diwariskan kepada anak-anak di lingkungan sekolah. Sekolah proaktif menggali, menata, dan mengajarkan budaya suku setempat kepada peserta didik agar kelak mereka tidak kehilangan indentitas, diri diri sebagai anak marga, anak meuwodede, ana suku Mee, anak Papua, anak Melanesia, anak Indonesia yang unik dan tak tergantikan.