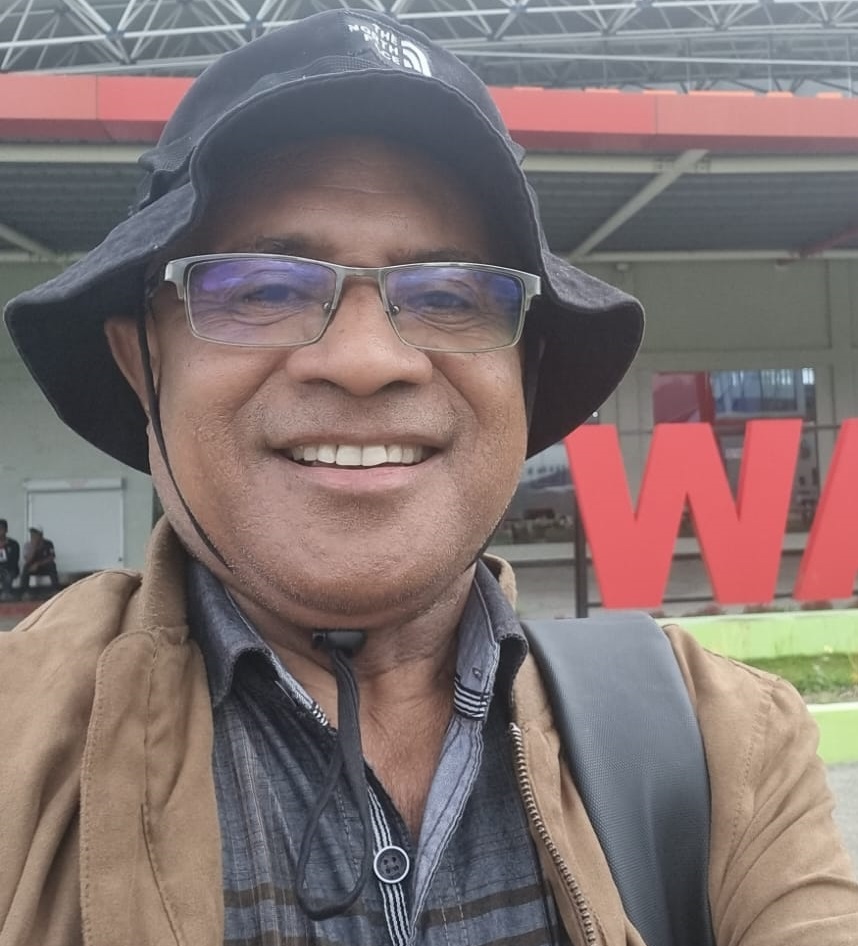Oleh Frans Maniagasi
Pengamat politik lokal Papua
PADA 7 Februari 2024 di Wamena ibu kota Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan rapat koordinasi oleh Penjabat Gubernur Dr Velix Wanggai bersama delapan bupati serta anggota Forkopimda terkait persiapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum, baik Pilpres maupun Pileg yang digelar serentak, Rabu (14/2).
Rapat yang dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo. Dalam rapat tersebut salah satu topik yang menjadi sorotan komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan Theo Kossay. Kossay menyatakan, sudah saatnya perlu ditinjau pemberlakuan sistem noken pada pemungutan suara di Pemilu.
Hal itu tentunya menimbulkan pertanyaan dalam benak saya (penulis), mengapa sistem noken perlu ditinjau kembali? Selama ini sistem noken menjadi sarana oleh masyarakat di wilayah pegunungan menyalurkan aspirasinya dalam pemilihan. Untuk menjawab pertanyaan itu ada dua pandangan yang perlu diperhatikan.
Pertama, pendapat yang menyatakan, sistem noken yang dipraktikkan pada Pemilu (Pilpres dan Pileg) maupun pilkada kabupaten dan provinsi nanti dianggap tidak relevan dengan perkembangan demokrasi.
Selain tak relevan, dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Pengalaman empiris menunjukkan inheren dengan praktik sistem noken telah berimplikasi terjadinya manipulasi dan transaksi suara.
Konsekuensinya, muncul kriminalisasi pada setiap kali event Pemilu, seperti sinyalemen Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Kasus-kasus hari ini yang terjadi tak terhindarkan yang sedang aktual kita hadapi.
Ekses lain tak terhindarkan adanya mobilisasi dalam pemberian suara yang tersentralisasi pada seseorang yang otomatis berlawanan dengan demokrasi sistem one man one vote. Praktik ini mudah dilakukan oleh elite birokrasi dan pemerintahan untuk mengintervensi hasil suara di tingkat PPD.
Apalagi kewenangannya yang otoritatif dapat mengalihkan perolehan suara kepada orang lain seperti keluarga dan relasi perkoncoannya, maka dipastikan terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Kedua, ada argumentasi bahwa sistem noken merupakan manifestasi dari nilai dan budaya setempat sebagai basis legitimasi sesuai amanat UU Otsus (UU No 21/2001 juncto UU No 2/2021) berciri kekhususan dan kekhasan Papua, teristimewa di wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah (Putusan Mahkamah Konstitusi No 31/PUU – XII/2014).
Selain itu dari studi antropologi tentang pola kepimpinan tradisional di Papua seperti tesis dari antropolog senior Uncen Prof Josh Mansoben (1994), terdapat empat pola kepimpinan (ondoafi, raja, bigman, dan campuran).
Di kalangan masyarakat Papua khususnya di pegunungan dikenal dengan pola kepemimpinan big man (orang besar atau kepala suku) serta sistem pengambilan keputusan musyawarah mufakat merupakan variabel kekhususan yang turut mendukung sistem noken.
Dengan kata lain corak seperti ini yang oleh Edward Aspinal & Ward Berenschot (2020) juga disebut demokrasi patronase. Demokrasi model ini sebenarnya merupakan praktik umum di Indonesia bahkan di seluruh dunia tatkala menghadapi Pemilu. Demokrasi patronase diwarnai oleh politik klientelisme (klien).
Klientelisme terdapat hampir di seluruh tingkatan institusi termasuk partai politik yang dibayangi oleh jejaring informal dan personal yang melaluinya mengalir keuntungan material dan bantuan. Contoh kasus apa yang diributkan dengan bantuan sosial (bansos) menjelang hari pencoblosan merupakan perwujudan dari praktik klientelisme dimaksud.
Di kalangan masyarakat Papua Pegunungan klientalisme dalam perspektif kultural khususnya mengacu pada corak kepimpinan tradisonal big man. Bukan sekadar aspek dukungan material, namun lebih pada seorang kepala suku yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan, mengayomi masyarakatnya (suku, marga) dan juga proses pengambilan keputusan dengan musyawarah-mufakat.
Peranan kepala suku sangat sentral dan dominan dalam pengambilan keputusan sehingga apa yang diputuskan oleh kepala suku itulah yang menjadi pedoman masyarakat untuk menjatuhkan pilihannnya.
Dua perspektif yang berbeda dengan argumetasinya masing-masing tapi tujuannya agar masyarakat dapat menyalurkan hak dan aspirasi politiknya melalui sistem Pemilu yang demokratis dan bermartabat tanpa mengenyampingkan kekhususan dan kekhasan nilai dan budaya lokal.
Demokrasi deliberatif dan pendidikan politik
Jika sistem noken hendak ditinjau putusan Mahkamah Konstitusi (No 31/PUU-XII/ 2014) maka menurut apa yang dikonstatir oleh Penjabat Gubernur Velix Wanggai syaratnya yang mesti dilakukan adalah pendidikan politik (political education) dan pendidikan publik (civic education) lewat demokrasi deliberatif publik atau warga masyarakat sebagai inti pembuatan keputusan yang diproduksi oleh negara melalui konsultasi dan uji publik. Sehingga melibatkan para pihak yang akan terkena imbas dari kebijakan peninjauan sistem noken.
Artinya, sebelum sistem noken diganti dengan sistem one man one vote, perlu dilakukan sosialisasi, konsultasi dan uji publik kepada para pemangku kepentingan terutama kepala suku sehingga tak menimbulkan kegaduhan kelak di kemudian hari bila terjadi perubahan sistem pemilihan. Pendidikan politik masyarakat menjadi urgen dan berbasis lokal, berpedoman pada tradisi dan budayanya.
Sehingga dalam rangka sosialisasi dan pendidikan politiknya dapat menggunakan keseharian lewat visualisasi seperti tanaman pertanian ubi, ketela, singkong, jagung, foto atau gambar yang memudahkan masyarakat menangkap pesan dan meresapi sesuai alam pikirannya. Simbolisasi alat peraga melalui pengetahuan lokal (local knowledge) berbasis kearifan lokal (local wisdom) seperti itu justru memudahkan untuk masyarakat menerimanya.
Pengalaman emperis pelaksanaan Pemilu pertama 1971 di masa Orde Baru khusus di Papua (Irian Jaya) pernah menggunakan simbol lokal seperti jagung, payung, salib, dan ka’abah, yang mencerminkan lambang dari kontestan peserta Pemilu.
Pengalaman ini dapat diadopsi dan dimodifikasi sebagai media komunikasi dan sosialisasi dalam rangka memperkokoh pendidikan politik kepada masyarakat yang diadaptasikan dengan lingkungannya serta tingkat pendidikan dan pengalamannya. Simpel, tak rumit dalam rangka pendidikan dan pemahaman politik masyarakat.
Perlu disadari untuk dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan guna memastikan sosialisasi dan pendalaman yang serius sekaligus memberikan pemahaman pada masyarakat, sehingga dapat dilakoninya. Memang tidak segampang membalik telapak tangan melakukan transformasi dan perubahan mind set masyarakat bermigrasi dari sistem noken ke sistem one man one vote.
Hal tak kalah penting, jangan sampai menimbulkan dampak psikologis politis berkurangnya peranan dan wewenang dari seorang kepala suku yang tadinya dominan dalam pengambilan keputusan, memberikan direction kepada masyarakat untuk menjatuhkan pilihan kepada kandidatnya. Butuh proses dan time line tidak saja dilakukan menghadapi Pemilu. Katakan butuh lima tahun dalam menyiapkan masyarakat untuk menggunakan cara baru.
Dengan demikian praktik dalam rangka substitusi transisi dari sistem noken ke sistem one man one vote dapat terwujud. Fungsi dan peranan partai politik maupun penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) agar bekerja serius menyukseskan transformasi politik dan transformasi digital kepada konstituen dan masyarakat.