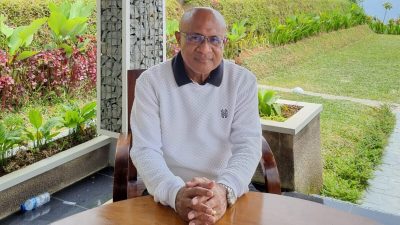Oleh Yoseph Yapi Taum
Penyair dan Dekan Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma
AGUSTUS 2025 mencatat satu bab gelap dalam demokrasi kita. Jalanan Jakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar dipenuhi massa yang berteriak, marah, dan akhirnya menjarah. Awalnya hanya protes soal kenaikan tunjangan anggota DPR. Tetapi bara api kecil itu meledak menjadi amukan kolektif, merenggut nyawa Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Di ruang publik, alih-alih menyelami akar persoalan, para pejabat sibuk mencari “dalang” seolah kerusuhan hanyalah konspirasi.
Narasi pencarian dalang ini sesungguhnya bukan hal baru. Dari era Orde Lama hingga kini, retorika yang sama berulang: selalu ada tangan tak terlihat, ada aktor misterius, ada musuh bersama yang perlu ditunjuk. Padahal, seperti diingatkan Ernest Bevin, pertanyaan tentang “siapa dalangnya” hanyalah cermin dari pikiran orang-orang malas. Di sinilah teori René Girard, filsuf dan antropolog Prancis, terasa relevan. Girard menyingkap bahwa peradaban manusia berdiri di atas mekanisme kambing hitam: ketika konflik meluas dan kekerasan membuncah, masyarakat meredakannya dengan mengorbankan seseorang atau sekelompok kecil.
Api Hasrat yang Menular
Girard memulai dari gagasan mimetic desire: kita menginginkan apa yang orang lain inginkan. Hasrat itu menular, membentuk rivalitas. Publik ingin hidup layak di tengah krisis ekonomi; para elit ingin mempertahankan privilese dengan menaikkan tunjangan. Dua hasrat yang bertabrakan inilah yang melahirkan medan magnet konflik. Ketika energi sosial menumpuk, percikan kecil saja cukup meledakkannya menjadi kerusuhan.
Ketika rivalitas meluas, muncullah apa yang disebut Girard sebagai “krisis mimesis”—perang semua melawan semua. Untuk meredamnya, masyarakat (atau elite yang mewakilinya) mencari kambing hitam (the scapegoat mechanism). Seseorang dikorbankan agar amarah kolektif tersalurkan. Dengan begitu, kekacauan berhenti, setidaknya sementara. Itulah logika yang berulang dalam sejarah bangsa ini: dari tuduhan komunis 1965, kriminalisasi aktivis 1998, hingga tragedi Agustus 2025.
Dalang dan Dalih
Karena itu tidak mengejutkan ketika pejabat segera menggaungkan retorika “mengungkap dalang.” Bagi Idrus Marham, Hendropriyono, dan sejumlah tokoh lain, mencari dalang adalah prioritas. Padahal, seperti ditunjukkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sumber kerusuhan jauh lebih sederhana: akumulasi kemarahan rakyat terhadap kondisi ekonomi yang buruk dan DPR yang abai. Artinya, “dalang” itu bukan sosok misterius, melainkan kegagalan struktural yang menumpuk.
Namun mengakuinya berarti para penguasa harus bercermin, mengakui kelemahan diri, dan bertanggung jawab. Itu pekerjaan yang paling mereka hindari. Maka dalih pun diciptakan. Masyarakat diarahkan untuk membenci musuh imajiner. Mekanisme kambing hitam kembali bekerja, menjaga status quo sambil menunda letusan berikutnya.
Polisi, Tumbal Baru
Ketika Affan Kurniawan tewas, arah kemarahan berubah. Target publik bukan lagi DPR, melainkan kepolisian. Institusi ini memang sudah lama digelayuti krisis kepercayaan: dari kasus “polisi bunuh polisi” hingga adagium “no viral no justice.” Tragedi Agustus 2025 membuat semua akumulasi itu meledak.
Bagaimana respons polisi? Bukan dengan reformasi substantif, melainkan dengan mencari tumbal di tubuhnya sendiri. Kompol Cosmas dan sejumlah anggota Brimob dijatuhi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Sidang etik yang digelar lebih menyerupai ritual pengurbanan ketimbang upaya mencari kebenaran. Hukuman cepat dan keras dijatuhkan bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk meredam amarah publik.
Cosmas, yang di ruang sidang membuat tanda salib sebelum putusan dibacakan, tampil sebagai figur tragis. Ia bukan dalang, bukan perancang tragedi, melainkan aparat di lapangan yang menjadi tumbal agar citra institusi selamat. Persis seperti yang ditulis Girard: korban diposisikan seakan-akan rela berkorban demi keselamatan komunitas, padahal ia hanya dijadikan alat untuk menutupi dosa kolektif.
Kebohongan yang Terbuka
Dalam mitos kuno, pengurbanan semacam ini ditutupi oleh “kebohongan mitis”—bahwa korban memang bersalah, atau bahwa ia dengan sukarela menyerahkan diri. Tapi di era modern, kebohongan itu semakin sulit bertahan. Forum Pemuda NTT dan berbagai kelompok masyarakat menyuarakan bahwa korban sebenarnya tidak bersalah. Ketika publik sadar bahwa Cosmas hanyalah tumbal, daya sihir mekanisme kambing hitam memudar. Kebisuan para pemimpin menjadi telanjang.
Di titik ini, pertanyaan yang lebih mendesak muncul: sampai kapan bangsa ini bertahan dengan cara lama—mengorbankan individu untuk menutupi kegagalan sistemik?
Tragedi Agustus 2025 memperlihatkan anatomi yang sama: hasrat menular → rivalitas membesar → kekacauan → kambing hitam → stabilitas semu. Tapi siklus itu hanya menunda masalah. Akar persoalan—ketidakadilan ekonomi, korupsi, krisis kepemimpinan—tetap membara. Maka jangan heran jika korban berikutnya tinggal menunggu waktu. Akan selalu ada Affan Kurniawan baru, Cosmas baru, tumbal baru.
Jalan keluar bukanlah terus mencari kambing hitam, melainkan membongkar mekanisme itu sendiri. Para pemimpin harus berani bercermin: mengakui kesalahan, bertanggung jawab secara moral, dan melakukan reformasi substantif. Polisi harus mengubah budaya represif menjadi budaya pelayanan yang transparan. DPR harus melepaskan privilese yang menyinggung rasa keadilan publik. Dan masyarakat harus kritis: menolak retorika dalang, menuntut akuntabilitas sistemik, bukan sekadar hukuman simbolis. Tanpa keberanian kolektif ini, bangsa hanya akan berputar dalam lingkaran setan, menunggu tumbal berikutnya jatuh.