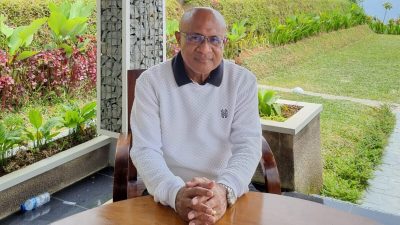Oleh Imanuel Gurik
Doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua
MAS KAWIN (bride price) adalah simbol pengikat relasi perkawinan pria dan wanita lajang dalam tradisi adat istiadat masyarakat Papua. Mas kawin bukan sekadar urusan saling menghormati kedua bela pihak suku dari pasangan yang akan melangsungkan pernikahan suci.
Namun, lebih dari itu mas kawin juga simbol penghargaan keluarga pria kepada calon mempelai wanita dalam relasi sosial. Mas kawin juga adalah pengikat relasi antar-keluarga dan antar-marga. Ia simbol pengikat nilai-nilai kekerabatan, status sosial serta pandangan hidup orang Papua terhadap manusia, perempuan, dan perkawinan itu sendiri.
Dalam konteks komunitas adat masyarakat Papua, mas kawin bukanlah sesuatu yang mengandung pengertian tunggal sebagai pengikat perkawinan dua pasangan calon pengantin. Karena itu, dalam keragaman suku, marga, dan budaya beragam mas kawin juga memiliki bentuk, ukuran, simbol, dan cara pandang yang berbeda.
Mas kawin di setiap wilayah adat di tanah seperti Mamberamo-Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Ha Anim, La Pago, dan Mee Pago memiliki pemaknaan mendalam selain sekadar pengikat dalam perkawinan. Dalam praktek perkawinan di tujuh wilayah adat ini, makna mas kawin juga dapat dilihat lebih dalam, terkait aspek sosial-budaya, tantangan modernisasi serta relevansinya dalam pembangunan sosial.
Konteks Budaya
Maskawin di Papua memiliki dimensi ganda. Di satu sisi, ia adalah bentuk ekonomi tradisional: pembayaran dengan benda berharga seperti manik-manik, kain timur, piring antik, garam, besi, hingga babi dan sekarang uang tunai.
Di sisi lain, ia adalah simbol ikatan sosial-spiritual. Artinya, seorang calon pengantin pria dan keluarganya menghargai calon pengantin wanita dan keluarganya sebagai mitra sejajar.
Mas kawin juga mengandung nilai-nilai utama yaitu penghargaan calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Mas kawin menegaskan bahwa perempuan adalah makhluk berharga, yang membawa kehidupan dan keturunan.
Dalam ikatan kekerabatan, mas kawin memperluas jaringan sosial antara marga, kampung bahkan antar-suku. Mas kawin juga simbol status. Semakin besar mas kawin, semakin tinggi status sosial pihak laki-laki.
Mas kawin juga memiliki nilai sosial bagi keluarga besar kedua belah pihak. Mas kawin yang diterima pihak perempuan dibagi kepada keluarga yang lebih luas sehingga manfaatnya menyebar.
Antropolog dan teolog Papua Pendeta Dr Benny Giay menegaskan, mas kawin bukan bertujuan membeli perempuan, melainkan simbol penghargaan tertinggi kepada perempuan dan keluarganya. Nilai mas kawin tidak boleh dilihat sekadar dari sisi uang tetapi dari nilai hubungan yang diciptakannya.
Namun, dalam perkembangan sekarang, kerap muncul situasi yang dilematis. Mas kawin sering dianggap terlalu mahal sehingga memberatkan satu pihak dalam perkawinan bahkan menimbulkan konflik sosial dan kemiskinan.
Di sini selalu menuntut kepekaan keluarga kedua belah pihak dari tujuh wilayah adat di Papua memahami bagaimana memandang mas kawin dalam konteks tradisi dan modernitas.
Tujuh Wilayah Adat
Mas kawin di tujuh wilayah adat di tanah Papua menarik dilihat lebih jauh. Misalnya, wilayah adat Mamta (Tabi). Mamta meliputi daerah Jayapura, Keerom, Sarmi, dan sekitarnya. Di wilayah ini, mas kawin sangat erat kaitannya dengan benda-benda antik yang bernilai sejarah, seperti manik-manik (noken timur), piring porselen, dan kain timur.
Bentuk mas kawin berupa manik kuno (bulu emas, bulu putih), guci, piring antik, serta kini uang tunai. Nilai sosial dalam masyarakat adat Mamta yaitu manik dianggap memiliki kekuatan magis dan spiritual serta diwariskan turun-temurun. Namun, seiring perubahan waktu, generasi saat ini cenderung menggunakan uang tunai dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Tokoh adat Tabi Yuli Heluay mengatakan, manik dan piring dalam mas kawin adalah pusaka leluhur. Setiap kali mas kawin dibayar sesungguhnya kita sedang menghidupkan kembali sejarah dan hubungan kekerabatan antar-marga. Maskawin di Mamta lebih menekankan simbol warisan leluhur dibandingkan sekadar nilai ekonomi.
Begitu pula wilayah adat Saireri. Wilayah adat ini meliputi Biak, Yapen, Waropen, dan Supiori. Di sini, mas kawin identik dengan piring antik, guci, dan manik-manik dari jalur perdagangan laut.
Bentuk mas kawin berupa piring putih Belanda, guci keramik Cina, manik-manik, perahu serta uang tunai. Mas kawin dalam wilayah adat Saireri memiliki nilai sosial. Ia menjadi simbol status yang tinggi dari komunitas adat. Semakin banyak piring antik yang diberikan, semakin terhormat pihak laki-laki.
Seiring kemajuan modernisasi, saat ini uang tunai lebih dominan dan benda-benda antik tetap dipertahankan sebagai unsur sakral. Mas kawin Saireri sangat dipengaruhi oleh hubungan perdagangan laut sejak abad ke-16.
Kemudian, wilayah adat Domberai meliputi daerah kepala burung yaitu Manokwari, Bintuni, dan Wondama. Mas kawin di sini berhubungan erat dengan kekayaan alam berupa manik, piring serta hasil bumi. Bentuk mas kawin adalah kain timur, perahu, babi, manik hingga uang tunai.
Nilai sosial mas kawin menjadi simbol keterikatan antara marga. Namun, seiring perubahan terutama masuknya agama dan pendidikan membuat mas kawin sedikit lebih sederhana, walau tetap tinggi di kalangan masyarakat adat tertentu.
Wilayah adat Bomberai meliputi Fakfak, Kaimana, Teluk Arguni hingga Kokas. Sebagai wilayah yang lama bersentuhan dengan Islam dan budaya Maluku, di sini mas kawin memiliki warna berbeda. Mas kawin di sini berupa manik-manik, piring, guci, kain timur, perhiasan emas, dan uang tunai.
Nilai sosial mas kawin atau belis berfungsi memperkuat ikatan antar-kampung. Seiring pengaruh Islam, prosesi perkawinan diwarnai adat dan syariat, sehingga mas kawin sering dipadukan dengan mahar Islami.
Wilayah adat Ha Anim meliputi Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Mas kawin di wilayah ini lebih banyak berupa babi, hasil kebun, dan barang-barang simbolik. Bentuk mas kawin berupa wati, babi, sagu, perahu jonson serta uang tunai.
Wati dan babi menjadi ukuran kekayaan dan status sosial. Meski uang tunai masuk sebagai pengganti, wati tetap menjadi inti mas kawin. Bagi orang Asmat, wati bukan sekadar minuman tetapi simbol kehidupan dan kemakmuran.
Kemudian, wilayah adat La Pago mencakup suku-suku pegunungan tengah bagian timur seperti Lani, Nayak, Yali, Nduga, dan lain-lain. Mas kawin di sini sangat terkenal dengan babi dalam jumlah besar. Jumlah mas kawin berupa babi berjumlah puluhan hingga ratusan ekor, kemudian noken, dan kadang ditambah manik atau uang.
Babi adalah pusat ekonomi, simbol persahabatan, dan sarana perdamaian. Babi menjadi penanda status sosial. Meski demikian, mas kawin sering menjadi beban karena jumlah babi yang dituntut sangat banyak. Bahkan babi sebagai mas kawin kerap membuat keluarga laki-laki jatuh dalam jebakan utang.
Tokoh adat Kitanggem Yikwa dari Lembah Toli (Swart Valley) menegaskan, babi dalam mas kawin bukan sekadar harta, tetapi tanda kehidupan. Namun, bila jumlah babi terlalu banyak, maknanya hilang dan berubah menjadi beban.
Kemudian, wilayah Adat Mee Pago meliputi suku-suku Mee, Moni, Damal, dan lain-lain. Mas kawin di sini juga berfokus pada babi, manik, dan uang tunai. Jumlah mas kawin berupa babi mencapai belasan hingga puluhan ekor ditambah uang tunai dan perhiasan.
Babi adalah simbol kehidupan dan ikatan sosial. Kini, banyak keluarga mulai menuntut uang tunai dalam jumlah besar, berdampingan dengan babi. Di kalangan masyarakat Mee Pago dan La Pago sering terjadi polemik akibat “tingginya harga” babi sebagai mas kawin.
Tantangan Masa Depan
Seiring modernisasi, mas kawin menghadapi tantangan serius. Pertama, beban ekonomi. Mas kawin yang mahal membuat banyak pemuda sulit menikah bahkan terjerat hutang.
Kedua, komersialisasi. nilai simbolik mas kawin sebagai simbol adat budaya yang mempersatukan pasangan calon pengantin beserta keluarga besar bergeser menjadi transaksi ekonomi murni.
Ketiga, ketidaksetaraan gender. Perempuan dianggap sebagai ‘barang mahal’ yang bisa dibeli. Padahal, sejatinya mas kawin adalah penghormatan. Keempat, konflik sosial. Perselisihan soal jumlah mas kawin sering memicu konflik antar-keluarga atau antar-marga.
Kelima, perubahan nilai. Generasi muda mulai mempertanyakan relevansi mas kawin dalam dunia modern. Pendeta Herman Saud dari GKI di Tanah Papua mengingatkan, mas kawin jangan sampai menjadi jerat hutang yang menghancurkan generasi muda. Mas kawin harus kembali kepada roh adat yaitu untuk mengikat kasih, bukan untuk memperjualbelikan manusia.
Pertanyaan penting ialah apakah mas kawin harus dihapus atau dilestarikan? Hemat penulis, mas kawin tetap relevan, tetapi tetap dalam konteks budaya dan adat-istiadat yang sehat dan berkeadilan.
Pelestarian nilai positif berupa penghargaan terhadap perempuan, solidaritas sosial, dan kebersamaan menjadi aspek utama dalam relasi budaya dan adat-istiadat warisan leluhur. Mas kawin tak mesti dijadikan beban ekonomi, tetapi simbol kasih sayang dan ikatan solidaritas antara kedua calon pengantin dan keluarga besar dua belah pihak.