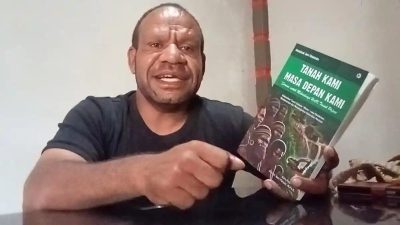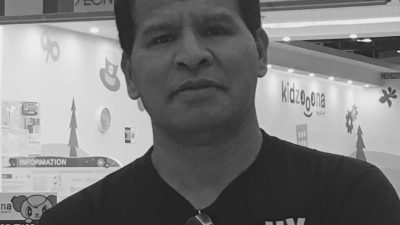Oleh Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran
SIAPAPUN yang melihat Papua hanya sebagai ujung peta akan terjebak dalam kedangkalan menilainya sebatas sebagai beban pembangunan.
Namun, siapa pun yang membaca Papua melalui data dan riset akan menyadari bahwa tanah ini adalah laboratorium alam dan kebudayaan, sekaligus ujian paling dalam atas mutu kenegarawanan kita.
Dan di situlah letak persoalannya, sebab hingga kini kita ternyata masih memandang Papua dengan cara keliru.
Papua menyimpan salah satu mozaik ekologi paling menakjubkan di muka bumi. Taman Nasional Lorentz, misalnya, diakui UNESCO sebagai kawasan lindung terbesar di Asia Tenggara dengan luas sekitar 2,35 juta hektare.
Kawasan ini menjadi warisan dunia karena memuat ekosistem lengkap, mulai dari pantai, rawa, hutan hujan dataran rendah, pegunungan, tundra alpina, hingga gletser tropis di Puncak Jaya.
Data konservasi menunjukkan Taman Nasional Lorentz menjadi habitat lebih dari 123 spesies mamalia yang mewakili 80 persen jenis mamalia di Tanah Papua, serta ribuan spesies tumbuhan endemik.
Di kawasan inilah burung Cenderawasih, Kasuari, hingga Kanguru pohon hidup berdampingan dalam satu bentang utuh, bukti bahwa Papua adalah bank keanekaragaman hayati yang nilainya setara dengan kawasan tropis terpenting dunia. Ia adalah bank penyangga kehidupan yang tidak memiliki padanan di wilayah lain di Indonesia (whc.unesco.org, 2025).
Beranjak ke laut, Lanskap Kepala Burung atau Semenanjung Doberai oleh para biolog disebut sebagai super hotspot keanekaragaman.
Jaringan kawasan konservasi laut di sini mencakup lebih dari 20 lokasi dengan luas gabungan sekitar 3,6 juta hektare, termasuk Raja Ampat, Teluk Cenderawasih, Kaimana, dan Fakfak.
Survei The Nature Conservancy dan Conservation International mencatat Raja Ampat memiliki lebih dari 600 spesies karang keras atau sekitar 75 persen dari total dunia, serta lebih dari 1.800 spesies ikan karang.
Publikasi di Marine Pollution Bulletin bahkan mengonfirmasi bahwa keanekaragaman ikan karang di Raja Ampat adalah yang tertinggi di dunia.
Fakta ini menunjukkan bahwa biodiversitas laut Papua bernilai strategis global, terlalu penting bila hanya direduksi sebagai sebuah objek wisata (nature.org, 2024).
Kekayaan mineral menambah bobot strategis Papua. Grasberg yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu tambang tembaga dan emas terbesar dunia, kini menjadi episentrum dinamika hilirisasi Indonesia.
Dampaknya langsung terasa pada arus ekspor konsentrat dan investasi smelter.
Data dari United States Geological Survey menempatkan Indonesia sebagai produsen tembaga utama dunia, dengan kontribusi terbesar justru berasal dari Grasberg di
Papua.
Pada 2024, pemerintah mengeluarkan izin ekspor bagi Freeport untuk mengirim ratusan ribu ton konsentrat tembaga, angka yang berpengaruh pada dinamika pasar global.
Dengan kata lain, tembaga dan emas dari Papua bukan hanya komoditas lokal, melainkan bagian dari rantai pasok industri dunia yang menentukan harga, biaya olah, dan investasi di berbagai negara.
Setiap kebijakan tentang Papua berhubungan langsung dengan posisi Indonesia dalam ekonomi mineral internasional (U.S. Geological Survey, 2025).
Papua juga merupakan jantung protein masa depan. Perairan Arafura memiliki potensi lestari perikanan pelagis kecil sekitar 468.000 ton per tahun, dengan dominasi famili clupeidae dan carangidae.
Kajian lain menambahkan potensi lestari udang, cumi, dan lobster di Arafura yang mencapai ratusan ribu ton per tahun.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa perairan ini adalah salah satu lumbung perikanan nasional.
Namun laporan juga menunjukkan praktik penangkapan ikan ilegal serta lemahnya pencatatan logbook kapal, mengindikasikan kebocoran hasil laut dalam jumlah besar.
Riset tentang pengelolaan demersal menegaskan pentingnya rezim penangkapan optimal berbasis bioekonomi serta efek kebijakan moratorium kapal asing terhadap rente ekonomi.
Tanpa disiplin saintifik dan koordinasi kelembagaan, kekayaan laut timur hanya akan berpindah ke buku kerugian sosial (Mongabay, 2022).
Di darat, hutan hujan Papua adalah benteng terakhir tutupan hutan primer Indonesia. Analisis citra satelit 2001–2019 menunjukkan laju deforestasi meningkat signifikan seiring pembangunan jalan Trans Papua dan ekspansi perkebunan besar, terutama kelapa sawit.
Proyeksi model memperingatkan bahwa jika izin perkebunan dan konsesi terus dikeluarkan tanpa kendali, fakta akan kehilangan hutan akan melonjak dalam dekade mendatang.
Laporan internasional mencatat, ketika laju kehilangan hutan di Sumatera dan Kalimantan menurun sejak 2016, justru tren ekspansi bergeser ke Papua.
Data ini memberi sinyal bahwa kebijakan tata ruang dan audit perizinan di Papua harus diperketat agar hutan tidak menjadi korban proyek jangka pendek (Mongabay, 2021).
Semua fakta ekologis ini berdampingan dengan kompleksitas manusia. Papua dihuni lebih dari 250 kelompok etnis dengan 300 bahasa lokal yang masih terjaga dari dulu hingga kini.
Penelitian demografi dan bahasa menunjukkan Papua adalah wilayah paling majemuk secara etnis di Indonesia.
Kajian linguistik terhadap bahasa kecil seperti Yonggom Wambon menegaskan bahwa setiap bahasa membawa pengetahuan ekologis, sejarah lisan, dan kosmologi unik. Hilangnya satu bahasa berarti hilangnya satu cara pandang terhadap dunia.
Fakta ini adalah hasil riset empirik, bukan retorika budaya belaka. Dengan ratusan bahasa yang dimiliki, Papua menjadi pusat penelitian linguistik dunia.
Artinya, kebijakan pembangunan Papua harus memperhitungkan keragaman bahasa dan budaya dalam desain pendidikan, kesehatan, dan layanan publik (kemendikdasmen.go.id, 2022).
Namun indikator sosial-ekonomi Papua memperlihatkan paradoks nyata. Data BPS Papua (Maret 2025) mencatat angka kemiskinan 19 persen, jauh di atas rata-rata nasional di bawah 10 persen.
BPS Papua Selatan bahkan melaporkan hampir 20 persen penduduk miskin pada periode sama. Indeks Pembangunan Manusia Papua 2024 juga masih berada di papan bawah.
Publikasi resmi BPS menegaskan ketertinggalan ini melalui indikator inflasi, pertumbuhan, ketimpangan, dan tenaga kerja.
Artinya, meski memiliki cadangan mineral, biodiversitas, dan potensi laut, ternyata kesejahteraan rakyat Papua tidak beranjak naik.
Riset panel data 2021–2023 menyebut jumlah penduduk miskin sebagai variabel paling signifikan yang menjelaskan kondisi sosial ekonomi di Papua. Dengan kata lain, akar masalah Papua adalah kemiskinan struktural, bukan sekadar minim infrastruktur.
Persoalan pendidikan memperlihatkan gambaran lebih rinci. UNICEF melaporkan tingginya ketidakhadiran guru di sekolah-sekolah Papua, yang berdampak pada rendahnya literasi dan numerasi anak-anak sejak dini. Kesenjangan makin parah karena keterbatasan listrik dan internet.
Program digitalisasi pendidikan tanpa perbaikan masalah dasar hanya akan memperlebar jurang. Karena itu, kebijakan pendidikan di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain.
Diperlukan skema afirmatif untuk rekrutmen guru lokal, pelatihan transisi literasi bahasa ibu ke bahasa Indonesia, dan perbaikan infrastruktur dasar sekolah. Dimensi sejarah Papua juga terikat pada data politik yang tidak bisa dihapus.
Sejak sidang BPUPKI 1945, Papua sudah diperdebatkan: sebagian tokoh bersikeras memasukkannya ke dalam Indonesia, sebagian lain meragukannya karena dianggap berbeda secara geografis dan etnografis (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1998).
Perdebatan ini berlanjut pada Konferensi Meja Bundar 1949, ketika Belanda menolak menyerahkan Papua meski mengakui kedaulatan Indonesia atas bekas Hindia Belanda.
Konflik baru berakhir lewat Perjanjian New York 1962, yang menyerahkan Papua kepada UNTEA sebelum masuk ke Indonesia pada 1963.
Namun, Penentuan Pendapat Rakyat 1969 tetap kontroversial karena hanya melibatkan perwakilan terbatas (UN Document A/7723). Fakta-fakta ini menegaskan Papua sejak awal berada di persimpangan sejarah dan politik.
Sejarah tidak boleh dijadikan alibi untuk mengabaikan Papua, sebaliknya ia menuntut koreksi jujur dan keberanian kenegarawanan hari ini.
Jika seluruh fakta itu dijahit menjadi satu kebijakan, ujungnya adalah arah baru yang berpijak pada data empirik, melindungi yang rentan, dan menolak akumulasi kepentingan sempit demi keadilan sosial-ekonomi jangka panjang.
Maka, tak ada pilihan lain, kebijakan harus diterjemahkan ke dalam mandat-mandat strategis yang jelas. Pertama, mandat ekologis harus tegas. Taman Nasional Lorentz dan Lanskap Kepala Burung harus diperlakukan sebagai infrastruktur alam nasional setara jalan, bandara, dan smelter.
Instrumen kebijakan berupa moratorium izin di bentang konservasi tinggi, penataan ulang konsesi tumpang tindih, serta pembiayaan berbasis hasil untuk desa adat penjaga hutan adalah langkah minimal agar bank kehidupan ini tidak menjadi kolateral proyek sesaat.
Kedua, mandat manusia sama penting. Angka kemiskinan dan IPM menuntut layanan dasar yang sesuai geografi sosial Papua. Perekrutan dan penempatan guru, tenaga kesehatan, serta penyuluh dari komunitas lokal harus diperkuat lewat skema afirmatif.
Ekosistem pembelajaran mesti mengakui keragaman bahasa, sehingga transisi literasi dari bahasa ibu ke bahasa Indonesia dirancang dengan dukungan pelatihan guru, materi ajar, dan partisipasi orang tua. Ketiga, mandat maritim membuka ruang kemakmuran jika tata kelola diperketat.
Stok pelagis dan demersal Arafura cukup untuk menopang ekonomi pesisir bila dilindungi dari praktik ilegal. Peningkatan kepatuhan pelaporan, modernisasi pelabuhan, serta pengawasan terintegrasi antarlembaga menjadi tiga sumbu yang saling mengunci. Data potensi lestari sudah ada, cetak biru penertiban tersedia.
Kurangnya hanyalah konsistensi menutup kebocoran hasil laut yang mencapai seperempat hingga sepertiga tidak tercatat.
Keempat, mandat nilai menuntut cara pandang baru terhadap pengetahuan. Selama puluhan tahun ratusan publikasi tentang biodiversitas, bahasa, antropologi, kesehatan publik, ekonomi, dan tata kelola hutan di Papua dihasilkan. Namun, sebagian besar berakhir sebagai sitasi akademik atau koleksi perpustakaan.
Diperlukan arsitektur penerjemah kebijakan yang menghubungkan kampus, balai riset, komunitas adat, dan pemerintah daerah dengan dukungan anggaran yang memadai.
Model pemantauan jejaring kawasan konservasi Lanskap Kepala Burung membuktikan data ekologis dan sosial dapat dipakai untuk evaluasi kinerja berulang dan koreksi strategi. Pendekatan ini bisa diperluas ke sektor pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.
Pada akhirnya, alasan strategis mengapa Papua harus menjadi atensi utama negara tersusun rapi di atas bukti. Ia adalah bank hayati yang menjaga iklim regional, simpul maritim dan protein yang menopang kedaulatan pangan, penentu posisi tawar dalam rantai mineral dan energi transisi, rumah bagi ratusan bahasa dan budaya yang memperkaya republik, sekaligus ruang sejarah yang menuntut pemulihan martabat.
Membiarkan Papua berjalan di jalur lama berarti menukar masa depan dengan catatan kehilangan. Sebaliknya, mengelola Papua secara benar berarti menempatkan manusia dan alam di pusat keputusan, lalu membiarkan data memandu langkah, bukan sekadar omon-omon.
Bukti ada di hadapan kita, waktu kian singkat, dan pilihannya hanya satu: beranjak dari retorika menuju keberanian bertindak memperbaiki yang masih tersisa. Betapa dungunya kita jika terus abai pada bukti dan kekayaan luar biasa pemberian Tuhan ini.
Sumber: Kompas.com, 21 Agustus 2025