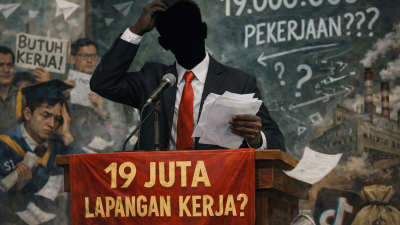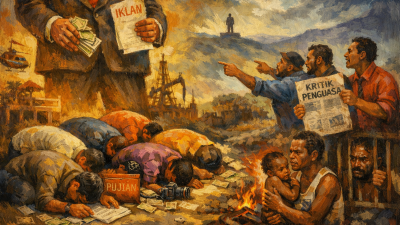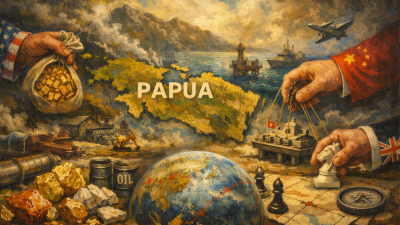LONGSOR di KM 138 jalan Trans Papua Nabire – Ilaga dan membuat arus orang dan barang tersendat, menyingkapkan beberapa kenyataan. Kejadian ini mestinya dikaji secara serius. Putusnya jalan itu membuka kenyataan bahwa rantai pasokan logistik wilayah dataran tinggi Papua Tengah saat ini bergantung sepenuhnya pada jalur darat. Tiadanya alternatif lain sejauh ini membuktikan bahwa kawasan pegunungan cenderung rentan.
Pertama, ketersediaan listrik di tiga kabupaten (Paniai, Deiyai, dan Dogiyai) bergantung 100 persen pada suplai BBM dari Depo Pertamina Nabire. Putusnya jalan membuat truk pengangkut BBM tidak bisa menyuplai ke sana. Pembangkit listrik di Deiyai tidak bisa beroperasi. Pasokan listrik putus.
Padahal pasokan listrik ini mutlak dibutuhkan oleh pusat-pusat layanan umum seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah-sekolah, kantor pemerintah, kantor-kantor swasta, dan lain-lain. Tindakan-tindakan operasi bisa gagal dilakukan karena tidak ada listrik. Vaksin-vaksin bisa rusak karena mesin penyimpan tidak berfungsi.
Bagaimana seandainya ada bayi yang lahir darurat dan memerlukan incubator? Penanganan cepat untuk penyelamatan sulit untuk dilakukan. Tanpa listrik alat-alat di rumah sakit menjadi tidak banyak fungsinya. Dokter-dokter pun kesulitan untuk bisa menolong secara optimal. Semakin lama waktu perbaikan jalan yang putus, kondisi-kondisi yang lebih buruk menjadi semakin mungkin terjadi.
Kedua, pasokan pangan untuk wilayah dataran tinggi sangat bergantung pada suplai dari Nabire. Ketika jalan itu putus, pasokan pangan sulit untuk naik. Mungkin bukan hanya pangan tetapi juga obat-obatan. Sebagian air minum juga dikirim dari Nabire, utamanya air minum dalam kemasan. Begitu juga ayam-ayam pedaging yang diternak di Nabire dan sebagian dipasarkan ke wilayah tiga kabupaten di atas.
Pasokan pangan dari Nabire ini sangat vital. Lebih-lebih untuk bahan pangan yang tidak diproduksi di wilayah setempat, tetapi sepenuhnya bergantung pada suplai dari luar. Misalnya, beras, ikan laut, daging, dan produk olahan lain. Sebab, di wilayah ini suplai bahan pangan ini betul-betul hanya lewat satu pintu masuk saja, yaitu jalur trans Papua yang sementara ini sedang putus.
Ketika jalan putus, stok menipis. Harga-harga bisa melambung jauh. Tentu saja ini menekan kemampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka. Akses penduduk terhadap pangan tiba-tiba menyempit.
Ketiga, penanganan longsor di KM 138 tidak secepat yang diharapkan oleh masyarakat. Siapa yang sebetulnya memikul tanggung jawab untuk menangani bencana di titik ini? Situasi darurat selalu menuntut respon yang cepat. Maka perlu juga pemerintah mengantisipasi kejadian-kejadian semacam ini di masa depan.
Respon yang lambat, bahkan di awal-awal tidak ada kejelasan siapa yang akan menangani, membuka satu tabir bahwa pemerintah kita masih kurang responsive; bahwa kemampuan tanggap darurat bencana masih perlu dipupuk; dan bahwa sistem peringatan awal bencana juga perlu dibikin.
Apakah keterlambatan penanganan ini berkaitan dengan pemahaman bobot urgensi ketika jalur terpotong, masih harus diperiksa lebih lanjut. Memang akan sangat disesalkan seandainya pemerintah tidak mempertimbangkan bobot serius putusnya jalan ini.
Selama ini kita cenderung mendengar normalisasi berulang tentang kendala geografis wilayah-wilayah dataran tinggi di Papua. Cerita tentang kehidupan masyarakat yang berada dalam berbagai keterbatasan terus disiarkan dan diterima sebagai kondisi yang wajar.
Masyarakat, bersama dengan pemerintahnya, mesti terus berupaya mengubah pandangan itu. Untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyat Papua akses transportasi yang baik sangat dibutuhkan. Begitu juga jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi dan internet, jaringan listrik dan ketersediaannya, layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, layanan perlindungan hak-hak sipil mereka.
Keempat, masyarakat di wilayah tiga kabupaten: Dogiyai, Deiyai, dan Paniai dapat dikatakan berada dalam posisi rentan. Mereka sejauh ini hanya memiliki satu akses keluar masuk yang dapat ditempuh, yaitu jalan darat ke Nabire. Sebenarnya, titik akses yang lain sudah tersedia yaitu penerbangan dari Deiyai, Dogiyai, dan Paniai. Akan tetapi layanan transportasi udara tidak bisa diakses secara rutin dan untuk banyak orang.
Komoditas yang dihasilkan oleh penduduk di tiga wilayah ini, ketika jalan putus, sulit untuk dikirim ke Nabire. Ubi, sayur-mayur, ternak, kopi, dan komoditas pertanian lain tidak dapat keluar. Seandainya produk itu tidak terserap oleh pasar lokal, produk itu membusuk. Para petani rugi. Arus yang sebaliknya juga sendat. Komoditas dari Nabire tidak bisa sampai ke tiga kabupaten di atas.
Kenyataan bahwa tiga kabupaten ini paling mungkin diakses hanya lewat satu jalur memperlihatkan bahwa mereka rentan. Tidak ada alternatif yang lain ketika satu pintu itu tertutup. Wilayah itu langsung tertutup. Orang-orang di sana langsung terisolasi.
Apabila kerentanan ini terus diabaikan, bahkan tidak disadari, masyarakat di dataran tinggi akan terancam. Kita harus belajar dari sejarah. Pada tahun 2008 terjadi wabah diare di Dogiyai. Ratusan orang meninggal. Pertolongan medis pada waktu itu sangat terlambat. Akses transportasi ke Nabire, yang dianggap memiliki layanan kesehatan lebih baik, belum tersedia secara memadai. Ugidimi, Dogimani, dan kampung-kampung yang lain di sekitarnya juga tidak memiliki jalur komunikasi ke luar yang baik pada tahun itu.
Pelayanan medis setempat belum mumpuni. Banyak orang tidak sempat mendapatkan pertolongan medis sampai saat meninggalnya karena aneka keterbatasan. Perawat dan dokter belum banyak. Fasilitas layanan perawatan juga masih sedikit. Obat-obatan masih belum tersedia cukup.
Sejarah buruk itu mungkin tidak akan terjadi semengerikan itu apabila kondisi wilayah Dogiyai sudah terbuka, dapat diakses dari mana-mana. Atau, jika saat itu layanan medis sudah melimpah sehingga dokter dan perawat cukup, laboratorium andal, obat-obatan terdapat di depan mata, dan jalur transportasi baik darat dan udara sudah lebih baik.
Bencana seperti tahun 2008 di Dogiyai semoga tidak berulang. Namun, harapan ini tidak cukup hanya digaungkan. Ada banyak pekerjaan yang mesti diberesi untuk menyediakan lingkungan yang mendukung kehidupan berkualitas. Ruas jalan yang putus di KM 138 itu membuka mata dan budi kita. Pemerintah harus lebih serius mengantisipasi bencana yang dapat terjadi sebagai dampak dari kondisi ini.
Para intelektual setempat dapat mengambil peran untuk membantu pemerintah dengan memperkuat masyarakat basis agar lebih berdaya: memproduksi pangan lokal sehingga tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar, mengolah air bersih untuk menjadi siap konsumsi, memperkuat layanan medis —menambah jumlah dan kemampuan para tenaga medis.
Juga tidak kalah penting adalah membuat terobosan untuk cadangan energi listrik. Apakah akan terus bergantung pada pembangkit bertenaga diesel di Deiyai? Apakah sudah saatnya untuk bekerja lebih keras melanjutkan proyek pembangkit listrik tenaga air di Urumuka yang pernah dimulai beberapa tahun lalu? (*)