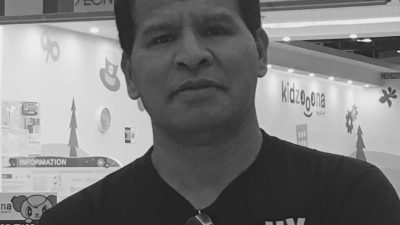Oleh Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran
BAGAIMANA masyarakat Papua terintegrasi ke dalam komunitas Kristen dunia dalam waktu yang relatif tidak lama sejatinya mengandung banyak pelajaran bagi Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Sejak pertama kali Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler menginjakkan kaki di tanah Papua di tahun 1855 sampai saat ini, proses integrasi tersebut terus berlanjut.
Hebatnya, dinamika perjalanan penyebaran agama Kristen di Papua relatif baik dan mulus. Nyaris tidak ada gejolak yang berarti apalagi konflik. Bahkan kehadiran agama Kristen sampai detik ini oleh mayoritas orang Papua tetap dianggap sebagai bagian dari “berkah” terbesar yang pernah diterima oleh Papua.
Sangat berbeda dengan kehadiran Indonesia sebagai sebuah entitas negara bangsa di Papua, yang justru hingga saat ini dianggap sebagai “masalah” dan bahkan oleh sebagian aktivis garis keras dikatakan sebagai “petaka” bagi sebagian masyarakat Papua.
Pasalnya, proses integrasi Papua ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak dijalankan layaknya proses integrasi masyarakat Papua ke dalam komunitas Kristen itu, baik nasional maupun internasional.
Indonesia datang dan berusaha bertahan di hati masyarakat Papua dengan cara-cara yang sebagaimana dikatakan aktivis Papua sebagai kurang manusiawi dan etis di satu sisi dan lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Papua di sisi lain.
Memang dua hal ini tidak bisa secara persis disamakan dan dibandingkan. Tapi secara substansial, ada hal-hal yang bisa dikaitkan, diperbandingkan, sekaligus diperdebatkan mengapa salah satunya terbukti sangat berhasil dan yang lainnya justru masih berjibaku dengan masalah demi masalah yang kian hari rasanya malah kian kusut plus semrawut.
Untuk itu, dalam konteks ini, beberapa catatan tentang keberhasilan penyebaran agama Kristen dan kinerja para misionaris di Papua perlu dibuat, terutama catatan untuk Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang sampai hari ini masih tetap menempatkan tanah Papua sebagai bagian dari NKRI.
Pertama, Kristen dan para misionaris datang ke Papua dengan niat baik berlandaskan tanggung jawab profetik berkerangka nurani yang tulus. Konsistensi niat dan tanggung jawab profetik tersebut senantiasa terjaga dari waktu ke waktu.
Mereka tidak saja datang untuk menyebarkan ajaran Nasrani dan menebar kasih sayang, tapi juga ingin melakukan perubahan sosial di Papua ke arah yang jauh lebih baik.
Pembangunan gereja-gereja dimaksudkan bukan saja untuk menjadi pusat-pusat penyebaran agama, tapi juga untuk menjadi pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi dengan tujuan utama untuk menjadikan masyarakat Papua jauh lebih beradab di satu sisi dan semakin memiliki harga diri yang setara dengan seluruh umat manusia di dunia di sisi lain.
Sementara Indonesia datang ke Papua; dan lagi-lagi mengutip istilah para aktivis, dengan ambisi “kerakusan kelas dewa” berbalutkan kemunafikan, dibingkai dengan “senjata persatuan dan kesatuan” yang berbahan dasar “mesiu” plus “pelatuk senjata”.
Indonesia mengaku datang dengan niat yang dinarasikan baik, tapi hingga hari ini orang Papua justru masih merasa dikhianati karena narasi baik tersebut nyatanya termanifestasikan secara tanpa malu-malu ke dalam tindakan “eksploitasi SDA Papua” dan “rasialisme akut”.
Ibaratnya, Indonesia datang membawa bendera persaudaraan, menebar narasi bahwa Papua menjadi salah satu titik di dalam garis persaudaraan tersebut, tapi nyatanya Indonesia memancangkan tiang bendera persaudaraan tersebut tepat di ubun-ubun alias di atas kepala orang-orang Papua sendiri.
Walhasil, sekujur tubuh dari tanah Papua “berdarah-darah”, hanya untuk menopang bendera persaudaraan yang dibawa dari tanah Jawa. “Darahnya” terus menetes hingga hari ini di atas tanah orang Papua sendiri, begitu juga dengan rasa sakitnya yang nyaris sangat sulit untuk diobati.
Tapi sumber daya alam dan segala kekayaan orang Papua justru terus mengalir ke Jakarta, dinikmati oleh Jakarta atas nama kepentingan negara bangsa bernama Indonesia, meskipun di dalam prakteknya hanya dinikmati oleh segelintir pihak yang dalam pandangan saya sampai hari ini tidak pernah merasa bersalah kepada orang Papua.
Kedua, misionaris menggunakan bahasa kasih sayang dan persaudaraan dalam makna yang sebenar-benarnya. Toh memang bahasa yang demikian menjadi bagian integral dari ajaran Kristen itu sendiri.
Artinya, misionaris Kristen secara konsisten menerapkan ajaran agamanya di Papua, tidak saja di dalam praktek perorangan, tapi juga di saat mengintegrasikan Orang Papua ke dalam agama Kristen.
Para misionaris berhasil secara faktual menjadikan orang Papua sebagai saudara kandung mereka, merangkul orang Papua ke dalam rumah besar “Kristen” yang penuh dengan kasih sayang, dan menyajikan makanan layaknya makanan yang dimakan sehari-hari oleh para misionaris, tanpa diskriminasi dan tanpa tendensi rasial sedikit pun.
Sementara Indonesia datang ke Papua menggunakan bahasa kekuasaan yang “arogan” berlatarkan senjata dan aturan-aturan “Jawa” yang sangat hirarkis. Di saat para misionaris berhasil “menjadi Orang Papua” di dalam mendekati masyarakat Papua, pemerintah Indonesia justru berhasil meniru peran “Belanda” di Indonesia, yakni menjadi “penjajah baru” di tanah Papua.
Ketika Belanda mulai ingin mengubah pendekatannya di Papua dengan menawarkan negara merdeka bagi Papua Barat, Indonesia justru berhasil menggagalkan rencana tersebut, tapi tidak berhasil membangun harapan baru untuk menggantikan harapan kemerdekaan yang telah terlanjur dijanjikan oleh Belanda kepada Papua Barat itu.
Saya yakin, di kalangan orang Papua sempat muncul harapan kala itu tentunya, di mana Indonesia diharapkan bisa memberikan masa depan yang lebih baik kepada Papua dan orang-orang Papua akan diperlakukan oleh Jakarta sama dan setara dengan orang Indonesia di berbagai daerah NKRI lainnya.
Pun Indonesia diharapkan bisa tampil dengan sensitifitas lokal yang tinggi, meninggalkan “logat dan langgam” Jawa di Papua alias bangga menggunakan “seragam Papua” di tanah Papua sendiri. Namun faktanya lagi-lagi tidaklah demikian. Bahasa Jakarta adalah bahasa kekuasaan, yang dimunculkan dalam logat dan langgam kekerasan, moncong senjata, dan kebijakan-kebijakan eksploitatif.
Bukan hanya orang Papua yang tersinggung, bahkan tersakiti dengan bahasa kekuasaan yang demikian. Aceh pernah mengalaminya dan sampai hari ini rasa dan aspirasi untuk tidak lagi bersedia bersama dengan Indonesia masih sangat besar di banyak kalangan orang Aceh, baik yang masih berada di Aceh maupun yang sudah bertahun-tahun berada di luar negeri.
Jelang akhir tahun 1950an, PRRI Permesta sejatinya juga hadir dalam konteks yang tak jauh berbeda, yakni tuntutan perlakuan yang lebih adil dari Jakarta atas daerah-daerah yang masuk ke dalam pergerakan PRRI, yakni sebagian dari Sumatera dan Sulawesi, meskipun ujung ceritanya tak sama.
Ketiga, Kristen datang untuk membawa misi perubahan sosial dan harapan atas penghidupan yang lebih baik di masa mendatang dan di kehidupan yang damai setelah kehidupan dunia. Misi perubahan sosial Kristen di Papua dilandasi sebenar-benarnya oleh kemanusian yang adil dan beradab.
Kristen menebar semangat perubahan sosial berbasiskan kepentingan orang Papua sendiri, bukan atas kepentingan orang Kristen di Jerman atau di Eropa bahkan Amerika. Karena itu, para misionaris di Papua fokus untuk membangun “manusia-manusia” Papua yang akan bertanggung jawab atas dirinya, agamanya, dan bangsa serta negaranya.
Selain gereja, sekolah-sekolah dihadirkan bersama dengan tenaga pendidik yang berkualitas sekaligus sangat memahami orang dan tradisi Papua, rumah-rumah sakit dibangun, fasilitas publik dihadirkan, termasuk bandara-bandara untuk konektivitas.
Para misionaris Kristen mendatangkan begitu banyak modal dari luar untuk ikut membangun Papua, bukan sebaliknya, bukan mencuri dari Papua untuk pengayaan Jakarta dan aktor-aktor elitnya.
Fakta-fakta ini menjadi faktor yang sangat meyakinkan (convincing factors) di mata orang Papua atas ketulusan para misionaris di dalam melakukan perubahan sosial di tanah Papua.
Sementara Indonesia dan Jakarta lebih banyak mengambil, atau bisa juga oleh kalangan aktivis disebut ‘mencuri’ dari tanah Papua ketimbang memberi. Itu pun dilakukan dengan seminimal-minimalnya “feedback” untuk orang Papua. Indonesia enggan membangun kemandirian di Tanah Papua sebagaimana yang dilakukan oleh para misionaris.
Indonesia tidak menanamkan spirit “berdiri di atas kaki sendiri” di Papua, sebagaimana dikampanyekan oleh para pemimpin-pemimpin Indonesia sejak dulu di panggung nasional. Yang dilakukan Indonesia adalah mengeksploitasi segala kekayaan yang ada di tanah Papua, lalu membawanya ke Jakarta, mengubahnya menjadi “harta kekayaan Jakarta”, dan implisit mengajarkan orang Papua untuk mengemis agar mendapatkan bagiannya.
Jakarta membangun jembatan ketergantungan berbalutkan emas dari Gunung Ertsberg terhadap Papua, sehingga seolah-olah kekayaan tanah Papua adalah sepenuhnya milik orang Jakarta. Ketika orang Papua ingin mendapatkan haknya, mereka harus terlebih dahulu memakai “baju” Jakarta, mengikuti segala keinginan Jakarta, dan menjalankan resep-resep perubahan sosial ala Jakarta di Papua.
Jika tidak, maka bahasa “permusuhan” dari kekuasaan akan digunakan oleh Jakarta, yakni pelabelan “pemberontak, teroris, pengganggu stabilitas keamanan, preman, dan seterusnya”.
Bahasa lain dari kekuasaan semacam ini, di mana pun di dunia, akan menimbulkan fragmentasi sosial. Yang lemah dan sudah terlanjur sangat tergantung kepada Jakarta akan mengikuti kehendak pemilik kuasa tersebut sampai ke mana pun. Tapi yang berhasil bertahan untuk tidak tergantung kepada Jakarta akan melawan dan akan bersedia menerima label apa pun yang diberikan oleh Jakarta.
Dan itulah yang terjadi pada hari ini. Jakarta memang masih menikmati cukup banyak ketergantungan orang Papua atas skema “jembatan emas ketergantungan” yang sudah dibangun oleh Jakarta sejak dahulu. Tapi di sisi lain, para pihak yang menganggap “jembatan emas ketergantungan” tersebut sebagai senjata pemusnah Papua juga semakin banyak.
Para pihak ini semakin hari semakin yakin bahwa dunia ini luas, ada banyak kawan di luar sana yang bisa diajak untuk duduk bersama dan mendengarkan dengan baik segala keluhan orang Papua, tidak hanya Jakarta. Dan sepanjang pengamatan saya, aksi pembangunan jejaring internasional tersebut terus berjalan hingga hari ini, bahkan malah semakin membesar.
Sehingga tak ada jaminan bagi Indonesia di dalam waktu lima, sepuluh, lima belas, atau dua puluh tahun mendatang, dunia akan tetap bersama dengan Indonesia di dalam masalah penyelesaian konflik di Papua
Pendeknya, di sini saya hanya ingin menegaskan bahwa saya sangat meyakini NKRI adalah sebaik-baiknya negara bangsa untuk Papua berdiri dan maju. Tapi di sini saya juga ingin menegaskan bahwa Indonesia harus berani melakukan perubahan strategis yang fundamental di dalam mempertahankan Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia.
Tak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pembelajaran agar ke depan Indonesia bisa lebih baik di dalam merangkul Papua. Contoh nyata sudah dihadirkan oleh para misionaris Kristen di Papua sejak lebih dari satu abad lalu.
Tidak ada salahnya strategi dan pendekatan misionaris Kristen ini diadaptasi, disesuaikan dengan konteks sebuah negara bangsa, dan dipraktekkan secara konsisten sesegera mungkin, agar Papua dan orang Papua bisa benar-benar menikmati statusnya sebagai “saudara kandung” dari orang Indonesia lainnya dan merasa memang sepantasnya menjadi bagian dari NKRI. Semoga!