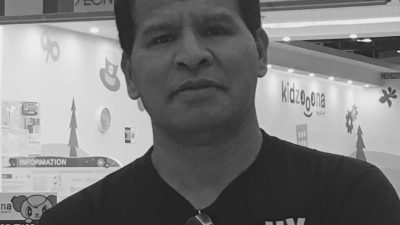Oleh Imanuel Gurik
Doktor Ilmu Ekonomi lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua
OTONOMI Khusus (Otsus) Papua adalah kebijakan monumental yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk penghormatan, pengakuan sekaligus jalan afirmasi untuk orang asli Papua (OAP). Kebijakan otsus Papua tercover dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Kemudian, mengalami revisi kedua melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Implementasi kebijakan ini diikuti dengan aliran dana sangat besar dan peluang kelembagaan untuk mengubah wajah pembangunan Papua.
Namun, pertanyaan besar yang selalu muncul ialah sejauhmana otsus benar-benar menyentuh kehidupan orang asli Papua di kampung-kampung, baik di wilayah pegunungan yang terjal maupun di pesisir yang terpencil? Banyak orang asli Papua merasa haru ketika kebijakan negara mulai masuk ke wilayah perkampungannya. Rasa haru itu lahir karena selama puluhan tahun mereka merasa jauh dari sentuhan pembangunan.
Namun, perasaan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa masih banyak kebijakan otsus di level implementasi yang belum dilakukan secara maksimal. Otsus tidak cukup hanya hadir dalam bentuk regulasi dan kucuran dana, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dengan pola baru yang berangkat dari data riil dan kebutuhan masyarakat.
Harapan dan Realitas
Masyarakat Papua khususnya orang asli hidup dalam kondisi geografis yang penuh tantangan. Masyarakat di pegunungan menghadapi keterisolasian transportasi, keterbatasan pelayanan kesehatan serta minimnya akses pendidikan. Sementara masyarakat pesisir sering bergulat dengan keterbatasan pasar, infrastruktur pelabuhan hingga akses ekonomi yang tidak stabil.
Meskipun dana otsus sudah mengalir namun masih banyak cerita haru yang terdengar. Misalnya, anak-anak harus berjalan kaki berjam-jam untuk sekolah, ibu-ibu melahirkan tanpa tenaga medis, petani kopi atau nelayan menjual hasilnya dengan harga rendah jauh di bawah hingga absennya akses pasar. Realitas inilah yang membuat orang asli Papua sering berkata bahwa mereka terharu bukan karena sudah sejahtera, melainkan karena masih ada perhatian dari negara meskipun belum sepenuhnya mengubah keadaan.
Salah satu kelemahan mendasar dalam implementasi otsus adalah minimnya basis data yang akurat mengenai orang asli Papua di setiap kampung. Banyak kebijakan dibuat tanpa pemetaan sosial-ekonomi yang mendalam. Akibatnya, program tidak tepat sasaran atau berhenti di tataran administratif. Di sinilah peran penting aparatur sipil negara (ASN) menjadi kunci. ASN bukan sekadar birokrat tetapi harus menjadi ujung tombak yang memahami kehidupan orang asli Papua secara nyata. Setiap ASN, terutama di daerah harus memiliki data yang komprehensif.
Dapat dimaksud sebagai berikut. Pertama, jumlah dan sebaran orang asli Papua di setiap kampung (the number and distribution of indigenous Papuans in each village). Kedua, tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga (the level of education, health, and family economy). Ketiga, akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, sekolah, dan Puskesmas. (access to basic infrastructure such as roads, clean water, electricity, schools, and health centers).
Keempat, potensi ekonomi lokal hasil kebun, laut, hutan, tambang rakyat (local economic potential such as agriculture, fisheries, forestry, and small-scale mining). Tanpa data ini, kebijakan hanya akan menjadi rumusan di atas kertas. Dengan data, ASN dapat memastikan bahwa setiap program otsus benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan.
Pola Baru
Untuk menjawab kerinduan orang asli Papua diperlukan pola implementasi baru otsus yang lebih humanis, berbasis data, dan menyentuh akar kehidupan rakyat. Beberapa pola inspiratif yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut. Pertama, kampung sebagai sentra layanan dasar. Setiap kampung harus menjadi pusat pelayanan minimal. Sekolah dasar, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan akses pasar kecil wajib tersedia. Hal ini mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus berjalan jauh untuk mendapat layanan dasar.
Kedua, ASN sebagai pendamping rakyat. ASN harus ditempatkan secara strategis untuk mendampingi masyarakat. Guru harus benar-benar hadir di kelas, tenaga kesehatan melayani di puskesmas, dan penyuluh pertanian membantu petani di kebun. ASN harus menjadi “wakil negara” yang hidup bersama rakyat. Ketiga, dana otsus berbasis data dan kinerja. Alokasi dana otsus ke daerah harus disesuaikan dengan data riil kampung, baik jumlah pendudukan orang asli Papua dan kondisi daerah serta dan capaian kinerja pembangunan. Daerah yang berhasil meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat patut mendapatkan dukungan lebih.
Keempat, integrasi budaya lokal. Pola baru tidak boleh mengabaikan nilai budaya orang asli Papua. Program pembangunan harus memperkuat identitas lokal. Misalnya, mendorong pertanian keladi, ubi, dan kopi atau melibatkan gereja dan tokoh adat dalam penyuluhan kesehatan. Kelima, monitoring dengan indikator kesejahteraan. Keberhasilan otsus harus diukur dari peningkatan kesejahteraan OAP, bukan sekadar serapan anggaran. Indikator yang relevan antara lain penurunan angka gizi buruk, peningkatan melek huruf serta bertambahnya jumlah rumah layak huni.
Kerangka NKRI
Otsus adalah jalan tengah untuk memastikan Papua tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan penghormatan terhadap kekhususan orang asli Papua. Namun, NKRI tidak boleh hanya menjadi slogan. Bagi orang asli Papua NKRI harus hadir dalam kenyataan sehari-hari. Pertama, di rumah mereka, dengan listrik, air bersih, dan rumah sehat, Di sekolah mereka, dengan guru dan fasilitas layak. Kedua, di ladang dan laut mereka, dengan akses pasar dan harga yang adil.
Ketiga, di pusat layanan kesehatan mereka, dengan tenaga medis dan obat yang tersedia. Keempat, jika ini terwujud, maka NKRI tidak hanya dirasakan dalam simbol, melainkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, inspirasi kebijakan yang dapat menjadi pegangan. Pertama, mewajibkan setiap ASN memiliki dan memperbarui data OAP di wilayah kerjanya (require every civil servant to have and regularly update indigenous Papuan such as data within their area of work).
Kedua, membangun sistem database orang asli Papua berbasis kampung yang terintegrasi dengan sistem perencanaan daerah (develop a village-based indigenous Papuan database system integrated with regional planning systems). Ketiga, distribusi dana otsus berbasis data kebutuhan dan capaian pembangunan nyata (distribute special autonomy funds based on actual development needs and achievements). Keempat, dorong kolaborasi pemerintah, adat, dan gereja sebagai mitra implementasi program (promote collaboration between government, traditional leaders, and the church as partners in program implementation).
Kelima, melibatkan generasi muda orang asli Papua dalam pengelolaan pembangunan berbasis teknologi dan inovasi (involve young indigenous Papuan generations in development management through technology and innovation). Dengan inspirasi ini, otsus akan bergerak dari sekadar dana menjadi mesin transformasi sosial-ekonomi yang mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Mereka telah lama hidup dengan kerinduan akan hadirnya pembangunan yang menyentuh mereka secara nyata.
Orang asli Papua terharu ketika negara hadir meski hanya dalam bentuk kecil. Namun, sudah saatnya air mata haru itu berubah menjadi senyum harapan karena orang asli Papua benar-benar merasakan peningkatan kualitas hidup. ASN adalah ujung tombak yang dapat memastikan hal ini.
Dengan data yang akurat dengan keberanian hadir di kampung serta dengan komitmen tulus implementasi otsus bisa diarahkan pada pola baru yang efektif. Otsus adalah kesempatan besar untuk membuktikan bahwa NKRI hadir bukan hanya melalui regulasi tetapi melalui kehidupan sehari-hari orang asli Papua yang semakin sejahtera, mandiri, dan bermartabat.