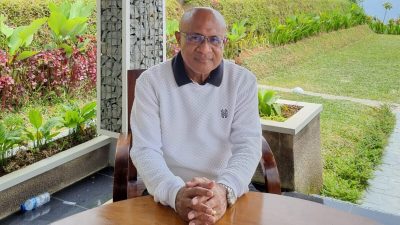Oleh Yosua Noak Douw
Doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua
MELIHAT Papua dari dekat, bukan dari peta. Jangan melihat Papua dari Jakarta. Frasa ini sederhana tetapi sarat makna dan menjadi diskusi di ruang publik, khususnya di tanah Papua. Ia adalah peringatan moral bagi para pemimpin dan elit bangsa ini agar tidak memandang Papua sekadar titik kecil di atas peta atau statistik dalam laporan kementerian dan lembaga di pusaran kekuasaan. Karena dari kejauhan, yang tampak hanyalah angka dan peta; bukan wajah, bukan air mata dan tawa anak-anak di Pegunungan Papua, misalnya.
Melihat Papua dari dekat berarti menjejak tanahnya, menyentuh realitasnya, dan memahami kompleksitas kehidupan di balik gunung dan lembah yang jauh dari pusat kekuasaan setiap berganti rezim. Papua tidak bisa didefinisikan dengan logika tunggal pembangunan nasional. Ia punya konteks, irama, dan sejarah sendiri. Di sini, pembangunan bukan sekadar beton dan angka pertumbuhan, tetapi tentang martabat manusia dan harapan yang hidup di tengah keterbatasan.
Tak berlebihan peringatan: jangan samakan Papua dengan pulau lain muncul di tengah masyarakat bumi Cenderawasih. Atau jangan ada penyamaan definisi antara Jakarta dan pulau lain di Indonesia dengan tanah Papua. Papua tidak bisa diseragamkan. Alamnya keras, budayanya lembut, dan masyarakatnya hidup dalam filosofi keseimbangan antara manusia dan alam. Di banyak tempat di tanah Papua, jalan bukan sekadar sarana transportasi. Ia simbol keterhubungan antar dunia. Ketika jalan tidak ada, bukan hanya ekonomi yang terputus, tetapi juga rasa kebersamaan dan akses terhadap pelayanan dasar.
Di Papua, harga beras bisa sepuluh kali lipat dari harga di Pulau Jawa. Biaya pengiriman satu truk semen sama mahalnya dengan membangun satu rumah di Sumatera. Karena itu, menyamakan Papua dengan wilayah lain adalah bentuk ketidakadilan kebijakan. Pembangunan di Papua harus lahir dari pemahaman mendalam terhadap geografi, budaya, dan pola hidup masyarakatnya. Bukan dari tiruan model pembangunan daerah lain yang datar dan mudah dijangkau.
Papua dari Meja Rapat
Papua tidak bisa diterjemahkan dari meja rapat di Jakarta. Kertas-kertas kebijakan tidak akan pernah cukup untuk memahami mengapa masyarakat di distrik-distrik di wilayah pegunungan Papua masih sulit mengakses pendidikan dan kesehatan. Papua harus diterjemahkan melalui pendengaran dan kehadiran, bukan sekadar laporan dan instruksi. Salah satu kegagalan besar pembangunan selama dua dekade otonomi khusus (otsus) adalah kurangnya empati kebijakan. Dana besar turun ke daerah, tetapi desain dan pengawasan masih terkesan Jakarta-sentris.
Padahal, setiap wilayah di Papua raya punya tantangan berbeda. Papua Pegunungan tanpa pelabuhan laut, Papua Tengah terisolasi oleh pegunungan tinggi, Papua Selatan dengan jarak antar kampung puluhan kilometer, Papua Barat Daya kaya laut tapi miskin konektivitas. Kebijakan nasional harus diturunkan menjadi kebijakan lokal yang adaptif, kontekstual, dan berbasis kearifan lokal. Hanya dengan begitu Papua bisa ditafsirkan secara benar; bukan sebagai ‘masalah’, melainkan bagian dari solusi bangsa.
Ada asa kolektif masyarakat di ufuk timur tanah Melanesia: negara melalui para pemipin tak lagi mendikte Papua tetapi hadir dengan hati membangun Bersama dalam semangat utuh. Negara mesti hadir untuk mengarahkan, mendampingi, dan membangun bersama. Papua tidak butuh dikontrol, tetapi didengarkan. Tidak butuh belas kasihan, tetapi keadilan. Tidak butuh dikasihani, tetapi diberi kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai jalannya sendiri.
Negara harus hadir bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk menopang agar Papua dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Pendampingan sejati berarti datang dengan hati yang mau belajar, bukan tangan yang ingin memerintah. Pembangunan yang berkelanjutan hanya akan lahir bila pusat dan daerah berdiri sejajar, dalam kemitraan yang tulus dan penuh kepercayaan (trust).
Membaca dengan Bijak
Untuk memahami Papua secara adil, negara melalui para pemimpin harus berani menghadapi realitasnya tanpa menutup mata hati. Paling kurang ada tujuh isu besar yang saat ini menentukan arah masa depan tanah Papua dan dilihat dengan bijak.
Pertama, konflik bersenjata dan keamanan. Konflik antara aparat dan kelompok bersenjata (TPNPB-OPM) masih menjadi luka terbuka. Jalan keluar bukan hanya operasi militer, tetapi dialog bermartabat dan rekonsiliasi kemanusiaan. Setiap peluru yang ditembakkan di hutan pegunungan bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga melahirkan generasi trauma di antara anak-anak yang tumbuh tanpa rasa aman.
Kedua, pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Setiap kasus kekerasan harus ditangani dengan transparansi dan keberanian moral. Papua tidak membutuhkan laporan tanpa tindakan, tetapi tindakan nyata yang memulihkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Ketiga, ketimpangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan antara penduduk asli dan pendatang masih lebar. Pembangunan ekonomi harus berpihak kepada masyarakat adat, memastikan mereka menjadi pelaku, bukan penonton di tanahnya sendiri. Skema ekonomi rakyat, seperti koperasi dan BUMDes berbasis wilayah adat, bisa menjadi jembatan antara modernitas dan kearifan lokal.
Keempat, eksploitasi sumber daya alam (SDA). Dari emas di Mimika, Papua Tengah; gas di Teluk Bintuni lalu tembaga di Mimika semuanya sering meninggalkan lubang besar di tanah dan jiwa orang Papua. SDA harus dikelola dengan transparan dan berbasis manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Papua tidak boleh terus menjadi tempat yang kaya sumber daya tetapi miskin kesejahteraan.
Kelima, pembangunan infrastruktur. Jalan dan jembatan penting, tetapi yang lebih penting adalah infrastruktur sosial: guru, tenaga medis, jaringan internet, dan layanan publik yang menjangkau kampung-kampung terpencil. Infrastruktur fisik harus diiringi dengan pembangunan manusia.
Keenam, pendidikan dan kesehatan. Papua tidak akan maju bila anak-anaknya tidak sehat dan tidak bersekolah. Investasi terbesar harus diberikan pada generasi muda Papua: membangun sekolah kontekstual, menyiapkan tenaga guru dan medis yang berasal dari anak daerah sendiri.
Ketujuh, partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang berkeadilan. Rakyat Papua harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Partisipasi bukan hanya formalitas dalam musrenbang, tetapi keterlibatan nyata dalam menentukan arah kebijakan daerah dan pemanfaatan dana otsus.
Dari Dialog ke Kolaborasi
Berbagai pemangku kepentingan telah menyadari bahwa pendekatan keamanan semata tidak menyelesaikan persoalan Papua. Kementerian HAM RI menekankan pentingnya rekonsiliasi dan penyelesaian damai.
Sementara tokoh-tokoh Papua seperti Yoris Raweyai menegaskan bahwa tidak ada pihak tunggal yang mampu menyelesaikan Papua sendiri; harus ada kolaborasi seluruh unsur bangsa: pemerintah pusat, TNI-Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat adat.
Di tingkat daerah, langkah positif mulai terlihat. Pemerintah Provinsi Papua dan provinsi baru hasil pemekaran telah menyiapkan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2025 yang mencakup dana cadangan, kepemudaan, pengelolaan SDA, dan RPJMD demi memastikan pembangunan berkeadilan berbasis hukum yang kuat. Namun semua ini akan bermakna bila diiringi political will pemerintah pusat untuk benar-benar memuliakan manusia Papua, bukan sekadar mengelola wilayahnya.
Papua adalah cermin keadilan bangsa. Bagaimana negara melalui para pemimpin memperlakukan Papua, begitulah sebenarnya nilai kemanusiaan Indonesia diukur. Karena itu, awasan: jangan melihat Papua dari Jakarta di atas menjadi relevan. Datanglah, berjalanlah, dan rasakanlah tanah ini dengan mata hati yang tulus. Karena membangun Papua bukan tentang menanam simbol negara, tetapi tentang menumbuhkan harapan manusia.
Papua tidak butuh belas kasihan. Ia butuh ruang untuk berdiri sejajar. Papua tidak butuh dikasihani tetapi butuh kesempatan untuk tumbuh bermartabat. Ketika Papua diperlakukan dengan adil, Indonesia akan benar-benar utuh. Bukan hanya di peta tetapi di hati seluruh rakyatnya. Papua bukan objek pembangunan, melainkan subjek kebangsaan. Hanya dengan cara itulah, negara benar-benar membangun Indonesia dari timur dengan kasih, keadilan, kebersamaan, dan berkeadaban.