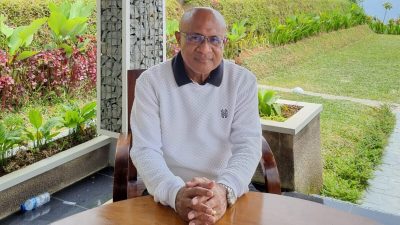Oleh: Yakobus Dumupa
(Pembelajar Hubungan Internasional dan Isu-isu Global, tinggal di Nabire, Tanah Papua)
KETIKA Israel diproklamasikan pada 14 Mei 1948, banyak pihak meramalkan bahwa negara kecil itu tidak akan bertahan lama. Ia lahir di tengah kawasan yang mayoritas dihuni oleh negara-negara Arab dan negara-negara mayoritas Muslim yang memusuhinya secara politik dan ideologis. Dari utara, timur, dan selatan, Israel dikepung oleh kekuatan yang jumlah penduduknya lebih besar, wilayahnya lebih luas, dan sumber dayanya lebih banyak. Namun sejarah justru menulis cerita yang berbeda. Israel bukan hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi salah satu kekuatan militer, teknologi, dan diplomatik paling tangguh di kawasan Timur Tengah.
Dari Negara Kecil Menjadi Pemain Besar
Latar belakang kelahiran Israel tidak lepas dari sejarah panjang diaspora Yahudi dan dinamika politik di wilayah Palestina Mandat Inggris. Setelah Holocaust yang menewaskan jutaan orang Yahudi di Eropa, gagasan membentuk tanah air bagi bangsa Yahudi semakin kuat. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1947 memutuskan pembagian wilayah Palestina menjadi dua: satu untuk negara Yahudi dan satu untuk negara Arab. Kaum Yahudi menerima, sementara negara-negara Arab menolak. Keputusan ini menjadi awal dari benturan panjang antara Israel dan negara-negara tetangganya.
Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak mengirimkan pasukan untuk menggagalkan berdirinya Israel. Tapi hasilnya di luar dugaan: dalam Perang Arab–Israel 1948, pasukan kecil Israel berhasil bertahan, bahkan memperluas wilayahnya. Peristiwa itu menanamkan kesadaran mendalam di benak para pemimpin dan rakyat Israel bahwa keberlangsungan negara mereka hanya mungkin jika mereka mampu mempertahankan diri dengan segala cara.
Dekade-dekade berikutnya menjadi saksi rangkaian konflik besar. Krisis Suez 1956, Perang Enam Hari 1967, dan Perang Yom Kippur 1973 menjadi tonggak sejarah penting. Dalam semua perang itu, Israel tidak hanya berhasil bertahan tetapi juga unggul telak. Perang Enam Hari bahkan mengubah peta kawasan. Dalam enam hari, Israel merebut Yerusalem Timur, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan, dan Gaza. Sejak saat itu, Israel tak lagi dilihat sekadar sebagai negara baru yang rapuh, tetapi sebagai kekuatan militer yang diperhitungkan.
Faktor Kekuatan Israel dan Kelemahan Lawan
Banyak faktor menjelaskan mengapa Israel tetap tegak di tengah kepungan. Faktor pertama adalah kemampuan militer dan intelijen yang mereka bangun sejak awal. Negara ini mewajibkan warganya ikut militer dan mengembangkan sistem pertahanan modern. Lembaga intelijen seperti Mossad, Shin Bet, dan Aman menjadi ujung tombak operasi keamanan. Doktrin preemptive — menyerang terlebih dahulu sebelum diserang — menjadikan Israel sering unggul dalam kecepatan dan ketepatan serangan. Mereka belajar bahwa di lingkungan yang penuh permusuhan, kewaspadaan bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Faktor kedua adalah dukungan politik, militer, dan diplomatik dari Amerika Serikat dan sekutu Barat. Hubungan ini menjadi pilar strategis yang memberi Israel kekuatan tambahan. Bantuan senjata, teknologi militer, serta perlindungan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan Israel lebih leluasa bergerak. Dalam berbagai krisis besar, dukungan Washington sering kali menjadi faktor pembeda antara kekalahan dan kemenangan.
Faktor ketiga, yang sering kurang diperhatikan, adalah kohesi sosial bangsa Yahudi. Pengalaman panjang sebagai kaum diaspora membentuk kesadaran kolektif untuk bersatu di tengah ancaman. Dalam situasi krisis, rakyat Israel menunjukkan kesolidan yang jarang dimiliki banyak negara di kawasan. Ketika banyak negara Arab sibuk dengan konflik internal dan pertikaian politik, Israel tampil dengan sistem politik yang relatif stabil dan arah strategis yang konsisten.
Di sisi lain, lawan-lawan Israel justru terjebak dalam perpecahan. Dunia Arab tidak pernah menjadi satu blok politik yang padu. Mesir, Yordania, Suriah, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Persaingan ideologis — antara rezim nasionalis sekuler, monarki konservatif, dan kelompok Islam politik — sering kali membuat mereka tidak sepakat bahkan terhadap langkah strategis yang paling mendasar. Perseteruan Sunni–Syiah menambah rumit peta politik kawasan. Sementara Israel memperkuat dirinya, dunia Arab justru sibuk dengan pertarungan internal.
Perpecahan ini semakin dalam setelah gelombang Arab Spring pada 2011. Suriah terjerumus dalam perang saudara, Mesir mengalami revolusi dan kudeta, Libya hancur, sementara banyak negara lain tidak stabil secara politik. Dalam kondisi seperti itu, melawan Israel bukan lagi prioritas. Fokus negara-negara Arab lebih banyak tersedot ke dalam urusan domestik dan rivalitas regional.
Dari Musuh Menjadi Mitra
Peta politik Timur Tengah perlahan berubah. Negara-negara Arab yang dulunya bersatu melawan Israel mulai bersikap pragmatis. Mesir menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979. Yordania menyusul pada 1994. Lalu Abraham Accords pada 2020 membuka pintu bagi Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan untuk menormalisasi hubungan diplomatik. Langkah-langkah ini menunjukkan perubahan besar dalam cara sebagian negara Arab memandang Israel: bukan lagi musuh eksistensial, melainkan mitra potensial.
Alasannya sangat jelas. Banyak negara Arab menilai ancaman Iran lebih besar daripada Israel. Ketegangan Sunni–Syiah membuat sebagian negara Teluk memandang Israel sebagai sekutu strategis dalam menghadapi pengaruh Iran. Di sisi lain, kerja sama dengan Israel juga berarti akses terhadap teknologi militer canggih, intelijen, dan peluang ekonomi yang menguntungkan. Israel dengan cepat membaca peluang ini dan bergerak memperluas jaringan diplomatiknya.
Sementara itu, negara-negara Islam non-Arab memiliki sikap yang lebih beragam. Iran menjadi musuh utama Israel, baik secara ideologis maupun strategis. Iran mendukung kelompok bersenjata seperti Hizbullah dan Hamas. Turki, di sisi lain, memainkan politik dua wajah: retorikanya keras terhadap Israel, tetapi kerja sama ekonomi dan militernya tetap berjalan. Negara-negara seperti Pakistan dan Indonesia mendukung perjuangan Palestina secara simbolik, namun tidak berkonfrontasi langsung. Semua ini menunjukkan bahwa kepungan Israel yang dulu solid kini semakin longgar.
Palestina dan Paradoks Kawasan
Selama beberapa dekade pertama, isu Palestina menjadi perekat dunia Arab dan Islam. Palestina adalah simbol perlawanan, identitas kolektif, dan alat pemersatu. Tapi seiring waktu, maknanya perlahan pudar. Banyak negara Arab mulai menggeser fokusnya ke kepentingan domestik dan persaingan regional. Isu Palestina tidak lagi menjadi prasyarat utama dalam hubungan dengan Israel. Dalam banyak kasus, perjanjian normalisasi ditandatangani tanpa melibatkan Palestina sama sekali.
Kini perjuangan Palestina lebih banyak digerakkan oleh segelintir negara dan aktor non-negara seperti Iran, Turki, Hizbullah, dan Hamas. Sementara banyak negara Islam lainnya hanya memberikan dukungan moral atau diplomatik di forum internasional, tanpa langkah politik nyata yang dapat menekan Israel. Palestina kehilangan posisi strategisnya dalam politik kawasan, meski secara moral dan historis masih menjadi isu penting bagi banyak masyarakat Muslim.
Ironinya, ketika dukungan terhadap Palestina melemah, posisi Israel justru semakin kuat. Negara kecil yang dulu dikepung kini memegang banyak kendali atas dinamika kawasan. Paradoks ini mencerminkan perubahan besar dalam politik Timur Tengah: bukan lagi perjuangan kolektif melawan Israel, melainkan persaingan kepentingan nasional yang terpecah-pecah.
Eksistensi yang Kian Kokoh
Israel kini bukan sekadar negara kecil yang bertahan, melainkan aktor regional yang aktif membentuk peta politik Timur Tengah. Dukungan kuat dari Barat, keunggulan teknologi, kekuatan militer, kecerdikan diplomasi, serta perpecahan lawan-lawannya membuat eksistensinya semakin kukuh. Negara-negara Arab yang dulu berada di garis depan perlawanan kini banyak yang justru menjadi mitra strategis. Negara-negara Islam non-Arab sebagian besar hanya memainkan peran simbolik.
Bagi Israel, kepungan yang dulu dianggap ancaman kini menjadi bagian dari strategi bertahan hidup. Dengan membangun aliansi taktis, memperluas jaringan diplomasi, dan menjaga dukungan Barat, mereka mampu mengurangi tekanan eksternal secara drastis. Kini Israel tak lagi sekadar bertahan di tengah ancaman, tetapi menjadi pihak yang menentukan arah pergerakan politik kawasan.
Selama dunia Arab dan Islam tidak memiliki visi strategis bersama, kecil kemungkinan akan terjadi perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Israel akan terus menjadi kekuatan dominan — baik dari segi militer, teknologi, maupun diplomasi. Eksistensinya kini tidak lagi tergantung pada simpati internasional, tetapi pada realitas politik dan kekuatan yang telah dibangunnya selama puluhan tahun.
Penutup
Kisah Israel di Timur Tengah adalah sebuah paradoks. Negara kecil yang lahir dalam kepungan permusuhan kini menjadi kekuatan yang disegani. Ia bertahan bukan karena lingkungannya bersahabat, tetapi karena mampu mengubah tekanan menjadi energi bertahan. Sementara dunia Arab dan Islam terpecah oleh kepentingan yang saling bertabrakan, Israel tampil solid, konsisten, dan pragmatis.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Israel bisa bertahan, melainkan sampai kapan dunia Arab dan Islam akan terus berada dalam posisi lemah dan terpecah. Selama itu terjadi, jawaban sejarah tampaknya akan tetap sama: Israel akan terus eksis — bahkan semakin kuat — di tengah kepungan yang semakin rapuh.