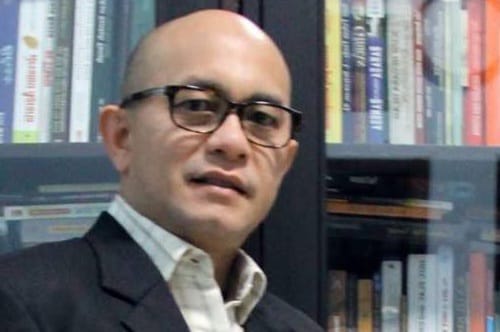Oleh Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran
“The first duty of the state is to protect its citizens, not to terrorize them.” — Václav Havel.
PADA malam 28 Agustus 2025, kutipan Havel, Presiden Cekoslovakia (1989–1992) dan Presiden Republik Ceko pertama (1993–2003), terasa menampar nurani bangsa ini. Seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta.
Rekaman yang beredar menunjukkan ia terjatuh di tengah kerumunan, tubuhnya terseret, lalu digilas ban kendaraan raksasa yang justru dibeli dari pajak rakyat, yang seharusnya peruntukannya demi menjaga ketertiban. Insiden itu bukan sekadar kecelakaan, melainkan tragedi yang menguak rapuhnya janji negara untuk melindungi warganya.
Aparat yang mestinya menjadi perisai justru menjelma sebagai mesin pemutus nyawa. Maka yang terjadi bukan insiden individual, melainkan krisis legitimasi negara. Sosiolog Max Weber (1946) dalam Politics as a Vocation menegaskan bahwa negara memiliki monopoli atas kekerasan yang sah. Namun, sah di sini bukan berarti bebas melakukan apa pun. Kekerasan hanya dapat diterima jika diarahkan untuk melindungi masyarakat.
Dalam tragedi Affan, kekerasan berubah bentuk: aparat menggunakan instrumen kekerasan negara bukan untuk melindungi, melainkan mencederai, bahkan membunuh. Monopoli itupun kehilangan legitimasinya. Weber menegaskan bahwa legitimasi bukanlah sekadar klaim, melainkan penerimaan publik atas tindakan negara. Jika rakyat melihat aparat sebagai ancaman, negara tidak lagi dipandang sahih sebagai pelindung.
Hannah Arendt (1970) dalam On Violence memberikan pembedaan penting, kekuasaan lahir dari legitimasi rakyat, sedangkan kekerasan muncul ketika kekuasaan kehilangan dasar moralnya. Negara yang kuat tidak butuh kekerasan berlebihan, karena legitimasi rakyat sudah menopangnya. Namun, negara yang lemah justru bersandar pada kekerasan, yang ia sebut sebagai “tanda rapuhnya kekuasaan.”
Apa yang terjadi malam itu di Pejompongan adalah bukti nyata tesis Arendt, penggunaan rantis Barracuda untuk menghadapi kerumunan sipil tanpa senjata menunjukkan lemahnya kemampuan negara membangun legitimasi. Mobil tempur menggantikan dialog, roda raksasa menggantikan perundingan, dan nyawa rakyat terhapus sebagai akibatnya.
Tragedi Affan mengingatkan pada kasus George Floyd di Minneapolis pada 2020. Floyd tewas setelah lehernya ditekan lutut polisi selama hampir sembilan menit, tindakan represif yang memicu gerakan global Black Lives Matter. Di sana, kekerasan aparat terhadap warga sipil tak bersenjata menjadi simbol ketidakadilan struktural yang berakar pada rasisme.
Di Indonesia, kasus Affan bisa menjadi simbol serupa: ketidakadilan struktural yang menimpa kelas pekerja informal, mereka yang setiap hari berada di jalanan tanpa perlindungan memadai. Jika George Floyd menjadi pemicu perdebatan ulang soal reformasi kepolisian di Amerika Serikat, tragedi Affan seharusnya menjadi momentum evaluasi besar terhadap aparat keamanan di Indonesia.
Reaksi negara memang muncul cepat: Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf, tujuh anggota Brimob yang berada di kendaraan diamankan, dan Istana menyatakan keprihatinan. Namun, permintaan maaf tanpa akuntabilitas hanyalah sebuah retorika.
Data Kontras (2024) mencatat 643 peristiwa kekerasan oleh aparat dalam lima tahun terakhir, dengan korban sipil berulang kali gagal mendapatkan keadilan. Polanya seragam, korban jatuh, aparat minta maaf, penyelidikan internal dilakukan, lalu publik diarahkan untuk melupakan.
Amnesty International (2022) bahkan menilai Indonesia masuk kategori negara dengan kasus kekerasan aparat yang berulang tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Impunitas ini adalah masalah struktural. Negara kehilangan kapasitas moral ketika nyawa hanya dibalas dengan kata maaf dan tampilan wajah memelas.
Solidaritas komunitas ojol terhadap kematian Affan menunjukkan bahwa tragedi ini bukan sekadar musibah personal, melainkan luka kolektif para pejuang di jalanan. Ratusan pengemudi mendatangi markas Brimob, menuntut pertanggungjawaban. Dalam sosiologi politik, ini bisa dibaca sebagai ekspresi kelas pekerja jalanan yang menolak diperlakukan sebagai korban abadi.
Antonio Gramsci menulis bahwa hegemoni dibangun bukan hanya lewat dominasi, tetapi lewat konsensus. Jika komunitas marjinal menolak untuk diam, maka negara bisa disebut telah gagal membangun hegemoni moral. Teriakan dan tangisan mereka yang menuntut keadilan adalah bukti bahwa negara telah gagal merangkul persetujuan rakyat, dan hanya menyisakan dominasi telanjang.
Masalah lain adalah ketiadaan mekanisme pengawasan independen. Polisi diperiksa oleh polisi, Brimob diawasi oleh Brimob. Di negara demokratis yang matang, pelanggaran aparat ditangani lembaga eksternal, entah berupa komisi independen atau ombudsman sipil.
Kanada, misalnya, memiliki Civilian Review and Complaints Commission yang bisa menyelidiki kepolisian federal secara terbuka. Di Hong Kong, insiden kekerasan polisi terhadap demonstran pada 2019, mendorong pembentukan panel penyelidikan independen, meskipun hasilnya pun masih diperdebatkan. Di Indonesia, mekanisme semacam ini nyaris tidak ada. Tak heran publik skeptis.
Survei LSI (2023) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hanya 63 persen, jauh di bawah TNI yang mencapai 76 persen. Tragedi Affan hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan itu. Kita juga tidak bisa lupa konteks normatif dalam hukum dasar kita sendiri. Pasal 28E UUD 1945 menjamin kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Itu artinya jalanan adalah ruang politik yang sah bagi warga.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya: jalanan lebih aman bagi kendaraan tempur daripada bagi rakyat. Demonstrasi dianggap ancaman, bukan hak. Ketika aparat lebih melindungi aspal daripada nyawa, demokrasi telah berubah menjadi prosedur kosong. Ia mungkin hidup dalam bilik suara, tetapi justru mati di jalanan.
Kasus Affan juga beresonansi dengan tragedi di Myanmar 2021, ketika junta militer menembaki demonstran sipil. Tentu skalanya berbeda, tetapi pelajarannya sama: begitu aparat merasa berhak menggunakan kekerasan tanpa batas terhadap rakyat, maka demokrasi telah berubah menjadi kedok belaka.
Demokrasi sejati bukanlah sekadar ritual elektoral, melainkan perlindungan menyeluruh atas hak-hak sipil. Jika aparat justru melanggar hak paling mendasar, yakni hak hidup, maka demokrasi sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri.
Kematian Affan Kurniawan seharusnya menjadi suatu titik balik. Negara tidak boleh lagi sekadar meminta maaf. Harus ada legislasi baru yang membatasi penggunaan kendaraan taktis dalam aksi sipil. Pendidikan HAM bagi aparat harus diwajibkan, bukan sekadar formalitas.
Mekanisme kontrol sipil independen harus dibentuk agar setiap pelanggaran diproses benar secara transparan. Tanpa itu, demokrasi Indonesia hanya akan berdiri di atas kekerasan aparat. Data Freedom House (2024) menilai Indonesia sebagai “partly free” dengan skor 59/100. Freedom House adalah lembaga independen berbasis di Amerika Serikat yang setiap tahun merilis laporan Freedom in the World, mengukur tingkat kebebasan politik dan hak sipil di lebih dari 200 negara.
Skor diberikan dalam rentang 0–100, di mana 0 berarti tidak bebas sama sekali, sementara 100 berarti sepenuhnya bebas. Dengan skor 59, Indonesia berada di kategori menengah, tidak otoriter penuh, tetapi juga jauh dari demokrasi liberal yang matang. Penyebab utamanya adalah lemahnya perlindungan kebebasan sipil, represi aparat, serta maraknya impunitas atas pelanggaran hak asasi.
Relevansinya jelas: jika tragedi seperti yang menimpa Affan Kurniawan tidak ditangani dengan reformasi serius, maka skor Indonesia bisa terus merosot, menggeser status demokrasi kita ke arah yang lebih tidak bebas lagi. Pada akhirnya, tragedi ini menimbulkan pertanyaan yang paling mendasar: untuk siapa negara ini berdiri? Jika negara hanya hadir untuk menjaga stabilitas semu dengan mengorbankan nyawa rakyat, maka ia telah kehilangan makna dasarnya.
Negara berdaulat bukanlah negara yang menebar rasa takut, melainkan yang mengayomi rakyatnya. Legitimasi tidak lahir dari moncong senjata atau ban kendaraan tempur, melainkan dari penghargaan terhadap nyawa manusia. Affan Kurniawan kini menjadi simbol bahwa demokrasi bisa mati di jalanan, bukan oleh musuh asing, melainkan oleh roda kekerasan negara sendiri.
Dan selama luka ini tidak dijawab dengan reformasi yang benar-benar reformatif, bayang-bayang Affan sang pahlawan jalanan akan terus menghantui republik ini sebagai peringatan bahwa demokrasi yang tidak menghargai nyawa hanyalah demokrasi semu. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan lain muncul yang tak kalah pedih: ke mana wakil rakyat saat kejadian ini?
Di mana suara mereka yang digaji dari pajak rakyat, ketika nyawa rakyat sendiri diremukkan di jalanan? Diamnya parlemen hanya menegaskan bahwa demokrasi kita bukan hanya terancam di jalanan, tetapi juga lumpuh di gedung perwakilan.
Sumber: Kompas.com, Jumat 29 Agustus 2025