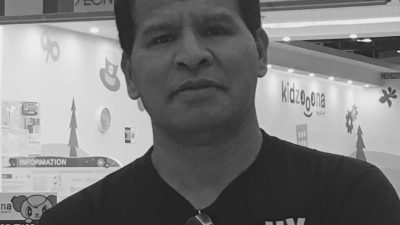Oleh Yakobus Dumupa
(Orang Asli Papua, tinggal di Nabire, Tanah Papua)
BAYANGKAN sebuah negara kecil di pegunungan Himalaya, di mana kemajuan diukur bukan dari jumlah uang yang dihasilkan, melainkan dari seberapa bahagia rakyatnya. Itulah Bhutan, yang sejak 1972 memperkenalkan konsep Gross National Happiness (GNH) atau Kebahagiaan Nasional Bruto. Berbeda dengan kita di Indonesia, yang sering menilai kemajuan dari pertumbuhan ekonomi dan teknologi, Bhutan memilih jalur unik dengan menempatkan kebahagiaan sebagai pusat pembangunan. Namun, bisakah kita menerapkan pendekatan ini di Papua, wilayah kaya sumber daya namun penuh tantangan sosial-budaya, meskipun bertentangan dengan prioritas nasional kita?
Mari kita jelajahi model GNH di Bhutan, bandingkan dengan pendekatan pembangunan di Papua, dan renungkan apakah kebahagiaan bisa menjadi tolok ukur kemajuan di sana.
Bhutan: Menjadikan Kebahagiaan sebagai Kebijakan Negara
Di Bhutan, kebahagiaan bukan sekadar impian, melainkan panduan nyata dalam setiap kebijakan. GNH, yang diperkenalkan oleh Raja Jigme Singye Wangchuck dan diresmikan dalam konstitusi 2008, mengukur kesejahteraan melalui sembilan aspek: kesehatan mental, pendidikan, kesehatan fisik, budaya, lingkungan, tata kelola, komunitas, standar hidup, dan keseimbangan waktu. Setiap proyek, dari pembangunan jalan hingga pembangkit listrik, harus mendukung kebahagiaan rakyat, pelestarian alam, dan budaya lokal.
Kita bisa melihat hasilnya: meski pendapatan per kapitanya hanya sekitar USD 3.000 pada 2024, Bhutan berhasil menjaga 60% wilayahnya sebagai hutan lindung dan menyediakan pendidikan serta kesehatan gratis. Pada 2022, Indeks GNH Bhutan mencapai 0,781, naik dari 0,756 pada 2015, menunjukkan bahwa rakyat mereka semakin bahagia, terutama di bidang pendidikan dan lingkungan. Bayangkan seorang petani di Thimphu yang tersenyum puas karena anaknya bersekolah gratis dan hutannya tetap hijau—itu adalah wajah GNH.
Berbeda dengan kita yang terpaku pada Produk Domestik Bruto (PDB), Bhutan menolak mengejar ekonomi semata. PDB hanya menghitung produksi barang dan jasa, sering kali mengabaikan kerusakan alam atau tekanan hidup. Negara-negara besar seperti Amerika atau Cina mungkin memiliki PDB tinggi, tetapi rakyatnya sering stres karena tekanan kerja. Bhutan bahkan berani menolak keanggotaan penuh WTO demi melindungi budaya lokalnya. Meski menghadapi tantangan seperti urbanisasi, hampir separuh warga Bhutan merasa “sangat bahagia” pada 2022. Bukankah ini sesuatu yang patut kita pikirkan?
Papua: Antara Kekayaan Alam dan Tantangan Sosial
Kita beralih ke Papua, wilayah Indonesia yang penuh kontradiksi: kaya akan emas, tembaga, dan hutan, namun sering dilanda konflik. Sejak Otonomi Khusus (Otsus) diberlakukan pada 2001, kita telah mengalirkan dana besar untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur seperti Jalan Trans-Papua. Fokus kita adalah ekonomi: pertambangan Freeport dan digitalisasi untuk meningkatkan PDB regional dan mengurangi kemiskinan. Tapi, apakah ini cukup?
Bagi masyarakat adat Papua, kebahagiaan bukan hanya soal uang, melainkan hidup selaras dengan alam dan komunitas. Sayangnya, pembangunan sering kali mengorbankan hutan dan hak adat, memicu konflik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih yang terendah di Indonesia, menunjukkan bahwa kesejahteraan belum merata. Meskipun ada upaya seperti Deklarasi Manokwari 2018 untuk melindungi 70% lahan Papua, kebijakan kita tetap berpusat pada PDB, bukan kebahagiaan rakyat.
Jika kita bandingkan, Papua dan Bhutan sama-sama kaya akan alam dan budaya yang menjunjung harmoni. Namun, Bhutan adalah negara kecil yang homogen, sementara Papua adalah bagian dari Indonesia yang besar dan beragam, dengan prioritas nasional yang menekankan pertumbuhan ekonomi. Di Papua, kebahagiaan sering terhimpit oleh ketegangan sosial dan politik, meskipun Otsus dirancang untuk kesejahteraan.
Bisakah Kita Membawa GNH ke Papua?
Kita mungkin bertanya: apakah model GNH Bhutan bisa kita adopsi di Papua? Jawabannya adalah ya, tetapi dengan penyesuaian. Budaya Papua, yang menghargai alam dan komunitas, sangat cocok dengan filosofi GNH. Kita bisa mengintegrasikan GNH ke dalam kerangka Otsus, misalnya dengan menciptakan indeks kebahagiaan lokal yang mengukur pelestarian hutan, hak adat, dan kesejahteraan mental. Program seperti Papua 2100 Vision, yang menargetkan pelestarian hutan, sudah selaras dengan semangat GNH.
Namun, kita menghadapi rintangan besar. Pendekatan GNH bertentangan dengan prioritas nasional Indonesia yang mengutamakan PDB dengan target pertumbuhan 5-7% per tahun. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, lapangan kerja dan teknologi lebih mendesak daripada kebahagiaan abstrak. Selain itu, konflik separatis dan biaya adaptasi GNH bisa menjadi hambatan. Bayangkan seorang kepala suku di Papua yang kehilangan tanahnya demi tambang—akankah dia menerima GNH jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi?
Meski begitu, kita punya alasan untuk optimis. Penelitian menunjukkan bahwa PDB tidak selalu mencerminkan kebahagiaan, dan pendekatan holistik seperti GNH bisa meredakan konflik di Papua. Dengan menggabungkan GNH dan Sustainable Development Goals (SDGs), yang sudah kita adopsi, kita bisa membangun model pembangunan yang lebih manusiawi di Papua.
Apa yang Bisa Kita Pelajari?
Kita telah melihat bagaimana Bhutan menjadikan kebahagiaan sebagai jantung pembangunan, meski dengan sumber daya terbatas. Di Papua, kita bisa meniru semangat ini untuk mengatasi ketidaksetaraan dan konflik, tetapi kita perlu keberanian untuk mereformasi kebijakan Otsus dan menggeser fokus dari PDB ke kesejahteraan rakyat. Pertanyaan untuk kita semua: apakah kita siap mengorbankan ambisi ekonomi demi kebahagiaan masyarakat Papua? Mungkin, seperti Bhutan, kita akan menemukan bahwa kemajuan sejati adalah ketika rakyat tidak hanya sejahtera, tetapi juga tersenyum bahagia.