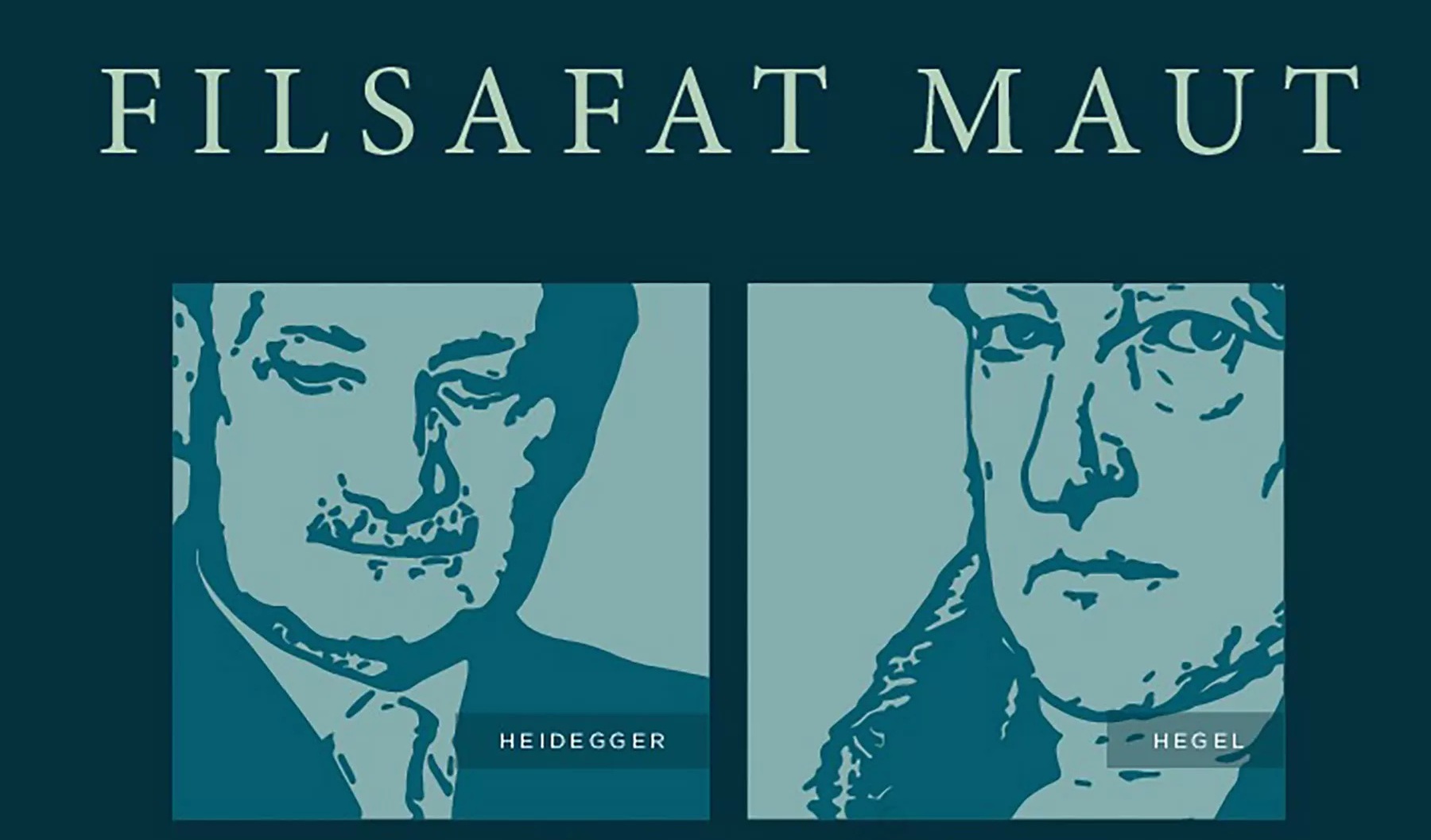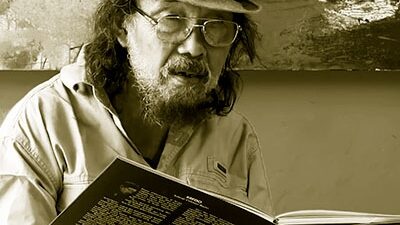![]()
TIDAK banyak orang berani berbicara tentang maut. Karena kata “maut” itu menakutkan. Padahal berita tentang itu banyak menghiasi media sosial baik di akun pribadi, grup maupun di akun publik.
Di era teknologi digital ini, bahkan situasi duka itu sering ditayangkan secara “live” oleh Netizen, bahkan menjadi konten seseorang di ruang publik demi cuan, yang tentunya hal tidak sepantasnya dilakukan dan dehumanistik.
Terlepas dari itu, bagaimanapun berita kematian mengguncang sukma, membangkitkan rasa pilu dan empati, lebih-lebih kalau duka itu menimpa anak-anak kecil yang ditinggal selamanya oleh ayah atau/dan ibunya.
Bahwa kematian selalu menggugah rasa dan peduli, dan empati adalah aspek etis penting. Di samping itu, peristiwa maut menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa kehadiran di dunia ini adalah sebuah peziarahan hidup.
Orang Latin, tepatnya Gregorius Agung dalam buku Moralia (VIII 54, hl. 92) mengistilahkan itu dengan dua kata, yakni homo viator, manusia peziarah. Ya peziarahan batin, ya peziarahan sosial, ya peziarahan spiritual.
Gabriel Marcel, filsuf Prancis di kemudian hari juga menyebut kembali istilah itu dalam bukunya, Homo Viator: Introduction to Metaphysic of Hope (Manusia Peziarah: Pengantar untuk Suatu Metafisika Pengharapan) tahun 2010.
Berita tentang kematian selalu memuat minimal dua pesan berikut. Pertama, mengingatkan bahwa ada waktu atau giliran setiap orang. Setiap kali melayat, bagi saya terbesit pesan bahwa ada saatnya bagi setiap orang untuk tiba gilirannya untuk mengakhiri perjalan peziarahan itu. Kapan? Kita tidak tahu. Yang pasti setiap orang akan mendapat gilirannya.
Ada yang duluan, ada yang belakangan. Orang Latin berkata, hodie tibi, cras mihi, hari ini giliranmu, lain waktu giliranku. Inilah saya katakan saat melayat seorang teman dekat di Unika Atma Jaya Jakarta, bernama Felix Lengkong, Senin 20 Juli 2025 di BSD, di depan tubuh almarhum terbujur kaku itu. Mungkin Sahabat itu juga mengatakan hal yang sama pada saya dan pelayat: hodie mihi, cras tibi, hari ini giliranku, besok adalah giliranmu.
Kedua, pentingnya menjalani hidup bermutu. Kematian sesungguhnya juga mengingatkan tentang pentingnya mengisi hidup bermutu sebelum ajal datang menjemput. Dengan kata lain, berbicara tentang kematian identik dengan berbicara tentang bagaimana menjalani hidup yang lebih baik dan bermakna bagi diri sendiri dan orang lain.
Menurut saya, ini adalah makna yang paling penting bagi manusia yang masih berziarah di dunia ini. Dua makna penting tentang kematian di atas dihadirkan oleh empat penulis dalam buku Filsafat Maut: Empat Renungan untuk Hidup Baik (2025, cet. ke-2).
SP Lili Tjahjadi menghadirkan narasi kultural tentang kematian dalam sudut pandang Jepang berdasarkan buku Hagakure sebagai pembahasan awal buku tersebut. Dari Hagakure, Lili Tjahjadi menyodorkan paham tentang makna kematian, yang dalam Bahasa Jepang dikenal dengan istilah bushido (jalan petarung) para samurai, sebagai peristiwa yang tak perlu ditakuti melainkan dihadapi dengan kemantapan hati.
Menghadapinya dengan sikap demikian menjadi tanda kesetiaan dan pengabdian pada Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Di sini, kematian mengingatkan hadirnya nilai keutamaan, tepatnya hidup yang baik, yang membuat manusia tumbuh menjadi pribadi pemberani.
Cara Pandang Filosofis
Selain perspektif kultural, cara pandang filosofis yang merujuk pemikiran FGW Hegel dan Martin Heidegger memperkaya pemaknaan tentang kematian. Dari Hegel, pembaca belajar tentang arti kematian sebagai hakikat Tuhan. Seperti diulas mendalam oleh Fitzerald K Sitorus, Hegel menyatakan bahwa kematian menghadirkan penjelmaan yang tidak terbatas menjadi terbatas.
Dan inkarnasi ini bermakna dialektis, karena di sana, ketakutan terhadap kematian justru menghasilkan hal-hal yang baik seperti: tumbuhnya peradaban, berkembangnya bakat-bakat manusiawi, pendisiplinan diri, dan menjadi hidup lebih bijaksana.
Jadi, bagi Hegel kematian dipandang sebagai peneguhan spiritual dan peneguhan keberadaan manusia sebagai makhluk yang kreatif, berkeutamaan rasional dan moral seperti digagas oleh Aristoteles dalam buku Nicomachean Ethics (2021).
Pendekatan filosofis yang sangat menyentuh hidup keseharian hadir dengan jelas dalam pemikiran Martin Heidegger yang diulas secara mendalam oleh Heideggerian, Prof Dr FB Hardiman.
Menurut Franky Hardiman, pandangan Heidegger tentang kematian berfokus pada pengalaman keseharian manusia, yakni keterkaitan waktu dengan keberadaannya. Ungkapan terkenal dari Heidegger tentang ini adalah sein zum tode, ada (manusia) menuju kematian.
Filsuf Jerman itu mengafirmasikan bahwa kematian merupakan sesuatu yang eksistensial dan bersifat personal. Dikatakan sebagai hal eksistensial karena memang itulah bagian dari keberadaan dan arah perjalanan hidup manusia. Maut tidak bisa diganti dengan uang atau dengan perak dan berlian yang mahal sekalipun agar ia tidak datang menjemput.
Dikatakan bersifat personal karena setiap pribadi akan menghadapinya. Karena itu juga kematian tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Setiap orang harus menjalaninya secara pribadi. Perbedaan hanya soal waktu tibanya.
Bagi Heidegger, seperti dirangkai dalam narasi elegan oleh Hardiman, kematian sebagai pusat permenungan memuat autentisitas (yang sebenarnya), waktu dan keterlemparan manusia di dunia.
Tidak jauh berbeda dengan Hegel dan cara pandang kultural Jepang, bagi Heidegger kematian justru memungkinkan kita untuk menghayati hidup yang bermakna dengan menjalaninya secara otentik (baca: jujur dan benar), dan mengisi waktu dengan baik dengan hal-hal yang positif. Dengan kata lain, kematian mengingatkan kita agar menjalani hidup dalam tanggung jawab moral atas diri kita, terhadap orang lain dan alam semesta.
Memperkuat cara pandang kultural dan filosofis tentang kematian, A Setyo Wibowo menghadirkan pemikiran para Stoik yang memiliki tekanan yang sama dengan cara pandang Jepang dan Hegel di atas, yakni melihat maut sebagai sesuatu yang tidak menakutkan, namun sebagai sesuatu yang rasional dan alamiah. Satu-satunya cara menyesuaikan diri dengannya adalah dengan hidup baik.
Menjalani hidup baik berarti manusia mempersiapkan kematian dengan sungguh-sungguh. “Persiapan demikianlah menjadi tanda manusia menghilangkan rasa takut pada kematian” begitu tulis guru besar filsafat dan alumni STF Driyarkara Jakarta itu.
Menurut hemat saya, gagasan dalam buku Filsafat Maut: Empat Renungan untuk Hidup Baik sangat mendasar. Ide-ide di dalamnya dirangkai dalam bahasa yang mudah dipahami dan amat mencerahkan. Buku ini menghadirkan sebuah pendekatan baru untuk memahami kematian,yakni pendekatan filosofis etis.
Pesan moralnya sederhana, yakni berbicara tentang kematian berbicara tentang kehidupan untuk lebih baik, bukan akhir hidup. Jangan takut bicara tentang maut. Karena itu benarlah kalimat terakhir Prakata buku ini: “Mereka yang berani hidup menyiapkan kematiannya dengan baik setiap saat.” (p.7).
Singkatnya, setiap orang harus menyadari betul bahwa kematian menjadi bagian hidupnya. Perlu kesiapan menghadapinya dengan menjalani hidup yang bermutu dalam keseharian, selagi jantung masih berdetak, nafas masih berhembus, pikiran masih berfungsi, dan tubuh masih berdaya. Salam sadar kehidupan. (*)
Judul: Filsafat Maut: Empat Renungan untuk Hidup Baik
Editor: Franky Budi Hardiman
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
Tebal: 182 halaman
Tahun terbit: 2025, cet-ke 2
Kasdin Sihotang
Dosen Filsafat Moral Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta