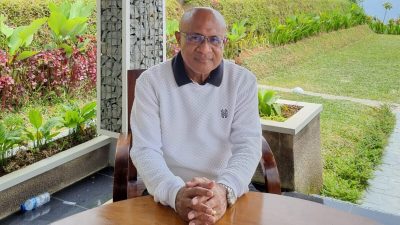Oleh: Yakobus Dumupa
(Pembelajar Hubungan Internasional dan Isu-isu Global, tinggal di Nabire, Tanah Papua)
Jalan Baru Damaskus
Pernyataan Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, pada 17 September 2025, membuat kawasan Timur Tengah kembali bergolak. Ia menegaskan bahwa Suriah siap menandatangani sebuah kesepakatan damai dengan Israel. Kesepakatan ini bukanlah normalisasi penuh sebagaimana yang ditempuh Mesir pada 1979 atau Yordania pada 1994, melainkan lebih bersifat pengaturan keamanan. Poin utamanya mencakup penghentian serangan udara Israel ke wilayah Suriah, penghormatan terhadap kedaulatan udara dan darat, pembentukan zona penyangga di perbatasan selatan, serta pengawasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meski hanya sebatas pengaturan keamanan, langkah ini sudah cukup untuk menandai perubahan besar dalam politik luar negeri Suriah, mengingat hubungan historis kedua negara selama ini lebih didominasi permusuhan dan perang.
Suriah tidak sedang mencari popularitas politik dengan langkah ini, melainkan keselamatan negara. Sejak rezim Bashar al-Assad tumbang pada akhir 2024, Suriah terjebak dalam kondisi yang sangat rapuh. Infrastruktur hancur, ekonomi runtuh, dan rakyat hidup dalam penderitaan panjang. Dalam keadaan seperti itu, pemerintah baru harus memilih jalan pragmatis. Melanjutkan konfrontasi dengan Israel hanya akan memperburuk kehancuran. Oleh karena itu, membuka pintu dialog dengan musuh lama dinilai sebagai jalan yang paling realistis untuk memberi ruang bernapas bagi pembangunan kembali negeri yang sudah porak-poranda.
Bagi Presiden al-Sharaa, pilihan ini adalah taruhan besar. Ia tahu risiko politiknya tinggi, baik di dalam negeri maupun di kawasan Arab. Namun bagi pemimpin yang mewarisi negara dalam reruntuhan, tidak ada pilihan lain selain bertindak realistis. Kesepakatan damai terbatas dengan Israel adalah alat untuk meredakan tekanan eksternal, menurunkan risiko eskalasi perang, dan membuka peluang bagi stabilisasi internal.
Suriah Dulu dan Suriah Sekarang
Untuk memahami arti perubahan ini, kita perlu menengok ke belakang. Suriah era Hafez al-Assad dan Bashar al-Assad adalah simbol perlawanan terhadap Israel. Sejak Perang Arab–Israel 1973, hubungan kedua negara nyaris tidak pernah normal. Suriah kehilangan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel pada 1967, dan sejak itu Golan menjadi luka sejarah yang membakar nasionalisme Suriah. Permusuhan dengan Israel kemudian diinstitusionalisasi, menjadi bagian dari identitas politik Damaskus.
Pada masa Assad, Suriah bukan sekadar musuh Israel, tetapi juga sekutu utama Iran dalam “Poros Perlawanan”. Iran memanfaatkan Suriah sebagai jalur logistik menuju Lebanon untuk memperkuat Hezbollah. Suriah menjadi pintu gerbang yang memungkinkan senjata, dana, dan dukungan politik mengalir dari Teheran ke Beirut. Dalam perang saudara Suriah sejak 2011, Iran bahkan mengucurkan miliaran dolar, mengirim pasukan elit, dan mendukung penuh rezim Assad. Tanpa Iran, Assad mungkin sudah tumbang jauh sebelum 2024.
Namun setelah Assad jatuh, wajah Suriah berubah. Presiden al-Sharaa mewarisi negara yang nyaris runtuh. Ia memahami bahwa meneruskan tradisi lama perlawanan akan menjadi beban yang tak tertanggungkan. Karena itu, ia mengubah haluan: lebih memilih pragmatisme ketimbang ideologi. Dalam kerangka baru ini, rekonstruksi ekonomi, konsolidasi politik, dan pemulihan kehidupan sosial masyarakat diprioritaskan. Israel tetap dipandang sebagai lawan, tetapi bukan musuh yang harus diperangi habis-habisan setiap hari. Inilah titik perbedaan yang paling mendasar antara Suriah dulu dan Suriah sekarang.
Murka Iran yang Kehilangan Sekutu
Langkah Damaskus ini membuat Iran murka. Teheran menganggap Suriah telah keluar dari orbit pengaruh yang mereka bangun dengan susah payah. Selama puluhan tahun, Suriah adalah sekutu Arab paling dekat bagi Iran. Hubungan keduanya lebih dari sekadar taktis, melainkan strategis. Iran menjadikan Suriah sebagai benteng pertahanan di Levant – wilayah timur Laut Tengah yang meliputi Suriah, Lebanon, Israel, Palestina, dan Yordania. Kehadiran Suriah dalam poros perlawanan memungkinkan Iran memiliki jalur darat menuju Laut Tengah, yang sangat penting secara geopolitik.
Kini semua itu terancam. Dengan Damaskus mulai membuka dialog dengan Israel, posisi Iran di Levant semakin lemah. Hezbollah di Lebanon, yang sangat bergantung pada jalur suplai melalui Suriah, menghadapi tantangan besar jika jalur itu diawasi ketat atau bahkan ditutup. Tidak mengherankan bila media dan pejabat Iran melontarkan kecaman keras, menuding Suriah “berkhianat” terhadap sejarah panjang perlawanan.
Namun di balik retorika, Iran berada dalam posisi sulit. Ekonomi mereka tercekik sanksi internasional, konflik terbuka dengan Israel semakin memanas, dan jaringan proksi mereka di Lebanon maupun Suriah melemah. Dalam situasi seperti itu, kemampuan Teheran untuk memaksa Damaskus kembali ke barisan lama sudah jauh berkurang. Murka Iran lebih banyak terdengar dalam pidato dan media, tetapi tidak punya daya untuk mengubah kenyataan. Suriah telah mengambil jalannya sendiri, dan Iran tak berdaya menghentikannya.
Mengikuti Jejak Mesir dan Yordania
Langkah Suriah ini jelas mengingatkan pada Mesir dan Yordania. Mesir menandatangani Perjanjian Camp David tahun 1979, yang membuat Israel menarik diri dari Semenanjung Sinai dan membuka hubungan diplomatik dengan Kairo. Keputusan itu membuat Mesir dihujani kecaman, bahkan dikeluarkan dari Liga Arab selama bertahun-tahun. Namun bagi Presiden Anwar Sadat saat itu, perjanjian damai adalah jalan keluar untuk mendapatkan kembali wilayah dan menstabilkan Mesir.
Yordania menyusul pada tahun 1994 dengan Perjanjian Wadi Araba. Raja Hussein menilai bahwa berdamai dengan Israel adalah cara paling rasional untuk mengamankan perbatasan, mengelola sumber daya air, dan memperkuat hubungan dengan Barat. Sama seperti Mesir, Yordania juga sempat dikritik keras, tetapi dalam jangka panjang langkah itu memberi stabilitas politik dan keuntungan ekonomi.
Kini, Suriah tampaknya sedang menapaki jalan yang sama. Bedanya, Suriah tidak langsung melompat ke normalisasi penuh. Damaskus memilih jalan bertahap: mengutamakan pengaturan keamanan lebih dulu, sebelum membicarakan normalisasi politik. Namun substansinya sama: mendahulukan kepentingan nasional di atas ideologi perlawanan. Suriah belajar dari pengalaman Mesir dan Yordania bahwa bertahan hidup lebih penting daripada terjebak dalam perang tanpa akhir.
Damai Parsial dan Implikasi Kawasan
Kesepakatan yang sedang dijajaki Suriah dan Israel adalah bentuk damai parsial. Tidak ada pembukaan kedutaan, tidak ada hubungan dagang, tidak ada normalisasi politik penuh. Namun, penghentian konflik aktif dan stabilitas di perbatasan sudah cukup untuk mengubah lanskap kawasan.
Bagi Israel, stabilitas di utara adalah keuntungan strategis. Selama ini, wilayah Suriah menjadi jalur bagi infiltrasi kelompok pro-Iran. Jika Damaskus benar-benar mengendalikan perbatasannya, ancaman itu bisa ditekan. Israel bisa lebih fokus menghadapi tantangan di Lebanon dan Gaza. Bagi Suriah, kesepakatan parsial ini memberi ruang bernapas untuk membangun kembali negara. Perang yang terus-menerus hanya akan menghambat proses rekonstruksi. Sedangkan bagi Iran, langkah ini adalah pukulan keras yang membuat mereka kehilangan salah satu pijakan terkuat di Levant.
Secara regional, pola baru mulai terbentuk. Damai tidak lagi harus berarti normalisasi total. Negara-negara bisa memilih damai parsial, cukup dengan memastikan perbatasan tenang dan konflik berhenti. Model seperti ini mungkin akan diikuti oleh negara lain yang masih enggan membuka hubungan resmi dengan Israel, tetapi ingin keluar dari lingkaran konflik. Suriah dengan langkah barunya bisa menjadi contoh bahwa damai parsial pun mampu memberi manfaat strategis yang besar.
Arah Baru Timur Tengah
Langkah Suriah mendekat ke Israel dan menjauh dari Iran memperlihatkan bahwa arsitektur politik Timur Tengah sedang berubah. Negara yang dulu dikenal sebagai simbol perlawanan kini berani mengambil keputusan pragmatis demi menyelamatkan dirinya. Israel menyambut dengan hati-hati, Suriah memperoleh keuntungan strategis, sementara Iran kehilangan sekutu penting.
Kisah ini menunjukkan bahwa politik kawasan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh ideologi. Realitas di lapangan, kebutuhan ekonomi, dan keinginan rakyat untuk hidup tenang justru menjadi faktor penentu. Jika Mesir dan Yordania pernah mengambil risiko besar demi stabilitas nasional, kini Suriah sedang menapaki jejak yang sama dengan versinya sendiri. Damai, meski hanya parsial, lebih bermanfaat daripada perang yang tak kunjung usai.
Dari sinilah arah baru Timur Tengah mulai ditata. Suriah memberi contoh bahwa pragmatisme bisa mengalahkan retorika. Bahwa kepentingan rakyat bisa lebih penting daripada simbol perlawanan. Dan bahwa stabilitas, meski rapuh, tetap lebih baik daripada hidup dalam konflik tanpa akhir.