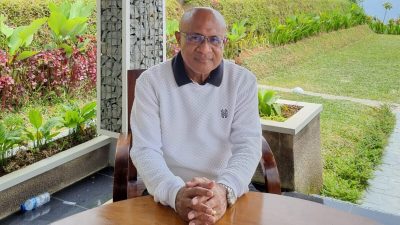Oleh Willem Bobi
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Fisika Universitas Sebelas Maret, Surakarta
GUNUNG-gunung Papua menjulang tinggi bagai benteng raksasa. Puncaknya yang diselimuti kabut seolah menyembunyikan rahasia purba. Namun, di balik dinding batu itu terkubur salah satu harta paling mahal di dunia: emas dan tembaga.
Dari perut Pegunungan Grasberg, miliaran dolar mengalir deras setiap tahun ke kas perusahaan dan negara. Freeport kerap digambarkan sebagai “jantung” industri tambang global, denyut nadi ekonomi yang tak pernah berhenti.
Namun, di balik kilau emas itu, ada luka panjang yang terus menganga. Luka berupa longsor dan kecelakaan kerja yang datang berulang, dari generasi ke generasi, seakan tak pernah benar-benar selesai. Setiap kali material runtuh, setiap kali lereng patah, setiap kali atap tambang roboh, yang tersisa hanyalah kabar duka, keluarga yang kehilangan, dan janji-janji yang tak pernah utuh ditepati.
Luka yang Berawal dari Era Awal
Sejak Freeport membuka tambang Ertsberg pada awal 1970-an, kecelakaan kerja sudah menjadi bagian dari kisah tambang. Catatan resminya jarang dipublikasikan. Laporan resmi perusahaan kerap mereduksi tragedi menjadi sekadar “gangguan operasional.” Tetapi kisah nyata beredar lewat jalur sunyi: bisikan para pekerja, obrolan di rumah ibadah atau laporan serikat buruh.
Pada 1974, beberapa pekerja dilaporkan tewas akibat runtuhan batu di area terbuka. Tak ada headline besar menghiasi halaman media cetak. Tak ada laporan mendetail. Hanya berita samar, dibawa angin pegunungan. Tahun-tahun berikutnya, cerita serupa kembali muncul.
Memasuki 1980-an, risiko semakin tinggi seiring ekspansi besar-besaran menuju Grasberg. Lereng curam yang digali terus-menerus menanggung beban tak wajar. Pada 1989, belasan pekerja hilang dalam runtuhan besar. Bagi perusahaan, insiden itu sekadar catatan teknis. Bagi keluarga korban, itu luka abadi.
Dekade 1990-an menghadirkan bab baru dalam kisah luka. Pada 1994, longsoran besar di Grasberg menewaskan 11 pekerja. Empat tahun kemudian, 1997, insiden serupa kembali terjadi dan merenggut belasan nyawa.
Pola lama semakin kentara: korban jatuh, perusahaan buru-buru menambal lereng. Operasi kembali berjalan. Sementara keluarga korban tenggelam dalam kesenyapan. Dalam logika tambang, produksi tak boleh berhenti. Dalam logika manusia, nyawa tak tergantikan. Namun di Papua, logika pertama selalu mengalahkan yang kedua.
Luka yang Berulang di Abad Baru
Abad 21 bukan penanda perubahan. Justru luka berlanjut dengan pola yang sama. Tahun 2000, longsor besar kembali menelan korban. Tiga tahun kemudian, 2003, runtuhan di tambang bawah tanah merenggut nyawa pekerja, bahkan ketika sebagian sedang beristirahat.
Tragedi terbesar datang pada Mei 2013. Atap terowongan big gossan runtuh, menewaskan 28 pekerja sekaligus. Dunia menoleh ke Papua. Untuk pertama kalinya, tragedi di tambang Freeport masuk dalam sorotan global. Perusahaan berjanji akan memperkuat sistem pemantauan, menambah sensor, dan mengutamakan keselamatan.
Namun janji itu hanya tinggal kata. Sensor dipasang, tapi tak pernah optimal. Pekerja masih mengeluh: “Alarm sering tak berbunyi atau berbunyi terlambat. Kita tahu bahaya saat material sudah jatuh.”
Setelah 2013, rangkaian kecelakaan tetap menghantui. Tahun 2014, kecelakaan di area terbuka menewaskan empat orang. Tahun 2016, operator dozer terperosok bersama alat beratnya. Tahun 2017, tujuh pekerja meninggal setelah jaminan kesehatan pasca mogok diputus perusahaan —sebuah tragedi yang lebih politis daripada teknis, namun sama-sama menelan nyawa.
Pada 2020, longsoran besar menutup jalur vital logistik menuju Tembagapura. Ratusan pekerja terjebak, meski akhirnya dievakuasi. Peristiwa itu menjadi alarm keras: sistem pemantauan geoteknik tambang raksasa ini rapuh.
Namun 2023 dan 2024, laporan runtuhan kembali muncul. Perusahaan menyebut “tak ada korban jiwa” tetapi saksi lapangan mengisahkan lain. Ada yang terluka, ada yang hilang dari daftar, dan ada yang pulang dengan trauma yang tak pernah hilang.
Puncaknya, 8 September 2025. Tambang bawah tanah Grasberg Block Cave mengalami aliran material basah yang menutup jalur evakuasi. Tujuh pekerja terjebak. Dua dipastikan meninggal. Sisanya masih dalam pencarian saat artikel ini ditulis. Proses penyelamatan berlangsung lambat, penuh risiko, dan getir. Tragedi ini hanyalah pengulangan dari luka-luka lama. Luka yang tak kunjung disembuhkan.
Minimnya Sensor, Maksimalnya Risiko
Tambang sebesar Freeport semestinya memiliki sistem pemantauan mutakhir: radar lereng, sensor tekanan, sistem alarm dini yang real-time. Di tambang modern, teknologi semacam ini adalah “mata” dan “telinga” yang menyelamatkan nyawa.
Namun di Freeport, para pekerja menyebut alat itu sering hanya menjadi pajangan. “Sensor ada, tapi tidak selalu aktif. Alarm berbunyi setelah terlambat,” kata seorang pekerja. Nyawa baru dihitung setelah korban ditemukan, bukan saat ancaman masih bisa dicegah.
Dengan cadangan emas dan tembaga raksasa, Freeport jelas mampu membeli teknologi terbaik. Tetapi dalam kenyataan, sensor longsor minim, integrasi prediksi tak kunjung jadi prioritas.
Papua bukan satu-satunya panggung tragedi tambang. Dunia punya catatan panjang. Pertama, Chile tahun 2010. Sebanyak 33 penambang terjebak di tambang San José selama 69 hari.
Dunia menonton, operasi penyelamatan besar-besaran jadi simbol solidaritas global. Pemerintah Chile segera menegakkan regulasi baru untuk meningkatkan standar keselamatan.
Kedua, Turki tahun 2014. Tragedi tambang batu bara Soma menewaskan lebih dari 300 orang. Skala bencana ini memaksa pemerintah merombak aturan tambang, memperketat inspeksi, dan mengubah standar operasional.
Ketiga, Afrika Selatan tahun 2018. Longsor di tambang emas Sibanye-Stillwater menewaskan belasan pekerja. Serikat buruh menuntut sensor yang lebih ketat dan regulasi pun diperkuat.
Bedanya, di Chile, Turki, dan Afrika Selatan tragedi besar memaksa perubahan regulasi nasional. Di Papua, insiden Freeport berulang tanpa gaung berarti. Luka ditutup rapat, operasi berlanjut, dan emas tetap mengalir.
Freeport sering digambarkan sebagai simbol kemajuan tambang dunia. Namun, perbandingan global menunjukkan satu hal: ketika tragedi di negara lain memaksa perubahan, Freeport justru berjalan di tempat. Sensor longsor tetap minim, integrasi prediksi tak kunjung jadi prioritas.
Di balik kilau emas dan tembaga, ada celah raksasa yang dibiarkan menganga: nyawa pekerja selalu berada di urutan kedua setelah produksi. Selama keselamatan dianggap sekunder, tragedi hanyalah soal giliran berikutnya. Dan Papua akan terus mengirim pulang peti-peti kayu ke kampung halaman, sementara emas dan tembaga tetap mengalir deras ke pasar dunia.