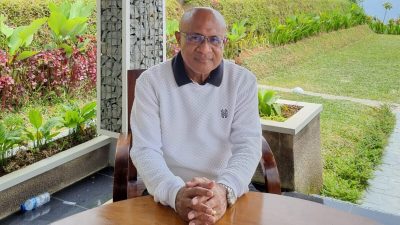Oleh Kasdin Sihotang
Dosen Filsafat Moral Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
JIKA mengamati bahasa yang terejawantah di media baik media sosial maupun media televisi, ada rasa miris dan keprihatinan yang mendalam. Rasa miris dan keprihatinan ini lebih-lebih lagi ketika menyaksikan siapa subjek yang ada di sana, yakni mereka yang pernah mengenyam pendidikan tinggi, bahkan sampai bergelar doktor. Mereka ini sering mengeluarkan kata-kata yang kurang mendidik di ruang publik dengan diksi yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang terdidik. Lebih buruk lagi, kata-kata mereka yang sarkastis itu digunakan oleh mereka sebagai alat kekuasaan untuk menjatuhkan harga diri orang lain, tanpa rasa bersalah dan rasa malu.
Persis seperti apa dikatakan oleh Julien Benda, bahasa kaum terdidik itu merupakan sebuah pengkhianatan intelektual yang sejati seperti ditulisnya dalam Pengkhianatan Kaum Cendekiawan (1997). Tom Nichols bahkan melihat bahwa orang seperti itu telah mengalami kematian kepakaran seperti dirangkainya dalam buku The Death of Expertise (2014). Dengan terus menerus mengumandangkan kebencian dan amarahnya sebagai politik balas dendam di masa lalunya di ruang publik, mereka telah menafikan peran etis intelektual sebagai pemberi motivasi dan pendorong kemajuan bagi generasi muda dan masa depan bangsanya.
Apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu memperlihatkan bahwa tindakan memperalat bahasa sebagai alat kekuasaan dengan ragam strategis telah terjadi. Seperti ditegaskan oleh Aprianus Salam dalam Kesalahan dan Kejahatan dalam Berbahasa (2025), minimal itu terjadi dalam tiga tindakan manipulatif, yakni tindakan manipulatif strategis, di mana orang-orang ini hanya mengutarakan di ruang publik hal-hal yang mendukung kepentingannya namun tidak pernah bersedia menerima apa yang sebenarnya, tindakan manipulasi etis, karena orang-orang ini menggunakan bahasa memelas, yang dalam logika disebut sebagai argumentum ad misericordiam, seolah-olah dia yang paling terzolimi setiap kali tindakan pihak lain terhadap kekeliruan mereka dilakukan, dan tindakan manipulasi teknik dengan menggunakan pencitraan dan identitas untuk mencari simpati dan meraup dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan identitas yang digunakan. Bahkan menurut Aprianus Salam, sesungguhnya dalam bahasa demikian telah terjadi tindakan kejahatan dalam berbahasa. Dan jelas hal ini merupakan antitesis dari esensi bahasa sebagai pengungkapan kepribadian.
Bahasa dan Eksistensi
Tidak bisa dimungkiri bahwa bagi manusia bahasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensinya. Sejak lama para filsuf sudah melihat keterkaitan itu. Mereka menggunakan ragam sudut pandang dalam melihat korelasi itu. Sebut saja misalnya beberapa nama penting seperti Ludwig Wittgenstein, yang menekankan penggunaan bahasa sehari-hari, Gottlob Frege, yang mengembangkan logika formal dan semantik, Noam Chomsky, yang menganalisis struktur mental bahasa. Selain itu ada nama lain seperti J.L. Austin dan Gilbert Ryle. Kedua terakhir ini berkontribusi pada aliran filsafat bahasa biasa di Inggris. Kendati tekanan berbeda terjadi dalam pendalaman para filsuf tersebut, namun ada satu benang merah yang bisa dirajut, yakni bahasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia.
Sebelum nama-nama tersebut di atas, bahkan seorang filsuf Jerman besar bernama Martin Heidegger menempatkan bahasa sebagai indikator dari kualitas pribadi seseorang. “Language is the house of human being” demikian tulis Heidegger dalam bukunya Being and Time (1975). Apa makna dibalik ungkapan ini? Jawabnya sederhana. Yakni, ada hubungan yang erat antara bahasa dengan kualitas manusia, tepatnya bahasa mencerminkan kualitas pribadi seseorang. Konkritnya, melalui bahasa seseorang bisa menunjukkan seperti apa kualitas pribadinya: sehat atau sakitkah jiwanya, bermutu tinggi atau rendah baik dari sisi kepribadian maupun kualitas keilmuan dan profesionalitasnya.
Nilai Intrinsik Bahasa
Para ahli bahasa tentu selalu menekankan bahwa fungsi utama bahasa adalah komunikasi, penghubung antara komunikator (subjek yang berbicara) dengan komunikan (mereka yang mendengarkan atau membaca tulisan) si komunikator. Namun para filsuf yang tersebut di atas melihat bahwa kedudukan bahasa bukan hanya fungsinya sebagai media komunikasi, tetapi lebih dari itu, yakni memiliki makna etis. Artinya, bahasa bukan hanya bernilai instrumental, tetapi juga bernilai intrinsik.
Yang dimaksudkan dengan nilai intrinsik adalah bahwa ada makna melebihi sekedar kata dalam bahasa seseorang. Secara lain dapat dikatakan, selain berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa juga menjadi penyebaran nilai-nilai. Sebagai penyebaran nilai-nilai, maka bahasa memiliki fungsi lebih mendasar, yakni fungsi etis itu. Maksudnya, apa yang diucapkan, dikatakan atau dituliskan oleh seseorang, mengandung pesan moral tertentu baik bagi komunikator, lebih-lebih bagi komunikan. Dengan demikian ucapan, tulisan tidaklah sekedar susunan huruf vokal dan konsonan, tidak juga hanya sebatas susunan kata-kata yang terstruktur, melainkan di situ ada makna yang ingin dihadirkan. Singkatnya, bahasa kita manusia mengandung sarat makna. Justru di sinilah perbedaan bahasa manusia dengan bahasa binatang.
Dengan gagasan dasar di atas jelaslah bahwa bahasa memiliki berbagai implikasi dalam setiap komunikasi yang terjadi di antara manusia. Implikasi yang lebih-lebih menonjol minimal terkuak dalam dua bentuk, yakni implikasi psikologis di satu sisi, dan implikasi etis di lain sisi. Aprianus Salam yang disebutkan di atas mengafirmasikan bahwa implikasi psikologis itu terungkap dalam penyertaan perasaan dalam berbahasa. Dalam bahasa, bisa dua muncul rasa itu, yakni bisa menimbulkan rasa jengkel dan kecewa, bahkan antipati yang bisa berakhir pada pertengkaran atau konflik akibat pemaknaan yang keliru atas kata yang digunakan, atau pilihan diksinya kurang tepat, walau mungkin maksudnya tidak demikian. Jadi dampak psikologis ini bernada negatif dalam relasi sosial.
Tetapi di sisi lain bahasa juga dapat menciptakan suasana nyaman dan bersahabat. Ini merupakan implikasi etis dalam berbahasa. Implikasi etis ini mengisyaratkan bahwa diksi atau bahasa yang digunakan dapat memberikan semangat bagi komunikan untuk menghayati hidup secara lebih baik atau memberikan penegasan afirmatif seperti respek pada pribadi dan dorongan positif bagi orang lain. Jadi fungsi etis bahasa ini tergambar dalam pilihan kata-kata yang bermakna afirmatif: mendorong, membangkitkan semangat, menghidupkan motivasi, mengharga, membuat orang berjuang terus tanpa patah semangat. Bahasa demikian biasa disebutkan dengan affirmative action.
Batasan Normatif
Fungsi etis demikian sesungguhnya mengisyaratkan bahwa bahasa mengandung batasan normatif, batasan kepantasan, lebih-lebih ketika itu dihadirkan dalam ruang publik. Artinya, ketika seseorang berucap di ruang publik, seyogianya diksi atau pilihan katanya tidaklah sembarangan, melainkan perlu selektif. Batasan itu terkait dengan apa? Seperti ditegaskan oleh Aprianus Salam, jawabnya adalah sensitivitas.
Sensitivitas menyangkut minimal dalam tiga hal, yakni bahasa yang terkait dengan isu agama, kesukuan dan harga diri seseorang. Ini artinya apa? Ketika berbicara di ruang publik menyangkut tiga hal itu perlu diperhatikan pilihan kata yang tepat agar jangan sampai menyinggung perasaan pihak lain yang terkait di dalamnya. Tentang dampak negatif dalam dua isu yang pertama, jelaslah bahwa bangsa ini sesungguhnya sudah punya pengalaman sejarah yang banyak. Dampaknya jelas sangat besar dan luas. Karena itulah ketika berbicara atau membahas isu tentang dua bidang tersebut perlu menghidupkan sensitivitas yang tinggi dan mumpuni, artinya melibatkan rasionalitas yang tinggi dalam pilihan diksi atau ungkapan yang disampaikan di ruang publik.
Namun bukan saja dalam dua isu itu perlu rasionalitas dan sensitivitas. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah bahasan yang bersangkut paut dengan harga diri seseorang. Merujuk apa yang dikatakan oleh Martin Heidegger, “Language is the house of human beings”, sangat jelas dalam perbincangan di ruang publik harga diri seseorang harus dijaga. Artinya, sensitivitas seorang komunikan haruslah hidup ketika berbicara tentang pribadi orang, lebih-lebih kalau perbincangan itu terjadi di ruang publik.
Imperatif Kategoris
Secara tegas dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab moral dalam berbahasa, lebih-lebih menyinggung sisi kemanusiaan personal di ruang publik. Meminjam gagasan Immanuel Kant, setiap orang memiliki imperatif kategoris (kewajiban moral) menghargai jati diri dan martabat seseorang dalam diksi yang dinyatakannya. Penghargaan pada harga dan martabat seseorang gitu tidak bisa ditawar-tawar, melainkan sesuatu yang mutlak. Secara negatif dapat dikatakan, tidak boleh seseorang atau kelompok menjatuhkan nama baik dan harga diri orang lain di ruang publik dengan kata-kata yang melecehkan. Ketika seseorang atau kelompok melakukan hal itu, mereka sesungguhnya tidak hanya merendahkan martabat dan pribadi orang lain, tetapi juga merendahkan dirinya di ruang publik. Dengan bahasa demikian, orang-orang seperti itu sama dengan menjatuhkan dirinya. Prinsipnya, seperti dikatakan oleh Walter Tubbs dalam Doa Gestaltnya, bahwa setiap orang adalah bagian dari dirinya, dan dirinya adalah bagian dari orang lain. Maka ketika ia memperlakukan orang lain secara tidak baik, sama dengan memperlakukan dirinya sendiri dengan cara demikian. “Aku hadir di dunia ini bukan hanya berbuat sesuai harapanmu. Aku ada di dunia ini untuk meneguhkan engkau sebagai manusia yang unik dan untuk diperteguh olehmu. Aku hadir untukmu dan engkau hadir untukku. Kita adalah perjumpaan Aku dan Engkau” demikian kata Walter Tubs seperti penulis kutib dalam Filsafat Manusia: Jendela Menyingkap Humanisme (2024: 115).
Mengafirmasi apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant dan Martin Buber, dan Walter Tubbs, Levinas bahkan memberikan penegasan lebih lanjut bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap harkat dan martabat orang lain sebagai ungkapan eksistensi kemanusiaannya. Ketika ia mengabaikan semua itu, lebih-lebih baginya perendahan orang lain itu tidak masalah lagi dalam arti tidak ada rasa bersalah atau malu, maka ia telah menafikan nilai pribadi dirinya sendiri, dalam perendahan orang lain itu. Dengan ulah demikian ia sekaligus menempatkan dirinya setara dengan makhluk infrahuman.
Ketika seseorang terus mengumbar kata-kata kasar di ruang publik untuk menjatuhkan seseorang, seperti ditegaskan oleh Aprianus Salam, orang seperti itu telah menggunakan bahasa sebagai alat kejahatan. Manakala hal itu terus dilakukannya berulang-ulang, bahkan secara ngotot terus, sesungguhnya orang-orang seperti itu tidak hanya secara etis bermasalah, tetapi juga secara psikologis. Di balik upaya demikian sesungguhnya bukan lagi rasionalitas yang berfungsi dalam orang demikian, tetapi rasa benci dan amarah. Dan ini merupakan persoalan psikologis atau masalah kepribadian.
Fenomena demikian merupakan hal yang sangat buruk dalam berbahasa. Dalam hal ini, meminjam istilah Saussure, bahasa sudah menjadi alat konstruksi yang disebutnya “parole”, artinya bahasa telah menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok. Sikap demikian jelas membelokkan makna apa yang dikatakan oleh Martin Heidegger “Language is the house of human being” itu.
Ketika hal itu dibiarkan secara berkelanjutan, tentu taruhannya cukup mendasar, yakni masa depan generasi muda bangsa ke depan. Apalagi kecenderungan demikian hadir di ruang publik secara berkelanjutan dan ditonton oleh anak-anak, yang memiliki sikap mudah meniru atau imitatif. Ditambah lagi mereka yang berbahasa demikian adalah orang yang memiliki kedudukan dan otoritas seperti pejabat publik atau selevelnya. Sudah terbukti dengan jelas salah satu contohnya adalah penggunaan kata “tolol” yang muncul di ruang publik belakangan. Dan yang paling banyak meniru itu adalah anak-anak sebagaimana tersebar melalui berbagai video di media sosial, yang memperlihatkan bagaimana anak-anak meniru ungkapan orang-orang demikian.
Dari paparan di atas, sangat jelas pesannya bahwa setiap warga bangsa di republik ini perlu menjaga bahasa kesantunan , lebih-lebih mereka yang memiliki apa yang disebutkan oleh Gerrit dengan “tough guy” alias yang memiliki peran. Perlu tanggung jawab moral dalam berbahasa, lebih-lebih di ruang publik. Tanggung jawab moral itu terejawantah dalam kemampuan menggunakan kata-kata yang afirmatif, respektif, dan meaningful serta progresif.
Sebagai bagian dari pilar demokrasi, media massa juga perlu menunjukkan tanggung jawab moral itu dengan menyeleksi atau memberikan rambu-rambu bagi orang-orang yang dihadirkan sebagai nara sumber di medianya. Ini seperti dikatakan oleh Hariatmoko dalam Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi (Kanisius: 2007) merupakan bagian dari peran etisnya sebagai pelayan publik, yang kehadirannya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Prinsip etika deontologi, yang menekankan perlunya kesadaran akan kewajiban moral demi bangsa ini sangat relevan dikumandangkan, bukan hanya semangat utilitarianisme, yang orientasinya hanya merebut jumlah pemirsa, namun destruksi bagi generasi muda bangsa. Bangsa ini butuh diksi dan aksi afirmatif untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045.