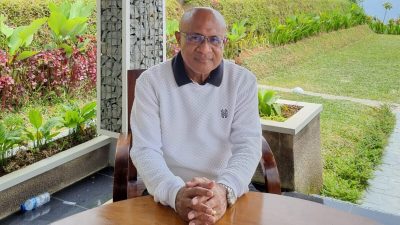Oleh Dr Imanuel Gurik, SE, M.Ec.Dev
Doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura,Papua
INDONESIA, negeri yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kembali diuji dan akan terus melewati ujian. Pada 29-30 Agustus lalu, berbagai kota di Indonesia —Jakarta, Makassar, NTB, Jawa Barat, Yogyakarta, dan beberapa daerah lainnya— dilanda amuk massa yang menimbulkan ketegangan politik dan menelan korban jiwa maupun kerugian materiil.
Fenomena ini bukan sekadar insiden kekerasan biasa. Di balik riuhnya jalanan dan asap yang mengepul dari kota-kota besar, tersimpan pesan mendalam. Sebuah peringatan bahwa rakyat, yang seharusnya dilindungi dan diwakili, kini menjadi korban dari permainan kekuasaan dan kepentingan segelintir elite politik.
Kerusuhan ini terjadi bukan dalam ruang hampa. Amuk massa adalah puncak dari frustrasi rakyat yang telah lama menumpuk akibat kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Demokrasi kita nampak buram di tengah himpitan kebutuhan hidup yang kian mencekik leher. Data ekonomi menunjukkan bahwa inflasi pangan dan energi di Indonesia terus meningkat, sementara akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan masih jauh dari memadai di banyak daerah.
Di Jakarta, pasca ricuh penghujung Agustus harga kebutuhan pokok sempat melonjak tajam, menyulitkan masyarakat miskin kota yang sehari-hari bergantung pada upah harian. Di Makassar dan NTB, bencana alam seperti banjir dan gempa menambah beban masyarakat yang sudah terhimpit ekonomi. Di Jawa Barat dan Yogyakarta, ketimpangan sosial terlihat dari kontras antara pusat kota yang modern dan kampung-kampung yang masih kekurangan infrastruktur dasar. Dalam konteks ini, kemarahan rakyat menjadi logis; kerusuhan bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan manifestasi dari rasa frustrasi yang telah lama ditekan.
Realitas Politik Pembangunan
Namun, yang lebih memprihatinkan adalah fenomena politik yang menyertainya. Banyak pihak menilai bahwa sebagian perwakilan rakyat —yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan kebijakan negara— justru tampak menari di atas penderitaan rakyat. Perumpamaan “menari di atas penderitaan rakyat” bukanlah hiperbola. Ia menggambarkan realitas politik pembangunan di mana sebagian elite politik menikmati posisi dan fasilitas yang mereka miliki. Sementara rakyat di tepian berbeda menghadapi dan terhimpit dalam kesulitan sehari-hari.
Anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, seringkali tersedot untuk kepentingan pribadi, proyek yang mubazir hingga kampanye politik yang menguntungkan segelintir pihak. Di tengah kerusuhan, bukannya hadir sebagai penengah yang menenangkan, beberapa anggota DPR dan pejabat pemerintah justru terlihat sibuk mempertahankan kepentingan politik masing-masing.
Kerusuhan 29-30 Agustus, misalnya, menunjukkan betapa rapuhnya sistem demokrasi jika representasi politik kehilangan moralitas. Di Jakarta, demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi anarkis karena kurangnya respons yang bijak dari aparat dan pejabat politik. Di Makassar dan NTB, konflik horizontal antar warga memicu kekerasan karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak sensitif terhadap kebutuhan lokal.
Di Jawa Barat dan Yogyakarta, pengelolaan informasi yang buruk dan ketidakadilan distribusi bantuan sosial memperparah ketegangan masyarakat. Dalam konteks ini, perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi penengah dan pelindung justru memperparah keadaan dengan retorika populis yang hanya menambah polarisasi.
Fenomena ini menegaskan satu hal bahwa demokrasi formal tanpa akuntabilitas nyata tidak akan pernah membawa kesejahteraan. Rakyat bisa memberikan suara, tetapi suara itu sering dibeli oleh janji-janji kosong. Perwakilan rakyat menjadi simbol status dan kekuasaan, bukan agen perubahan dan perlindungan.
Akibatnya, rakyat menjadi korban dari sistem yang seharusnya melayani mereka. Dalam kerusuhan ini, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, usaha rakyat hancur, dan rasa aman terenggut. Semua itu terjadi sementara sebagian elit politik masih menikmati fasilitas, perjalanan dinas mewah, dan proyek-proyek prestisius yang jauh dari kebutuhan masyarakat.
Selain aspek politik dan ekonomi, kerusuhan ini juga menyingkap luka sosial yang mendalam. Ketimpangan antara pusat dan daerah, antara elite dan rakyat biasa, semakin menganga lebar. Di Papua, misalnya, ketidakadilan pembangunan menyebabkan ketegangan horizontal yang berpotensi memicu konflik. Di Sumatera dan Sulawesi, masalah akses pendidikan dan kesehatan menimbulkan frustrasi generasi muda yang merasa diabaikan.
Di Jawa, urbanisasi tanpa pengelolaan sosial menimbulkan segregasi kota dan kampung, memperburuk rasa ketidakadilan. Ricuh Agustus menjadi peringatan bahwa jika negara tidak hadir secara nyata untuk rakyat. Buntutnya, rakyat akan mengambil jalan pintas untuk menuntut keadilan, bahkan jika harus melalui kekerasan.
Dari perspektif hukum dan tata kelola, kita harus mengakui bahwa institusi negara juga gagal dalam mencegah eskalasi. Aparat keamanan, meskipun bekerja keras, sering terjebak dalam dilema antara menjaga ketertiban dan menghormati hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi.
Peraturan dan protokol keamanan yang ada tidak cukup adaptif terhadap kondisi darurat yang muncul di berbagai kota dengan karakteristik berbeda. Lebih tragis lagi, sebagian pejabat publik menanggapi kerusuhan dengan retorika defensif, bukannya evaluasi kritis terhadap kebijakan yang menimbulkan ketidakpuasan publik.
Kelemahan Sistemik
Penting untuk dicatat bahwa fenomena “menari di atas penderitaan rakyat” bukan hanya soal perilaku individu, tetapi mencerminkan kelemahan sistemik. Sistem demokrasi kita memungkinkan akumulasi kekuasaan tanpa kontrol moral yang ketat. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas kerap alpa dan lemah.
Media dan lembaga pengawas memiliki keterbatasan untuk benar-benar menahan perilaku elit yang menyalahgunakan kekuasaan. Akibatnya, rakyat yang paling menderita sering kali tidak memiliki jalur efektif untuk memperjuangkan hak-haknya. Kerusuhan menjadi salah satu ekspresi ekstrem dari kegagalan sistem ini. Namun, kerusuhan juga memberi sejumlah pelajaran penting.
Pertama, rakyat Indonesia tidak bisa dianggap pasif. Mereka memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan keberanian untuk menuntut keadilan. Kedua, perwakilan rakyat harus segera melakukan refleksi mendalam. Menari di atas penderitaan rakyat bukan hanya perilaku yang amoral, tetapi juga berisiko merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ketiga, aparat keamanan dan pemerintah daerah harus membangun mekanisme respons yang lebih manusiawi dan adaptif terhadap dinamika sosial. Penanganan yang keras tanpa pemahaman akar masalah hanya akan memperburuk konflik di masa depan.
Seiring dengan itu, penting pula bagi akademisi, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil untuk turut memberi seruan moral yang menekankan empati dan keadilan sosial. Rakyat harus melihat bahwa perjuangan mereka di jalanan atau melalui aspirasi politik memang memiliki dukungan intelektual dan moral yang kuat. Perwakilan rakyat yang menari di atas penderitaan rakyat harus ditegur melalui mekanisme hukum, moral, dan politik. Reformasi struktural diperlukan agar sumber daya publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar simbol status elit.
Dalam kerangka jangka panjang, pengalaman Agustus lalu menjadi panggilan untuk melalukan reformasi mendalam. Pendidikan politik rakyat perlu ditingkatkan agar mereka memahami hak dan tanggung jawabnya secara proporsional. Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik harus dijadikan standar mutlak. Elite politik harus menginternalisasi prinsip bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk menari di atas penderitaan rakyat. Sistem demokrasi Indonesia hanya akan sehat jika setiap elemen—rakyat, perwakilan rakyat, aparat, dan masyarakat sipil—bekerja sama untuk keadilan sosial dan kemakmuran bersama.
Kerusuhan yang terjadi bukan akhir dari cerita, tetapi alarm bagi seluruh bangsa. Jika tidak ada introspeksi, kerusuhan berikutnya mungkin lebih parah, dan penderitaan rakyat akan semakin dalam. Sebaliknya, jika peristiwa ini menjadi momentum reformasi —bukan hanya kosmetik tetapi substantif— Indonesia bisa menata kembali hubungan antara rakyat dan wakilnya. Demokrasi sejati tidak diukur dari kemewahan istana atau keangkuhan parlemen, tetapi dari kesejahteraan rakyat yang sejati, keamanan yang nyata, dan keadilan yang dirasakan di seluruh penjuru negeri.
Perwakilan rakyat tidak boleh lagi menari di atas penderitaan rakyat. Mereka harus menari bersama rakyat, di jalan pembangunan yang nyata, di lapangan pendidikan, di rumah sakit yang memberi harapan, dan di desa yang terhubung oleh infrastruktur yang adil. Hanya dengan demikian, demokrasi Indonesia bisa membumi, rakyat tidak lagi menjadi korban, dan negara benar-benar hadir sebagai pelindung dan pelayan.
Rusuh Agustus adalah cermin yang memaksa pertanyaan retoris lahir. Apakah kita masih rela melihat rakyat menanggung beban sementara perwakilannya menari di atasnya? Ataukah saatnya menata ulang tatanan politik dan sosial agar setiap langkah politik menjadi langkah untuk kesejahteraan rakyat? Amuk massa tak akan pernah terhindar dari negara yang terus melangkah melayani rakyat. Namun, upaya merawat demokrasi juga tak boleh tanggal.