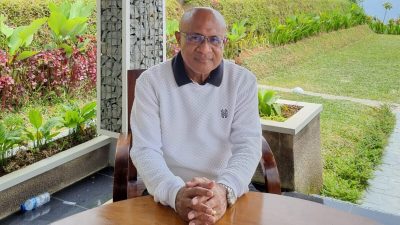Oleh Ben Senang Galus
Penulis buku, tinggal di Yogyakarta
BEBERAPA abad lalu seorang filsuf Yunani Diagne le Cynique menyalakan obor di siang hari, seraya berjalan di tengah kerumunan manusia. Ketika salah seorang diantara kerumunan itu bertanya perihal perbuatannya itu, sang filsuf menjawab “uffatisu an insanin”. Artinya aku sedang mencari manusia.
Apa yang dilakukan sang filsuf tadi, sebenarnya adalah reaksi keprihatinan atas kehidupan manusia pada zaman dan tempatnya, kondisi kehidupan mana sudah terlalu jauh dari alam kemanusiaan manusia, karena tergilas oleh semangat ”gaudeamus igitur iuvenes dum sumus” (bersenang-senang selama kita masih muda/hidup).
Mengamati kehidupan orang Kristen di Papua (sebagai mayoritas penduduk) saat ini, barangkali sudah saatnya tokoh gereja, menyalakan obor di siang hari seraya berjalan di tengah umat, dengan menyerukan Uffatisu an Christen Papua (aku sedang mencari orang Kristen Papua).
Hal ini beranjak dari hasil refleksi intens saya selama beberapa tahun terakhir ini di mana banyak orang Kristen saat ini sedang menjauhi kehidupan Gereja yang dicita-citakannya dan dicita-citakan oleh sebuah Gereja umumnya. Orang Kristen Papua yang semestinya menampilkan semangat Kristus, justeru begitu tumpul dalam kehidupan Gereja. Kultur Gereja yang semestinya bertumbuh subur, namun justeru tertimpa kemarau panjang.
Tidak sedikit umat atau jemaat kita meninggalkan identitas kekristenannya dan lebih memilih “hijrah ke dunia provan atau dunia sekuler”, demi pemenuhan keinginan sosial dan kebendaan semata. Sehingga hubungan Gereja dengan umat tidak lebih bersifat “loco parentis”, sebagai anak asuhan dari sebuah Gereja.
Bersamaan dengan itu muncullah peran-peran umat atau jemaat sebagai “santri-santri”, sebagai pelanggan biasa yang mengambil berbagai peran (pelajaran) untuk mencari identitas provan dan selebihnya sebagai “bohemians ecclesia” (petualang-petualang gereja).
Entah besar atau kecil, bahwa kultur kehidupan menggereja di Papua telah kehilangan semangat, sangat mungkin terjadi oleh keadaan obyektif Gereja kita, yang terwujud dalam beberapa gejala dominan atau berupa komitmen yang diemban atau karakteristik masalah yang dihadapi oleh sebuah Gereja yang di gerogoti oleh banyak peroalan. Gereja yang demikian disebut sebagai Gereja Massa atau Gereja yang Kehilangan Semangat.
Entalah Gereja kita di Papua digolongkan ke dalam jenis Gereja apa. Namun, yang jelas semua Gereja di manapun mengembangkan misi yang sama yakni sebagai pusat pengembangan ajaran Kristus, yakni mampu membangun kehidupan Gereja yang baik dan bermutu.
Kebesaran sebuah Gereja tidaklah ditentukan oleh lancar dan tertibnya seluruh peraturan Gereja dan proses ibadah (Misa), akan tetapi sejauhmana seluruh umat Kristen itu, menegakkan dan menjunjung tinggi kehidupan (kultur) Gereja, yang tampak dalam semangat morality bewareness dan semangat morality inquiry. Kedua semangat ini merupakan faktor kunci bagi tumbuhnya suatu kehidupan menggereja di Papua.
Ibadah (Misa) hanyalah salah satu elemen penting, namun bukan satu-satunya jantung utama yang menggerakkan kehidupan Gereja. Jantung kehidupan Gereja (menggereja) bukan hanya terletak pada proses ibadah (misa) pada hari Minggu. Menurut saya ada tiga elemen penting yang menjadi modal pertumbuhan kehidupan menggereja.
Pertama, Injil (doa) atau disebut “morality machine”, sebagai mesin yang menggerakkan sendi-sendi kehidupan iman umat Kristen. Kedua, lingkungan sosial atau disebut laboratory church, sebagai tempat untuk melatih umat Kristen dalam menaburkan semangat Injil demi menunjang kegiatan peran sosial Gereja secara keseluruhan.
Ketiga, hubungan kooperatif umat-imam-pendeta. Antara umat-imam-pendeta atau uskup perlu dikembangkan relasi partnership demi terwujudnya suatu hubungan kooperatif yang harus dilandasi oleh semangat Injil dan Ajaran Sosial Gereja tentunya berlandaskan keterbukaan dan kejujuran.
Ketakberdayaan mengembangkan kultur Gereja, itu sama halnya Gereja sedang melakukan satu proses pauperisasi atau proses pemiskinan iman. Maka pada gilirannya akan melahirkan umat-umat yang kering imannya.
Begitu pesimisnya pandangan tersebut di atas namun kita merasa terhibur “Gereja tidak diposisikan sebagai menara gading”. Kehadiran gereja ini lebih merupakan gereja sedang mengalami proses “membuminya ajaran Kristus di tanah Papua”.
Argumentasi ini hadir sangat tepat tat kala sebagian umat/jemaat kita saat ini sedang mengalami pilihan tidak pasti oleh perubahan zaman yang menyerang seluruh pikiran, jiwanya. dan bahkan menggoyahkan imannya.
Di sisi lain hadirnya argumen ini lebih sebagai kontekstualisasi ajaran kitab suci, sehingga umat Kristen Papua akan menemukan dirinya dalam habitus baru. Sebab menurut pandangan banyak orang sejak manusia dijadikan dan hingga sekarang dalam perkembangan zaman kesecitraan manusia dengan Allah sering dipertaruhkan dan dirongrong oleh kemajuan zaman.
Perkembangan dan kemajuan zaman bukan tidak dikehendaki Allah. Allah menghendakinya karena itulah Ia menjadikannya jauh melebihi semua ciptaan dan untuk itulah Allah memberikan kuasa bagi manusia untuk menata ciptaan lain di luar dirinya.
Namun kemajuan itu seringkali menjauhkan manusia dari citra yang telah melekat dalam dirinya sejak dijadikan, manusia mulai menjauh dari kebahagiaan sejati yang hanya ada pada Allah. Dalam situasi demikian, citra Allah yang ada dalam dirinya berusaha mencari sesuatu yang mulai kabur atau merangkak menjauh dari dirinya, yakni manusia selalu mencari kebahagiaan semu.
Untuk itu manusia belajar dalam hidupnya, entah itu dari pendidikan formal maupun informal. Pada intinya, manusia belajar dan bekerja adalah untuk mencari dan meraih sesuatu yang sudah sejak dahulu ada dalam dirinya, hanya pencarian dan jalan yang ditempuh oleh manusia seringkali keliru. Kemajuan zaman yang seharusnya memerdekakan manusia tetapi justru ‘memenjarakan’ manusia dalam beroleh kebahagiaan hidup.
Melayani dalam Cahaya Kebenaran
Seiring dengan perubahan zaman, tokoh gereja tidak berhenti atau puas dengan menyebut diri sebagai kaum agamawan atau penggembala umat, namun juga harus memiliki sifat-sifat sebagai seorang Resi. Seorang Resi adalah seorang bijaksana, dan sarat akan nilai moral dan iman.
Karena tokoh gereja adalah penggugah hidup masyarakat atau penguasa. Oleh karena itu tokoh gereja tidak hanya puas menyebut diri animale rationale atau prominent people, tetapi lebih dari itu ia juga sebagai ens sociale, artinya tokoh gereja bercendekiawan, berperan mengabdikan dirinya kepada kebenaran, kejujuran, kebaikan, keadilan, kedamaian dan keindahan serta memiliki moral dan agama yang kuat serta lebih berpihak kepada masyarakat kecil.
Persoalan ini memang tidak berdiri sendiri. Seiring dengan munculnya sistem kekuasaan yang korup, tokoh gereja harus mengambil peran sebagai serviens in lumine veritatis (melayani dalam cahaya kebenaran) yang lebih menekankan aspek ens sociale.
Karakteristik sistem pelayanan seperti menciptakan hubungan umat/jemaat dengan gerejanya bersifat “loco parentis”. Dengan pengertian bahwa para umat ibarat “anak asuhan” dari sebuah Gereja yang bertanggungjawab atas bimbingan dan perkembangan pribadi iman umat/jemaat.
Bersamaan dengan itu muncullah peran-peran tokoh gereja sebagai “santri-santri”, sebagai pelanggan biasa yang mengambil berbagai peran (pelajaran) untuk mencari “gelar ilmuwan” dan selebihnya sebagai “bohemians” atau pemisah diri yang berada di masyarakat, yang memisahkan dirinya dari perkara-perkara masyarakat yang sungguh-sungguh.
Jelaslah paradoksal (antagonistis) karena sering bertolak belakang, konon pendidikan menjadi pendeta atau imam lebih baik dari pada pendidikan umum lainnya, namun dalam praktiknya sering terjadi a histories, karena itu berarti sebuah bentuk keterasingan kehidupan sosial serta sebuah bentuk pengingkaran kebenaran.
Sesungguhnya, hal demikian erat hubungannya dengan kondisi obyektif pendidikan menjadi amam atau pendeta yang tidak pernah memperdulikan segi-segi ens social dalam tataran axiologis. Artinya pula bahwa model pendidikan calon imam atau pendeta sudah saatnya harus direkayasa (reengeenering), sehingga out put-nya sungguh-sugguh menjadi imanen, bukan transenden.
Tokoh Gereja Sebagai “Lalat Liar”
Socrates, cendekiawan Yunani kuno, akhir hidupnya sangat tragis. Ia mati oleh hukuman masyarakatnya. Menjelang kematiannya ia menyebut dirinya “lalat liar”. Ia mengatakan “… mungkin kedengarannya lucu, saya seperti seekor lalat liar di tengkuk seekor kuda”. Kuda adalah pemerintah atau masyarakat yang lelap terlena dalam berbagai kebusukan karena pengabaian nilai-nilai luhur manusiawi. Ia berjuang untuk menegakkan nilai-nilai itu.
Penguasa atau masyarakat merasa terganggu dalam tidurnya dan tanpa pikir panjang memukul lalat liar (baca: Socrates) agar pules lagi dalam gelimang dosa. Socrates mati namun kematiannya tidak dapat begitu saja membuat penguasa/masyarakat tetap tenang melanjutkan tidurnya. Dalam keadaan mata terpejam penguasa/masyarakat berpikir tentang pikiran dan sikap hidup Socrates.
Pesan apa yang akan disampaikan Socrates kepada tokoh gereja di Papua? Jelasnya Socrates ingin mewariskan suatu pesan pada tokoh gereja. Apa isi pesannya. Tokoh gereja tidak boleh hidup aman dalam ketentraman palsu dan stabilitas semu. tokoh gereja harus berperan sebagai “lalat liar”. Kehadirannya di tengah umat/jemaat tidak membuat lagi yang terlena dalam kebusukan tetapi mengganggunya agar terbangun dari tidurnya.
Ini peran tokoh gereja di Papua ke depan; harus memberi kesaksian agar kehidupan ini terjaga. Seorang tokoh gereja (termasuk para calon imam/pendeta), sejak dini harus digembleng dan merasa tidak dapat hidup lebih lanjut kalau tidak menjalankan perannya itu.
Tugas tokoh gereja pada masa kini memang makin tidak gampang. Dewasa ini kehadiran tokoh gereja harus bersuara kuat seperti Socrates dan memegang teguh etika dan kejujuran. Sebab Papua sedang berhadapan dengan masalah berjuang menegakkan kemerdekaannya. Jika dalam perjuangan itu masih ada orang yang pro kontra itu menjadi tantangan tersendiri bagi para tokoh gereja.
Bila tokoh gereja tidak kuat dan jujur ia akan beralih profesi, tidur bersama birokrat dan banyak orang dalam pengabaian nilai-nilai luhur manusiawi. Kita harap kehadiran tokoh gereja tampak semakin jelas dalam latar belakang negara yang semakin gelap, dalam maraknya KKN, merosotnya moralitas pemimpin kita.
Untuk itu perlu ketangguhan moral dan pribadi tokoh gereja, karena jika tidak demikian, peristiwa Socrates terjadi lagi “lalat liar” dipukul mati di Papua. Dan seperti Socrates, pada saatnya tokoh gereja mengambil sikap bahwa kehadiran fisiknya tidak penting lagi, yang penting kehadiran “gangguan” itu.
Gangguan itu membuat penguasa tidak tenang dalam melanjutkan tidurnya. Saya yakin hal itu bukan sesuatu yang sia-sia. Karena sang tokoh gereja bukan memasukan sesuatu yang asing, yang berasal dari luar, ke dalam diri sesama melainkan menyadarkan sesama apa yang terlekat dalam martabatnya sebagai manusia. Manusia pada hakekatnya baik.
Ia mencintai apa yang baik, adil, indah….. Harap oleh hidup dan karya sang cendekiawan masyarakat menyadari bahwa ia tidak dapat hidup lebih lanjut kalau tidak mengubah cara hidupnya sekarang.
Satu catatan penting, kita tidak menafikan peran tokoh gereja dan karya tokoh gereja di tanah Papua, namun akan berbahaya jika sudah merasa diri berhasil dan mulai membanggakan diri. Untuk itu tokoh gereja sudah saatnya membangun komunikasi dan sinergitas dengan tokoh masyarakat untuk melihat peran sosial Gereja terhadap kondisi riil masyarakat (umat/jemaat) Papua.
Sanggupkah para tokoh gereja mengubah kondisi sosial kemasyarakatan (umat/jemaat) saat ini sebagaimana spirit yang telah dibangun oleh Kristus yang telah memerdekakan kita.