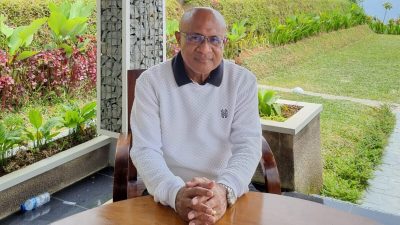Oleh: Yakobus Dumupa
(Pembelajar Hubungan Internasional dan Isu-isu Global, tinggal di Nabire, Tanah Papua)
Tragedi Palestina dan Luka Kemanusiaan
Penderitaan rakyat Palestina telah menjelma menjadi salah satu tragedi kemanusiaan paling mengiris dalam sejarah modern. Setiap kali konflik meningkat, dunia kembali disuguhi pemandangan memilukan: anak-anak yang berlarian mencari perlindungan di tengah serpihan beton, ibu yang meratap di samping jasad anaknya, keluarga yang kehilangan rumah dalam hitungan menit, serta ribuan warga sipil yang hidup dalam ketakutan permanen. Dalam ruang moral umat manusia, tidak ada yang dapat membenarkan penderitaan semacam itu. Tragedi Palestina bukan hanya soal konflik politik, tetapi pelanggaran mendasar terhadap martabat manusia.
Namun tragedi yang menyayat hati itu tidak berdiri sendiri. Di balik air mata dan jeritan yang viral di media sosial, terdapat kenyataan dingin yang mengendalikan jalannya peristiwa: politik. Di ruang moral, manusia menangis. Di ruang politik, negara menghitung kepentingannya. Kemanusiaan mengutuk kekerasan, tetapi kekuasaan menimbang risiko, strategi, dan aliansi. Inilah ironi terbesar tragedi Palestina: secara moral ia adalah luka yang dalam, tetapi dalam logika politik internasional, ia justru dianggap sesuatu yang “wajar”—“dapat diprediksi” meski tidak pernah benar.
Moral yang Mengutuk, Politik yang Mengabaikan
Secara moral, tidak ada bangsa yang pantas mengalami ketakutan dan penindasan yang berlangsung selama puluhan tahun seperti yang dialami Palestina. Namun dalam logika “real politik,” tindakan Israel terhadap Palestina selalu dianggap bagian dari upaya mempertahankan kepentingan nasional dan keamanan negara. Israel memiliki kekuatan militer terbesar di kawasan, teknologi persenjataan canggih, ekonomi kuat, sistem keamanan yang terorganisir, serta dukungan politik yang tidak kecil dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Israel melihat ancaman, baik dari kelompok perlawanan maupun dinamika geopolitik, sebagai ancaman eksistensial.
Dalam logika semacam itu, tindakan represif, operasi militer besar, pembatasan ruang gerak warga, bahkan penghancuran infrastruktur sipil dapat muncul sebagai langkah yang dianggap “perlu”. Tidak wajar secara moral, tetapi wajar secara politik. Inilah perbedaan mendasar antara cara moral bekerja dan cara kekuasaan bekerja. Moral mempertimbangkan nilai, sedangkan kekuasaan mempertimbangkan kemampuan.
Di sisi lain, Palestina berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Sumber daya terbatas, struktur politik internal yang sering tidak solid, dan minimnya dukungan militer membuat mereka tidak mampu memberikan perlawanan atau perlindungan yang setara bagi rakyatnya. Ketimpangan akut inilah yang menjadikan Palestina selalu berada di pihak yang paling menderita.
Dalam kaca mata moral, ini adalah kezaliman yang nyata. Tetapi dalam kacamata politik global, ketimpangan semacam ini dianggap sesuatu yang dapat diprediksi.
Ketimpangan Kekuatan dan Kebisuan Dunia
Dunia berkali-kali mengecam, mengutuk, dan menyatakan solidaritas, tetapi tragedi Palestina tetap berlangsung. Mengapa? Karena politik global diatur oleh kepentingan, bukan kemanusiaan. Negara-negara besar memiliki aliansi strategis dengan Israel, kepentingan ekonomi, teknologi, keamanan, hingga perhitungan geopolitik yang membuat mereka enggan mengambil sikap tegas. Banyak negara mengeluhkan kekerasan, tetapi sedikit yang berani menggunakan kekuatan diplomatik atau politik untuk menghentikannya.
Lembaga internasional pun tidak banyak berbuat. Resolusi penting di Dewan Keamanan PBB terhalang hak veto dari negara-negara kuat. Kecaman hanyalah suara moral, sedangkan keputusan politik ditentukan oleh aliansi dan kepentingan strategis. Dunia tidak sepenuhnya buta terhadap penderitaan, tetapi dunia memilih untuk tidak bergerak karena konsekuensi politiknya terlalu besar.
Inilah kenyataan pahit: penderitaan Palestina bukan hanya akibat tindakan Israel, tetapi juga akibat kebisuan dunia yang lebih menghitung kepentingan daripada nilai kemanusiaan.
Palestina dalam Cermin Politik Global
Tragedi Palestina sebenarnya bukan fenomena tunggal dalam sejarah dunia. Banyak negara telah menggunakan kekuasaan untuk menundukkan kelompok atau bangsa lain demi kepentingan nasional. Rwanda, Bosnia, Irak, Suriah, Myanmar, dan Ukraina adalah beberapa contoh bagaimana kekerasan dapat meledak ketika moralitas tidak lagi menjadi panduan dalam politik.
Indonesia pun memiliki pengalaman pahit yang menunjukkan pola serupa—meski konteksnya berbeda. Timor Leste pernah mengalami operasi militer keras demi integrasi negara. Aceh pernah merasakan tekanan di era Daerah Operasi Militer sebelum perdamaian tercapai. Papua hingga kini menyimpan ketegangan yang berulang. Penyebutan ini bukan untuk menyamakan seluruh situasi, melainkan untuk menunjukkan bahwa pola dominasi kekuasaan adalah fenomena global: negara kuat cenderung menekan yang lemah ketika merasa terancam. Palestina hanyalah salah satu contoh paling jelas—dan paling panjang—dari pola tersebut.
Namun dibandingkan berbagai konflik lain, tragedi Palestina memiliki satu karakter yang membuatnya berbeda: lamanya penderitaan dan tidak adanya solusi yang berkeadilan selama puluhan tahun. Palestina bukan hanya tragedi, tetapi simbol dari kegagalan politik global untuk menghentikan kekejaman yang berkepanjangan.
Pelajaran Moral untuk Dunia, Dengan Fokus pada Palestina
Tragedi Palestina memberi pelajaran penting bagi dunia, tetapi pelajaran itu tidak boleh mengaburkan fokus utama: rakyat Palestina sedang menderita dan dunia belum mampu menghentikannya. Dari Palestina, dunia belajar bagaimana kekuasaan dapat membungkam moral. Bagaimana kepentingan dapat mengalahkan nilai. Bagaimana negara dapat menjustifikasi kekerasan hanya karena mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya.
Pelajaran ini berlaku untuk semua negara dan semua manusia. Dunia pernah melihat krisis kemanusiaan di Rwanda, pembersihan etnis di Bosnia, pengusiran Rohingya di Myanmar, perang Suriah yang menghancurkan, hingga invasi dan pertempuran di Ukraina. Semua tragedi itu menunjukkan pola yang sama: kekuasaan yang tidak dikendalikan moral selalu melahirkan penderitaan.
Tetapi dalam semua contoh itu, Palestina tetap menjadi titik yang paling menonjol karena konsistensinya—penderitaan yang tidak berhenti, ketidakadilan yang berlangsung dari generasi ke generasi, dan dunia yang terus berputar tanpa mampu memberikan jawaban.
Penutup: Palestina sebagai Ujian Moral Peradaban
Palestina adalah luka yang terbuka bagi dunia. Secara moral, tragedi itu adalah kezaliman yang tidak boleh dibiarkan. Namun secara politik, tragedi itu adalah konsekuensi dari struktur kekuasaan internasional yang timpang dan tidak adil. Dua ruang berpikir ini bertabrakan setiap hari: moral menyerukan kemanusiaan, politik mempertahankan kekuasaan.
Jika dunia ingin berubah, Palestina harus menjadi titik refleksi. Dunia harus bertanya: sampai kapan kita akan menerima tragedi kemanusiaan sebagai sesuatu yang wajar dalam politik? Sampai kapan nyawa manusia diperlakukan sebagai angka di meja negosiasi? Dan sampai kapan kekuasaan akan dibiarkan mengalahkan hati nurani?
Selama pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab dengan tindakan nyata, penderitaan Palestina akan terus berlangsung. Dan selama kekuasaan lebih kuat daripada moralitas, dunia akan terus gagal menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasi peradaban.
Palestina adalah cermin dunia. Melalui tragedinya, manusia dapat melihat betapa rapuhnya moralitas dan betapa dominannya kekuasaan. Jika dunia ingin masa depan yang lebih manusiawi, maka politik global harus mulai tunduk pada nilai-nilai moral. Tanpa itu, tragedi seperti Palestina hanya akan menjadi bab yang terus berulang dalam sejarah umat manusia.