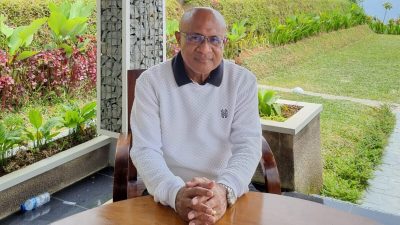Oleh Yosua Noak Douw
Doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura
SEBUAH stiker sederhana menyampaikan ajakan moral: “Ayo Bersama Kita Akhiri Kemiskinan Ekstrem”, sesungguhnya yang sedang disuarakan bukan sekadar program pemerintah.
Lebih dari itu adalah panggilan moral, sosial, dan struktural yang harus dijawab oleh seluruh elemen bangsa, terutama bagi kita yang hidup dan bekerja di atas tanah Papua.
Kampanye seperti ini, yang diinisiasi oleh pemerintah dan didukung data Badan Pusat Statistik (BPS) bukan sekadar retorika komunikasi. Ia bentuk intervensi kesadaran kolektif yang sangat dibutuhkan di tengah realitas kemiskinan yang berurat akar.
Tak Disangkal
Tanah Papua —yang kaya akan sumber daya alam, hutan, air, budaya, dan keragaman hayati— justru menyimpan ironi pembangunan nasional: tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia. Ini kenyataan yang tak bisa disangkal.
Daerah-daerah seperti Papua Pegunungan, Intan Jaya, Yahukimo, Puncak, hingga Pegunungan Bintang, menjadi simbol dari ketimpangan struktural dan keterisolasian geografis yang belum terobati.
Akses jalan terbatas, listrik belum menyala penuh, sekolah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) hanya ada di papan nama. Faktanya, banyak anak masih kekurangan gizi dan ibu-ibu melahirkan tanpa pertolongan medis tak bisa dielak.
Kondisi ini bukan hanya bicara soal angka statistik, tetapi soal martabat manusia Papua yang selama puluhan tahun menjerit dalam diam. Bahkan terpenjara dalam kondisi alam nan ekstrim, terjepit dalam gunung, lembah, ngarai, dan sejenisnya.
Mengapa Masih Miskin?
Penyebab kemiskinan di Papua tidak bisa disederhanakan hanya sebagai “kurang dana” atau “belum merata pembangunan”. Sebaliknya, persoalan kemiskinan ekstrem di Papua adalah hasil dari kompleksitas multidimensi.
Pertama, persoalan struktural karena ada ketimpangan pembangunan nasional yang berakar dari sentralisasi masa lalu. Kedua, persoalan sosial dan budaya, di mana banyak komunitas adat yang belum terakses pendidikan dan informasi.
Ketiga, persoalan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari sumber daya lokal belum dikelola oleh masyarakat asli, dan pasar belum tumbuh. Keempat, persoalan pemerintahan, di mana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), inefisiensi, dan lemahnya pengawasan dana publik belum optimal.
Kelima, persoalan keamanan. Ini terkait erat dengan konflik bersenjata atau gejolak sosial membuat pembangunan tidak bisa dilaksanakan secara berkesinambungan. Singkatnya, Papua tidak miskin karena orang Papua tidak mampu tetapi miskin karena sistem belum memungkinkan orang Papua menjadi tuan di atas kaki sendiri.
Bukan Sekadar Retorika
Jika pemerintah pusat dan daerah serius ingin mengakhiri kemiskinan ekstrem, maka perlu perubahan pendekatan. Bukan lagi “pemberian”, tetapi “pemberdayaan”. Bukan lagi “program dari Jakarta”, tapi “inisiatif dari kampung”. Ada beberapa strategi yang sangat relevan untuk konteks Papua.
Pertama, pemetaan ulang rumah tangga miskin berbasis nama dan alamat agar bantuan tepat sasaran. Kedua, investasi besar-besaran pada SDM lokal melalui pendidikan vokasi dan sekolah rakyat.
Ketiga, penguatan ekonomi kampung berbasis komoditas lokal seperti sagu, kopi, ikan air tawar, dan kerajinan tangan. Keempat, peningkatan infrastruktur dasar: air bersih, listrik mikrohidro, jalan kampung, layanan kesehatan.
Kelima, pengawasan publik atas dana otonomi khusus (otsus) melalui pelibatan gereja, tokoh adat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tanpa strategi yang berakar dari konteks Papua, program kemiskinan hanya akan bertumpu pada bantuan yang bersifat seremonial dan bukan jalan keluar dari ketertinggalan.
Kunci dari semua strategi ini adalah mengembalikan posisi orang asli Papua (OAP) sebagai subjek pembangunan. Artinya, orang Papua harus menjadi perencana, pelaksana, dan pengawas dari pembangunan di kampungnya.
Selain itu, koperasi adat dan kelembagaan lokal harus menjadi motor ekonomi, bukan hanya perpanjangan tangan proyek. Berikut pendidikan harus relevan dengan budaya dan kondisi setempat, bukan sekadar meniru kurikulum Jawa.
Dengan prinsip ini, ekonomi kampung akan bangkit, pengangguran berkurang, dan harga diri sebagai orang Papua terangkat.
Gerakan Kolektif
Mengakhiri kemiskinan ekstrem di Papua bukan tugas tunggal pemerintah. Ini adalah tanggung jawab dan gerakan kolektif yang menyasar segmen gereja, tokoh adat, pemuda, perempuan, pengusaha lokal, dan masyarakat kampung. Semua pihak (stakeholders) harus duduk dalam satu meja, merumuskan masa depan bersama.
Gereja tidak cukup sekadar berkhotbah, tetapi harus menjadi penggerak komunitas. Pemerintah tidak cukup hanya membagi bansos, tetapi harus membangun infrastruktur dan membuka pasar. Anak muda Papua tidak cukup hanya menjadi penerima beasiswa, tetapi juga harus menjadi inovator dan pelaku usaha baru.
Stiker dalam awal tulisan di atas hanya satu langkah kecil. Tapi bila stiker itu benar-benar dijadikan pemantik kesadaran kolektif, maka ia bisa menjadi awal dari gerakan besar: Gerakan Papua Bangkit dari Kemiskinan.
Harapan itu nyata, jika kita berani menyusun strategi berdasarkan konteks lokal, melibatkan masyarakat adat sebagai subjek, dan melaksanakan semua program dengan transparan, terukur, dan penuh tanggung jawab.
Akhirnya, kita tidak hanya menyaksikan kampanye bertuliskan, “Ayo Bersama Kita Akhiri Kemiskinan Ekstrem”, tetapi kita benar-benar menghidupi dan mewujudkannya: dari kampung ke kota, dari gunung ke pesisir, dari mimpi ke kenyataan. (*)