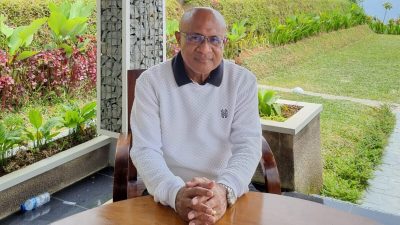Oleh: Yakobus Dumupa
(Pembelajar Hubungan Internasional dan Isu-isu Global, tinggal di Nabire, Tanah Papua)
Pendahuluan
Konflik Israel–Palestina adalah salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia modern. Sejak berdirinya negara Israel pada 1948 hingga kini, konflik ini selalu menghadirkan babak baru yang menegangkan. Perang, intifada, blokade, hingga perundingan damai menjadi bagian dari kisah yang tidak pernah berakhir. Di balik kekerasan fisik, ada juga perang narasi yang tak kalah sengit. Salah satunya adalah soal pelabelan “teroris.” Kata itu tidak hanya menggambarkan tindakan kekerasan, melainkan juga sarana politik untuk menjatuhkan legitimasi pihak lawan.
Bagi Israel, Hamas adalah simbol terorisme. Setiap serangan yang dilakukan Hamas dianggap bukti nyata bahwa mereka bukan pejuang, melainkan penjahat. Sebaliknya, bagi banyak pihak di dunia, Israel justru adalah aktor yang melakukan terorisme negara dengan menargetkan warga sipil Palestina. Dua pandangan yang berlawanan ini menjadikan istilah “teroris” sangat cair dan bergantung pada sudut pandang politik. Artikel ini akan menguraikan tuduhan terhadap Hamas, tuduhan terhadap Israel, pandangan pihak lain, serta refleksi akhir tentang apa makna dari saling melabeli tersebut.
Tuduhan terhadap Hamas
Israel dan negara-negara Barat melihat Hamas sebagai organisasi teroris sejak lama. Puncaknya terjadi pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel. Serangan itu menewaskan lebih dari seribu orang, sebagian besar warga sipil, dan ratusan lainnya disandera. Peristiwa itu digambarkan media Barat sebagai “9/11 versi Israel”. Bagi Washington, Brussels, London, dan Canberra, serangan itu sudah cukup membuktikan bahwa Hamas beroperasi dengan logika teror, bukan perlawanan.
Sejalan dengan itu, berbagai negara menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Amerika Serikat mencatat Hamas dalam daftar Foreign Terrorist Organization sejak 1997. Uni Eropa menempatkannya dalam “EU terrorist list”, sementara Inggris memproskripsinya penuh sejak 2021. Kanada, Australia, Jepang, dan Selandia Baru mengikuti langkah yang sama, disusul Paraguay dan Ekuador. Status ini membawa konsekuensi hukum serius: aset Hamas dibekukan, pendanaan ke mereka dianggap kriminal, dan simpatisan bisa dikenai pidana.
Israel menggunakan dukungan ini untuk memperkuat legitimasi militernya. Setiap operasi di Gaza disebut sebagai bagian dari “perang global melawan terorisme”. Dengan narasi tersebut, Israel berharap tindakannya tidak dipandang sebagai agresi terhadap rakyat Palestina, melainkan pembelaan diri terhadap ancaman yang sejajar dengan Al-Qaida atau ISIS. Bagi negara-negara Barat, narasi ini sejalan dengan agenda mereka pasca-9/11, ketika terorisme internasional dianggap ancaman utama.
Namun Hamas menolak keras label itu. Mereka menyebut diri sebagai harakat muqawama, gerakan perlawanan melawan pendudukan. Menurut mereka, bangsa yang terjajah memiliki hak membela diri dengan segala cara, termasuk bersenjata. Hamas berargumen bahwa perlawanan mereka sah dalam hukum internasional, sebab Israel dianggap sebagai penjajah. Dari sudut pandang ini, serangan yang mereka lakukan adalah strategi perang, bukan aksi terorisme.
Narasi ini mendapat dukungan luas di dunia Muslim. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, secara terbuka menyatakan Hamas bukan teroris. Iran menyebut Hamas sebagai bagian dari “front perlawanan” di Timur Tengah. Qatar bahkan memberikan ruang politik bagi Hamas dengan membuka kantor mereka di Doha. Di dunia Arab, Hamas sering dipandang sebagai simbol perjuangan rakyat Palestina. Di Indonesia pun, banyak pihak menilai Hamas bukan teroris, melainkan pejuang yang mempertahankan tanah air.
Dengan demikian, label terhadap Hamas sangat bergantung pada posisi politik masing-masing negara. Barat menegaskan Hamas teroris, sementara sebagian dunia Islam menegaskan Hamas pejuang sah. Perbedaan persepsi ini menjadikan kata “teroris” tidak memiliki makna universal, melainkan sangat politis dan relatif.
Tuduhan terhadap Israel
Jika Hamas menghadapi tuduhan terorisme dari Barat, Israel justru menghadapi tuduhan sebagai pelaku terorisme negara dari berbagai organisasi HAM dan negara-negara Global South. Amnesty International menyebut Israel menjalankan sistem apartheid terhadap Palestina. Human Rights Watch menuduh adanya ethnic cleansing di Gaza. Komisi Independen PBB mengungkap pola serangan indiscriminatif yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur vital.
Afrika Selatan membawa tuduhan ini ke Mahkamah Internasional dengan gugatan genosida. Mereka menampilkan bukti berupa retorika pejabat Israel yang menyamakan warga Gaza dengan “binatang” dan operasi militer yang menewaskan puluhan ribu orang, termasuk banyak anak-anak. Gugatan ini menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Israel bukan sekadar retorika politik, tetapi sudah masuk ranah hukum internasional.
Tuduhan juga datang dari opini publik. Gelombang demonstrasi di berbagai belahan dunia menampilkan poster dengan tulisan “Israel = Terrorist State”. Di jalanan London, Paris, Jakarta, hingga New York, narasi ini terus bergema. Media sosial memperbesar gaungnya dengan menyebarkan video pemboman rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsian. Bagi masyarakat global, bukti visual itu cukup untuk menilai Israel sebagai pelaku kekejaman sistematis.
Israel membela diri dengan mengangkat hak atas membela diri. Mereka menegaskan bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, menyimpan senjata di sekolah, rumah sakit, dan masjid. Karena itu, setiap serangan Israel diklaim sebagai tindakan militer yang sah. Namun banyak pihak menilai pembelaan ini tidak proporsional. Skala kehancuran di Gaza terlalu besar untuk sekadar disebut konsekuensi perang.
Dengan demikian, Israel berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, mereka didukung Barat sebagai negara yang berperang melawan terorisme. Di sisi lain, mereka dituduh sebagai pelaku terorisme negara dan genosida. Dua narasi ini berlawanan, tetapi sama-sama kuat, sehingga membuat dunia semakin terbelah.
Pandangan pihak lain terhadap keduanya
Dunia tidak bulat dalam menilai siapa teroris. Negara-negara Barat berdiri tegak di belakang Israel, konsisten melabeli Hamas sebagai ancaman global. Dukungan politik, diplomatik, dan militer mengalir deras dengan alasan melawan terorisme. Sementara itu, dunia Arab dan negara-negara Global South cenderung melihat Israel sebagai pelaku terorisme negara.
Rusia menolak melabeli Hamas sebagai teroris, tetapi juga tidak terang-terangan menuduh Israel sebagai teroris. Tiongkok mengambil posisi pragmatis, menjaga jarak dari kedua pihak agar bisa tampil sebagai mediator. Indonesia tidak pernah memasukkan Hamas dalam daftar teroris, sesuai dengan prinsip konstitusional yang menolak segala bentuk kolonialisme. Sikap ini memperlihatkan bahwa politik luar negeri berperan besar dalam menentukan cara pandang terhadap konflik.
Selain negara, organisasi masyarakat sipil internasional juga menyoroti isu ini. Akademisi, tokoh agama, dan aktivis HAM menegaskan bahwa perdebatan tentang label hanya memperpanjang konflik. Mereka mengingatkan bahwa fokus utama seharusnya adalah perlindungan warga sipil. Anak-anak yang terbunuh, keluarga yang kehilangan rumah, dan masyarakat yang terusir adalah bukti nyata bahwa kekerasan kedua pihak sama-sama menghancurkan masa depan.
Dengan demikian, saling tuduh ini lebih banyak menciptakan polarisasi daripada solusi. Alih-alih memperjelas siapa yang benar, label “teroris” justru membuat ruang dialog semakin sempit.
Penutup
Saling tuduh “teroris” antara Israel dan Hamas bukan sekadar deskripsi, tetapi strategi politik. Israel berkepentingan untuk meyakinkan dunia bahwa Hamas adalah teroris agar tindakannya sah. Hamas berkepentingan untuk menunjukkan bahwa Israel adalah pelaku terorisme negara agar perjuangan mereka sah. Dua narasi ini menentukan aliran dukungan global, baik dari Barat maupun dari dunia Islam dan Global South.
Namun di balik retorika itu, korban utamanya tetap rakyat sipil. Warga Israel yang tewas akibat serangan Hamas dan warga Gaza yang hancur akibat serangan Israel sama-sama kehilangan masa depan. Kata “teroris” yang seharusnya membatasi kekerasan justru dipakai untuk membenarkan kekerasan baru.
Jika dunia terus terjebak pada perdebatan siapa teroris, maka penderitaan akan terus berulang. Yang lebih mendesak adalah bagaimana menghentikan teror nyata: penderitaan manusia biasa yang tak berdaya. Hanya dengan menegakkan hukum internasional secara konsisten, membuka ruang dialog, dan menjamin perlindungan warga sipil, maka konflik ini bisa mendekati penyelesaian. Selama label digunakan sebagai senjata, perdamaian akan tetap menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan.