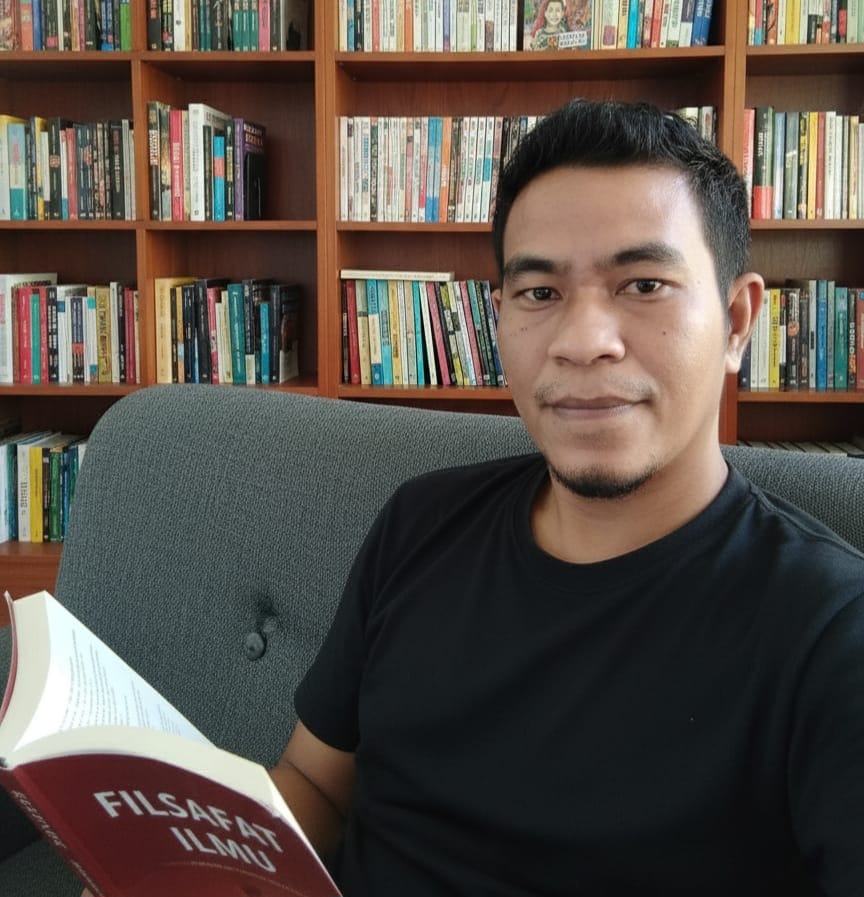Oleh Eugene Mahendra Duan
Guru SMP YPPK Santo Antonius Nabire, Papua Tengah
MENJADI guru di Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi cinta, pengabdian, sekaligus luka yang sering kali tidak diakui negara. Profesi ini selalu direpresentasikan secara heroik—guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa, cahaya peradaban, bahkan poros utama pembangunan manusia.
Namun ironisnya, di balik penghormatan simbolik tersebut, kebijakan pemerintah justru menghadirkan bentuk diskriminasi yang mencolok, terutama dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam momentum Hari Guru (HGN) tahun 2025, kontradiksi inilah yang patut menjadi refleksi kritis: mengapa profesi yang dimuliakan secara moral justru diperlakukan tidak adil dalam sistem kebijakan?
Dalam kultur Indonesia, guru memiliki tempat yang sangat tinggi dalam struktur sosial. Masyarakat memandang guru sebagai figur moral yang membentuk karakter generasi. Guru tidak sekadar mengajar konten, tetapi juga membentuk kesadaran, nilai, dan kedewasaan sosial peserta didik. Mereka bekerja melampaui jam formal, sering bertindak sebagai konselor, mediator keluarga, dan fasilitator komunitas.
Cinta publik kepada guru tidak pernah pudar. Namun penghargaan moral ini tidak selalu memiliki ekuivalensi dalam bentuk perlindungan struktural. Negara tetap menaruh guru dalam posisi rentan melalui kebijakan yang tidak konsisten, berbelit, dan sering kali menempatkan guru sebagai objek administrasi alih-alih subjek utama pendidikan.
Diskriminasi Struktural
Realitas pendidikan Indonesia hari ini menunjukkan hadirnya diskriminasi struktural dalam kebijakan perekrutan PPPK, di mana pemerintah tidak mengizinkan guru yang mengajar di sekolah swasta untuk mengikuti seleksi.
Ketentuan ini berlandaskan regulasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia dan Kemendikbudristek yang mengutamakan guru honorer negeri sebagai sasaran utama rekrutmen, sehingga secara tidak langsung menutup akses bagi guru swasta untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam peningkatan status dan kesejahteraan.
Kebijakan ini menegaskan adanya ketimpangan perlakuan antara guru negeri dan swasta sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memberikan keadilan profesional bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia.
Kebijakan PPPK pada dasarnya dirancang untuk menyelesaikan masalah ketimpangan status guru dan memperbaiki kualitas pendidikan. Namun ketika implementasinya menyingkirkan guru swasta, maka kebijakan tersebut berubah menjadi instrumen eksklusi.
Padahal, guru swasta sama-sama berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa bahkan di daerah yang tidak terjangkau sekolah negeri. Mereka mengajar dengan kondisi sarana terbatas, sering kali tanpa jaminan kesejahteraan, tetapi tetap tidak diberi kesempatan untuk meningkatkan status profesionalnya melalui jalur PPPK.
Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi persoalan keadilan substantif. Diskriminasi ini membangun hierarki baru di dunia pendidikan: guru negeri dianggap prioritas, guru swasta dianggap pelengkap.
Pemerintah melalui slogan Merdeka Belajar menyerukan kemerdekaan guru untuk berinovasi, berkreasi, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Namun bagaimana mungkin guru dapat merdeka jika akses terhadap status kerja yang layak saja dibatasi? Bagaimana mungkin guru bisa berinovasi jika hidupnya dibayangi ketidakpastian ekonomi dan status sosial?
Paradoks ini terlihat jelas: kemerdekaan pedagogis didorong, tetapi kemerdekaan struktural dibatasi. Guru diberikan ruang imajinasi, tetapi tidak diberikan ruang kesejahteraan. Guru diperintah untuk kreatif, tetapi dibatasi oleh birokrasi yang tidak sensitif terhadap realitas mereka.
Dalam pendekatan kebijakan publik, keadaan seperti ini disebut sebagai kesenjangan implementasi, yaitu ketika nilai normatif kebijakan tidak sejalan dengan kebijakan teknis di lapangan.
Dampak Diskriminasi
Diskriminasi dalam perekrutan PPPK membawa dampak yang signifikan bagi motivasi dan profesionalisme guru swasta. Sekurangnya terdapat tiga konsekuensi utama.
Pertama, menurunnya motivasi kerja. Guru yang merasa diperlakukan tidak adil akan kehilangan semangat untuk mengembangkan kompetensinya. Kedua, brain drain ke sektor lain. Banyak guru muda yang meninggalkan profesi karena tidak melihat masa depan yang pasti.
Ketiga, (dan paling berbahaya) hilangnya regenerasi guru berkualitas di sekolah swasta, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) karena mereka tidak memiliki peluang peningkatan karier yang setara.
Ironisnya, sekolah swasta sering kali menjadi penyangga pendidikan nasional ketika sekolah negeri tidak merata. Namun kontribusi ini seperti tidak dianggap relevan dalam penyusunan kebijakan PPPK.
Momentum Hari Guru Nasional tahun ini harus menjadi ajakan moral sekaligus tekanan publik agar pemerintah mereformulasi kebijakan PPPK secara lebih inklusif dan berpihak pada keadilan. Ada tiga rekomendasi mendasar.
Pertama, membuka kembali akses PPPK bagi guru swasta tanpa pembatasan diskriminatif. Seleksi harus berbasis kompetensi, bukan asal institusi tempat mengajar.
Kedua, melakukan afirmasi untuk guru swasta yang telah mengabdi dalam jangka panjang, terutama di wilayah terpencil dan sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.
Ketiga, menciptakan ekosistem rekrutmen nasional yang bersifat universal, adil, dan transparan sehingga seluruh guru memiliki hak yang sama atas pengembangan karier dan kesejahteraan.
Jika negara sungguh menghormati guru, maka kebijakan publik harus selaras dengan prinsip keadilan, bukan sekadar slogan inspiratif.
Cinta Tidak Boleh Mengalahkan Keadilan
Guru di Indonesia mencintai profesinya dengan ketulusan yang jarang ditemukan di profesi lain. Mereka bekerja di tengah keterbatasan, mengajar dengan hati, dan menjaga masa depan bangsa tanpa pamrih.
Namun cinta guru tidak boleh membuat mereka menerima diskriminasi sebagai takdir. Dalam refleksi Hari Guru Nasional tahun ini, kita harus berani mengatakan bahwa negara tidak boleh mencintai guru hanya dalam pidato, tetapi harus membela mereka dalam kebijakan.
Selama diskriminasi dalam PPPK masih berjalan, maka cinta negara kepada guru hanya akan menjadi retorika kosong. Bangsa ini tidak akan pernah maju jika gurunya terus hidup di antara cinta dan diskriminasi.