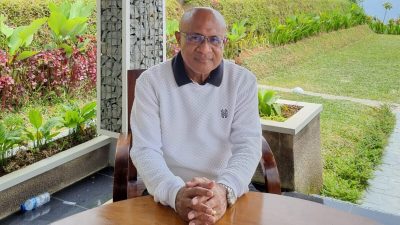Oleh Yosua Noak Douw
Doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua
KEMISKINAN adalah kata yang akrab di telinga. Ia sering muncul dalam berita, pidato politik bahkan terpampang nyata di lingkungan sekitar. Ia bagai penyakit kronis yang seolah tak kunjung menemukan obatnya. Setiap periode kepemimpinan, program pengentasan kemiskinan digulirkan.
Namun, angka statistik kerap tak bergerak signifikan bahkan naik di tengah guncangan ekonomi. Pertanyaan di mana letak soal atau apakah negara melalui aparaturnya di semua tingkatan pemerintahan sudah bekerja memerangi kemiskinan dengan cara tepat dan efektif berkelebat.
Selama ini, pemahaman di tenhah publik tentang kemiskinan seringkali simplistis: tidak punya uang. Solusinya pun dianggap sederhana: beri uang. Program bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) tentu diperlukan sebagai shock absorber untuk mencegah masyarakat terperosok lebih dalam. Namun, pendekatan ini ibarat memberikan obat penurun panas tanpa menyembuhkan sumber infeksinya.
Kemiskinan bukanlah kondisi monolitik, namun masalah multidimensi yang kompleks. Ia adalah jerat yang dibangun dari rendahnya pendidikan, akses kesehatan yang terbatas, kurangnya keterampilan, ketiadaan modal, dan isolasi geografis.
Oleh karena itu, strategi untuk memutus rantai kemiskinan perlu bergerak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan. Tidak bisa lagi bergantung pada satu jurus andalan. Perlu sebuah “orkestra” strategi yang dimainkan secara harmonis, menyerang akar masalah dari segala penjuru.
Pilar Penting
Ada beberapa strategi memutus mata rantai kemiskinan yang merupakan pilar penting. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, bukan elitis. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang adalah sebuah ilusi. Namun, yang dibutuhkan adalah pertumbuhan yang inclusif, yang menyentuh lapisan terbawah.
Caranya sebagai berikut. Pertama, dengan fokus pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pertanian modern, pariwisata, dan industri kreatif. Daripada hanya membanggakan investasi miliaran dolar di sektor tambang yang padat modal, lebih baik menciptakan ribuan ‘pahlawan ekonomi’ baru dengan memudahkan perizinan UMKM, memberikan akses permodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR), dan membuka pasar digital bagi produk-produk lokal.
Kedua, menjaga stabilitas harga, terutama harga bahan pokok. Inflasi adalah musuh utama orang miskin. Kenaikan harga sedikit saja dapat langsung menggerus pendapatan mereka yang sudah pas-pasan. Kebijakan moneter yang hati-hati dan manajemen stok pangan yang cerdas adalah benteng pertahanan pertama bagi daya beli masyarakat.
Kedua, investasi terbaik adalah manusia. Investasi ini adalah strategi jangka panjang yang ampuh. Kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi. Seorang anak yang lahir dari keluarga miskin, dengan akses pendidikan dan kesehatan yang buruk, memiliki peluang besar untuk tetap miskin saat dewasa. Untuk memutus siklus setan ini, investasi pada manusia merupakan keharusan.
Pendidikan berkualitas diperlukan bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa bersekolah dengan layak melalui program beasiswa. Selain itu, aspek yang tak kalah penting adalah merevitalisasi pendidikan vokasi (kejuruan). Daripada menghasilkan pengangguran terdidik, sistem pendidikan harus link and match dengan kebutuhan industri, menciptakan lulusan yang siap kerja atau berwirausaha.
Kesehatan mesti terjangkau. Satu kali anggota keluarga sakit parah, bisa menghabiskan tabungan bertahun-tahun dan menjerumuskan keluarga ke dalam kemiskinan. Kehadiran program asuransi kesehatan nasional seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah sebuah terobosan. Tugas lanjutannya adalah terus menyempurnakan, memastikan kemudahan akses, dan kualitas layanannya terjaga. Pencegahan seperti pemberian gizi tambahan untuk balita dan ibu hamil, juga lebih murah dan efektif dalam jangka panjang.
Pelatihan keterampilan juga tak kalah penting. Sebagian warga pengangguran sebenarnya memiliki semangat kerja, tetapi tidak memiliki keterampilan yang relevan. Program pelatihan teknis seperti listrik, otomotif, programming, dan kewirausahaan, yang diikuti dengan pendampingan adalah ‘pemberian pancing, bukan ikan’ yang sesungguhnya.
Ketiga, pemberdayaan, bukan sekadar perlindungan. Bantuan sosial tetap penting, tetapi harus diarahkan untuk memberdayakan. Program keluarga harapan (PKH) adalah contoh yang baik, di mana bantuan tunai diberikan dengan syarat anak harus bersekolah dan mendapat imunisasi. Ini adalah investasi pada manusia sekaligus perlindungan sosial.
Aspek yang juga krusial adalah pemberdayaan perempuan. Berbagai studi membuktikan, ketika seorang perempuan diberdayakan secara ekonomi dan pendidikan, dampaknya akan berlipat ganda. Ia akan lebih memperhatikan gizi anak, pendidikan anak, dan pengelolaan keuangan keluarga. Kredit usaha mikro untuk perempuan dan kampanye kesetaraan gender bukan sekadar urusan keadilan tetapi strategi cerdas untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Keempat, membuka keran sumber daya produktif. Masyarakat miskin seringkali terperangkap karena mereka tidak memiliki akses kepada sumber daya yang dapat membuat mereka berproduksi. Jerat rentenir dengan bunga yang mencekik adalah kenyataan pahit bagi banyak pelaku usaha mikro. Inklusi keuangan melalui layanan perbankan digital, lembaga keuangan mikro, dan fintech yang bertanggung jawab merupakan solusi.
Bagi petani di pedesaan, tidak memiliki kepemilikan lahan yang jelas membuat mereka sulit untuk mengembangkan usaha atau mengajukan kredit. Program reforma agraria dan legalisasi aset adalah langkah strategis untuk memberikan kepastian dan martabat. Menguatkan koperasi juga penting. Dengan berkoperasi, usaha-usaha mikro yang lemah dapat bersatu, mendapatkan kekuatan tawar, mengakses pasar yang lebih luas, dan menekan biaya produksi.
Menghubungkan yang Terisolasi
Kemiskinan struktural seringkali berkorelasi dengan isolasi geografis. Desa-desa terpencil yang tidak memiliki akses jalan, listrik, dan internet, akan sulit berkembang. Pembangunan infrastruktur dasar —jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan internet— adalah kunci untuk membuka isolasi ini. Ia menurunkan biaya logistik, membuka akses pasar, dan membawa informasi serta peluang baru. Pembangunan pedesaan yang terintegrasi, seperti mengembangkan agroindustri atau pariwisata berbasis komunitas, akan membuat pemuda desa tidak perlu lagi berbondong-bondong mengadu nasib ke kota.
Tata kelola yang bersih dan berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan. Semua strategi mulia ini akan sia-sia jika tata kelola pemerintahannya buruk. Korupsi, salah sasaran, dan program yang tumpang-tindih adalah pemborosan dana negara dan pengkhianatan terhadap rakyat.
Pemerintah harus menggunakan data yang akurat dan terpadu untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah obat terbaik untuk mencegah kebocoran. Perlu melihat kemiskinan dan kerusakan lingkungan sebagai dua sisi mata uang yang sama.
Masyarakat miskin seringkali bergantung pada sumber daya alam yang rentan. Bencana banjir atau kekeringan yang dipicu kerusakan lingkungan dapat menghancurkan sumber penghidupan mereka dalam sekejap. Karena itu, program konservasi yang melibatkan masyarakat dan promosi pertanian berkelanjutan adalah bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan.
Mimpi yang Dapat Diwujudkan
Menurunkan angka kemiskinan tentu bukan tugas yang mudah dan instan. Tidak ada “pil ajaib” yang bisa menyembuhkannya dalam semalam. Ia membutuhkan komitmen jangka panjang, konsistensi kebijakan yang melampaui batas periode kepemimpinan serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akademisi.
Mata negara melalui apatur dari pusat hingga daerah, Masyarakat, dan semua pihak (stakeholders) harus beralih dari paradigma ‘mengurusi orang miskin’ menjadi ‘menciptakan ekosistem yang memungkinkan setiap warga negara untuk keluar dari kemiskinan dengan kemampuannya sendiri.’
Ini adalah perjalanan maraton, bukan lari sprint. Dengan pendekatan yang komprehensif, holistik, dan berkelanjutan —yang menyerang akar masalah dari semua sisi— mimpi untuk memutus rantai kemiskinan tentu bukan hal yang mustahil. Ia adalah cita-cita bersama yang layak dan wajib kita perjuangkan.