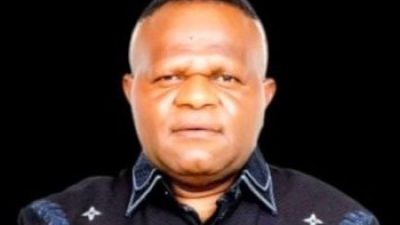![]()
Oleh Ben Senang Galus
Penulis buku Lubang Hitam Kebudayaan Papua
GELORA perjuangan nasionalisme Papua, semakin menggema di seantero Papua. Bak gayung bersambut, gempita nasionalisme Papua belakangan ini didukung oleh pejuang kemerdekaan yang tinggal di beberapa negara di dunia. Secara umum nasionalisme merupakan jiwa dan semangat yang membentuk ikatan bersama, (karena ada common enemy, penderitaan yang sama bertahun-tahun), baik dalam hal kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan demi bangsa dan negara.
Menurut catatan penulis, selama bertahun-tahun berinteraksi dengan beberapa kalangan mahasiswa terutama di kota studi Yogyakarta, terjadi pembelahan (perpecahan) nasionalisme (split of nationalisme) di kalangan mahasiswa. Mereka tidak mempunyai spirit nasionalisme seperti Mohammad Hatta, ketika belajar di Negeri Belanda tahun 1927.
Dengan ungkapan lain, terjadi pasang surut rasa nasionalisme yang ditunjukkan oleh masyarakat Papua. Baik yang tinggal di Papua maupun Papua warga diaspora di kota-kota besar di Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan kota-kota kecil lainnya di Indonesia, mengindikasikan belum mengakarnya nasionalisme Papua pada hati sanubari setiap anak bangsa di Papua.
Nasionalisme Papua hanya bergema ketika ada imperialisme atau ancaman yang datang dari luar saja. Meminjam terminologi I Nengah Suastika (2012) apa yang disebutnya hanya terbentuk dalam tataran “grand narasi” yang diikrarkan oleh para pendiri bangsa dan kalangan elit politik saja?
Ataukah guna kepentingan politik! Sementara pondasi dasar yang semestinya dibangun oleh akar rumput tidak memahami hakikat dan makna dasar nasionalisme Papua. Sehingga berbagai bentuk penyimpangan terhadap hakikat nasionalisme terus terjadi.
Nasionalisme Papua yang telah dibangun awal tahun 50-an adalah dasar kebersamaan identitas (Melanesian collective identity) kini dihadapkan pada tantangan menurunnya spirit masyarakat, memudarnya nilai-nilai nasionalisme, terabaikannya identitas nasional Papua,
Pemikiran di atas cukup merefleksikan betapa kita mengalami “krisis nasionalisme, krisis kebangsaan.” Setidaknya kita mengidap ambivalensi dan ambiguitas tentang nasionalisme yang mampu menggerakkan rakyat untuk mencapai Papua merdeka.
Bahwa ada kekhawatiran, nasionalisme menjadi usang oleh dominasi kapitalisme sumber daya alam dan sebagian akibat formalisme paham kebangsaan oleh oknum yang menyatakan diri sebagai pejuang kampiun nasionalisme, yang ternyata sekadar kamuflase.
Pemimpin yang kuat
Dewasa ini, nasionalisme dan nasionalitas di Papua telah mengalami krisis multi dimensi, membutuhkan solusi yang efektif dan cepat. Bagi Papua, sangat penting memiliki para pemimpin yang kuat, visioner dan legitimate.
Ketiganya merupakan suatu keharusan, sebagai conditio sine qua non mengingat Papua saat ini berada dalam zona bahaya atau zona merah dari sebuah bangsa lemah yang bergerak menuju bangsa yang gagal mencapai cita-cita kemerdekaannya.
Dalam pandangan ini, Papua akan selamat dan terlindung dari bahaya menjadi bangsa yang gagal (failed nation), apabila memiliki kepemimpinan yang kuat dan visioner serta ada komitmen untuk membantu Papua dalam bidang ekonomi dan rekonstruksi sosial, khususnya dalam upaya penegakan hukum dan demokrasi.
Papua akan menghadapi masa-masa sulit dalam beberapa tahun mendatang dan memerlukan kepemimpinan yang berbobot dan kuat untuk menghindari terjadinya bangsa gagal mewujudkan cita-citanya mencapai kemerdekaan.
Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai upaya terstruktur yang akan meruntuhkan rasa nasionalisme masyarakat Papua. Bahkan “terkesan” nasionalisme Papua belum menemukan “bentuk yang pasti” (definite shape), yang dapat dijadikan pedoman oleh para pejuang baik di level lokal maupun internasional maupun generasi penerus bangsa Papua.
Dengan demikian, apa yang didengung-dengungkan oleh “penguasa lokal atau para pejuang OPM” tidak sejalan dengan tindakan dan tata laku yang teraplikasi dalam kehidupan keseharian. Para pemuda terutama yang “mengikuti trend mode ala perjuangan Papua tapi pola pikirnya masih “ambigu”. Apakah ini merupakan bentuk “imperialisme modern” yang sengaja membangun karakter masyarakat Papua dengan “budaya Indonesia”?
Memperkuat nasionalisme
Nasionalisme per definisi seringkali dikonotasikan dengan aspek-aspek emosional, kolektif, idola dan syarat memori histories seperti seperasaan, senasib, sependeritaan. Faktor memori histories adalah faktor kecenderungan yang dibangun untuk menumbuhkan rasa perasaan “bersatu” dalam sebuah konsep kebangsaan tertentu.
Menurut Ernest Renan, seorang teoritikus Perancis dalam esai terkenalnya, What is Nation? menyebutkan bahwa nation adalah jiwa dan prinsip spiritual yang menjadi ikatan bersama baik dalam pengorbanan (sacrifice) maupun dalam kebersamaan (solidarity).
Sementara menurut Benedict Anderson, nation didefinisikan sebagai “sebuah komunitas politik terbayang” (an imagined political community). Nation pada awalnya lebih dalam bentuk imajinasi pikiran belaka. Namun nation kemudian terbayangkan sebagai komunitas, dan diterima sebagai persahabatan yang kuat dan dalam (deep horizontal comradeship).
Dalam semangat inilah nasionalisme Papua muncul sebagai satu ikatan bersama melawan kolonialisme dan imperialisme Indonesia (Socrates Yoman, 2021). Di sini, nation dan nasionalisme dipakai sebagai perasaan bersama oleh ketertindasan kolonialisme dan imperialisme Indonesia, menurut beberapa tokoh pejuang kemerdekaan Papua, dan oleh karena itu dipakai sebagai senjata ampuh untuk membangun ikatan dan solidaritas kebersamaan melawan kolonialisme dan imperialisme.
Nasionalisme saat itu tergolong nasionalisme yang diciptakan. Seperti ditulis Eriksen (Ethnicity and Nationalism) bangsa adalah sebuah komunitas yang diharapkan terintegrasi dalam hal budaya dan identitas diri secara abstrak dan anonim. Oleh sebab itu, semangat nasionalisme harus dijaga dan ditanam, sehingga merasuk ke darah dagang setiap orang Papua, tidak peduli di mana dia lahir dan dari suku apa orang tuanya berasal.
Bagaimanakah nasionalisme Papua sekarang? Di era otonomi daerah atau otonomi khusus ini makna nasionalisme justeru terasa kabur. Bahkan sebagai akumulasi dari sejarah perkembangan nasionalisme itu sendiri, nasionalisme tak jarang disebut-sebut sebagai suatu yang usang, ketinggalan zaman, menurut penafsiran beberapa tokoh masyarakat.
Kalau kita mau belajar dari masa lalu, tahun 50-an bangsa Papua pernah memiliki rasa nasionalisme yang begitu tinggi menjelang dan di awal kemerdekaan Papua tahun 1961, sekurang-kurangnya tiga hal.
Pertama, bangsa Papua menghadapi musuh yang sama (common enemy), penjajahan Belanda. Akibat musuh yang bersama ini telah membentuk rasa solidaritas yang sangat tinggi untuk menghadapi dan mengusir musuh.
Kedua, berhubungan dengan yang pertama, pada waktu itu bangsa Papua memiliki tujuan yang sama yakni ingin mandiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka.
Ketiga, karena kedua hal di atas bangsa Papua menjadi merasa senasib seperjuangan semua merasa tertindas dan teraniaya oleh bangsa Indonesia. Di sinilah terjadi sinergi dari segenap lapisan masyarakat dengan kemampuan masing-masing untuk berjuang mengubah nasib bersama.
Perjalanan sejarah Papua kemudian telah menyebabkan kesadaran akan nasion itu menggelora. Kenapa? Di antaranya karena ketidakadilan, pemusnahan etnis, penghancuran sumber daya alam. Karena itu, kenyataan masa lalu itu hendaknya menjadi tantangan besar bagi Papua dalam memperjuangkan nasibnya (self determination), bagaimana agar kesadaran sebagai nasion itu tetap bisa dijaga, dipertahankan, diperkuat dan dilestarikan.
Tetapi dengan adanya otonomi daerah dan otonomi khusus, dan pemekaran daerah otonomi baru (kabupaten dan provinsi) terlihat adanya tendensi ke arah disintegrasi nasional Papua. Hampir semua daerah, kecuali yang sudah mapan melakukan dua hal. Pertama, pencarian jati diri dari akar sejarahnya yang paling dalam. Kedua, revitalisasi paham-paham yang menunjukkan primordialisme kedaerahan.
Apabila kita simak dengan seksama makna nasionalisme yang dikemukakan oleh Ernest Renan di atas, apa yang dikritisi oleh para penulis maupun para cendekiawan Papua (baca postmodernist), yakni ’linguinnya bangsa Papua’ yang dialami memiliki heterogenitas yang tinggi, dapat dipahami sebagai munculnya gejolak fenomena ethno-nationalism maupun religion-nationalism (mengarah ke teokrasi).
Munculnya kedua gejolak fenomena nasionalisme ini, secara historis masing-masing memiliki alasan tersendiri sesuai dengan konteks kepentingan sosial, budaya, ekonomi dan politik Papua. Barangkali hal inilah yang dianggap oleh kalangan postmodernist sebagai sisi gelapnya nasionalisme.
Dengan kata lain, pada satu sisi sejak pengumuman kemerdekaan 1961, nilai-nilai nasionalisme sudah berkelindan dengan sikap dan perilaku politik para pendiri bangsa Papua dan segelintir elit-elit nasional maupun lokal. Tetapi pada sebagian besar warga atau rakyat Papua yang tersebar di pelosok-pelosok negeri Papua belum demikian.
Artinya sikap-sikap politiknya masih didominasi oleh nilai-nilai primordial (keagamaan dan kesukuan). Inilah transisi nasionalisme di Papua yang dianggap oleh kalangan postmodernist belum sepenuhnya terkonstruksi secara sosio politik dalam konteks-konteks sosial kewarganegaraan (negara-bangsa).
Apa yang dikatakan Ernest Renand di atas mau menegaskan suatu hal bahwa nation atau nasionalisme adalah jiwa dan semangat yang membentuk ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan. Identitas nasional merupakan produksi kesadaran kesatuan identitas nasional Papua (production of awareness of national identity unity Papua) tidak pertama-tama muncul berdasarkan kesadaran akan kesatuan latar belakang budaya, etnis, agama, atau golongan sosial.
Tetapi lebih merupakan strategi produk sosial, budaya dan politik untuk membangun dan memproduksi identitas diri (self identity) baru sebagai penegasan identitas yang diimposisikan kekuatan penjajah.
Para nasionalis Papua menganggap negara adalah berdasarkan beberapa “kebenaran politik” (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu “identitas budaya”, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat atau gabungan kedua teori itu (bandingan dengan I Nengah Suastika, 2012).
Dalam pandangan kaum anti kemerdekaan Papua, simbol-simbol seperti lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua dan bendera Bintang Kejora bahkan bahasa serta lambang-lambang kenegaraan lainnya hanyalah merupakan mitos dan legenda bagi nasionalisme dan tegaknya negara-bangsa Papua. Bila masih bersandar pada hal-hal yang demikian dianggap hanya menjadi beban karena cukup besar biaya yang dikeluarkan untuk itu.
Bagi Kenichi Ohmae (2005) misalnya, penulis buku The Next Global Stage: Tantangan dan Peluang di Dunia Yang Tidak Mengenal Batas Kewilayahan berpandangan posmodernisme, kegiatan ekonomilah yang penting. Sebab, di samping lebih rasional juga lebih menguntungkan bagi pembinaan sebuah negara-bangsa (termasuk nasionalisme).
Kenichi menasehati dan mengingatkan bahwa citra abad ke-21 ini mencakup 4-I, yaitu industri, investasi, individual, dan informasi. Menurutnya hal ini sebaiknya dijadikan kebijaksanaan bagi negara (Subiyakto, 2005)
Selain itu, agar sebuah bangsa maupun nasionalisme dapat terjaga dan berkelanjutan penting juga menciptakan “the emergence of region states”, suatu kawasan (daerah/negara) berikat atau “negara-wilayah”. Negara-wilayah yang dimaksudkan Ohmae di sini bukanlah unit politik melainkan unit ekonomi. Contohnya “Sijori” (Singapura, Johor, Riau) atau MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) dan yang jenis lainnya.
Namun, yang penting juga menurut Ohmae adalah hadirnya multinational corporation karena dapat berperan dan lebih dapat memberikan keuntungan yang tidak langsung kepada negara-negara nasional baru. Menurutnya lagi, bahwa untuk sebuah nasionalisme memang perlu biaya (cost) dan menjalankan proteksionisme merupakan suatu dalih belaka bagi kepentingan penguasa atau kekuasaan (Subiyakto, 2005)
Sementara itu, dalam pandangan dan sudut tinjauan yang berbeda, Thomas H. Eriksen (1993), penulis buku Ethnicity & Nationalism: Anthropological Perspectives mengemukakan, untuk nasionalisme, terutama prinsip politik, politik dan unit nasional harus kongruen.
Nasionalisme sebagai sentimen atau gerakan, paling dapat didefinisikan dalam istilah prinsip ini. Sentimen nasionalis adalah rasa marah terangsang oleh pelanggaran prinsip atau perasaan kepuasan terangsang oleh pemenuhan.
Menurut Gellner (1983), suatu gerakan nasionalis adalah salah satu ditekan oleh sentimen semacam ini. Nasionalisme adalah ideologi yang berpendapat bahwa etnis (kelompok) mereka harus mendominasi negara.
Oleh karena itu, suatu negara bangsa adalah sebuah negara didominasi oleh kelompok etnis, dengan penanda identitas (bahasa atau agama) yang sering tertanam dalam simbolisme resmi dan undang-undang.
Nasionalisme dalam masyarakat polyethnic, dapat digambarkan sebagai konflik antara kelompok-kelompok etnis didominasi melawan kekuatan mendominasi dalam kerangka sebuah negara bangsa modern (Lyotard, JF. 1984).
Para pakar politik sering mendapati suatu bentuk penjelasan yang menarik dalam nasionalisme karena di dalamnya menjanjikan penjelasan mengenai sebab-sebab konflik yang tersembunyi di antara berbagai kelompok etnik. Di dalam hal ini, nasionalisme bukan keyakinan melainkan kekuatan yang bisa menggerakan sekumpulan orang melakukan perbuatan sekaligus menganut suatu keyakinan.
Nasionalisme sebaiknya dianggap sebagai seperangkat gagasan dan sentimen yang secara lentur merespons, dasawarsa demi dasawarsa, situasi-situasi baru —biasanya situasi-situasi sulit— yang memungkinkan rakyat menemukan jati dirinya.
Di lain pihak, Tom Nairn (1977) mengemukakan pandangan yang meragukan wacana tentang nasionalisme, yang dianggapnya menampilkan keraguan diri. Nairn menyatakan bahwa kode genetik dari semua nasionalisme menunjukkan tanda-tanda yang bertentangan dengan apa yang ia sebut “kesehatan” dan “ketidaknormalan”: dalam bentuk-bentuk prasangka, sentimen, egoisme kolektif, agresi, dan sebagainya.
Nasionalisme merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia. Tak ada satu pun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali.
Berakhirnya perang dingin dan semakin merebaknya gagasan dan budaya globalisme (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat akseleratif, tidak dengan serta-merta membawa lagu kematian bagi nasionalisme Papua.
Nasionalisme Papua lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik karena dia berakar pada etnisitas dan budaya pramodern. Kalaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalis pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya ketika terjadi krisis identitas kebudayaan.
Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar dalam membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya.
Perspektif etnonasionalisme yang membuka wacana tentang asal-muasal nasionalisme berdasarkan hubungan kekerabatan dan kesamaan budaya. Nasionalisme memiliki kapasitas memobilisasi massa melalui janji-janji kemajuan yang merupakan teleologi modernitas.
Dari sudut pandang postmodern gerakan nasionalisme mengakar pada entitas yang melekat pada pendirian dan kedirian manusia yang memiliki keragaman identitas, pola pikir, tata laku, dan pedoman hidup yang membedakannya dengan yang lain.
Oleh karena itu tak ada satu bangsapun yang dapat “mereduksi” bangsa lainnya karena alasan ketidakmapuan, kurang berdaya atau lebih rendah dari bangsanya (Lyotard, JF 1984).
Sebagaimana dikatakan Helius Sjamsudin (2007), bahwa pemikir postmodern dan dekonstruksi adalah belajar mengkontekstualisasi, mentoleransi relativisme dan pluralisme. Mereka menolak pikiran tentang kebenaran universal (universal truth) yang mencari metanarrative atau grand theory.
Mereka menolak otoritas yang secara implisit atau eksplisit mendukung hak istimewa dari suatu teori atas teori yang lain. Mereka menggantikannya dengan suatu titik pandang parsial dan relativistik dengan menekankan ketidak pastian dan dasar menengahi dalam pembangunan teori.
Bagi postmodern, gerakan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa penjajah merupakan bentuk dominasi atas bangsa yang lainnya karena merasa lebih mapan, modern, pintar, terhormat dan memiliki “kekuasaan” untuk memimpin bangsa yang lemah.
Asumsi dasar dari proses imperialisme adalah kemamapan bangsa penjajah, perkembangan teknologi, dan pengetahuan ilmiah yang dapat diperlakukan secara universal pada semua masyarakat yang ada di dunia, tanpa memandang keragaman budaya, adat, tradisi dan kondisi sosial-geografis masyarakat yang dijajah (Benedict Anderson 1999).
Membawa implikasi
Kebijakan otonomi daerah maupun Otonomi Khusus Papua yang tidak terkontrol membawa implikasi pada beberapa hal. Pertama, semakin menurutnya mutual trust di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pada saling percaya itu modal utama, maka Francis Fukuyama, dalam The End of History and Last Man (1999) menyebutnya sebagai social capital.
Kedua, Kebanggaan etnik terhadap asal usul keturunan, zaman keemasan, bahasa, budaya yang tak mengabaikan hak-hak budaya minoritas, berpotensi mendorong kehidupan demokratis. Sebaliknya ketidakmampuan menjinakan aspek keetnikan tadi, bisa mengarah pada chauvinisme, rasisme, bahkan fasisme. Kebanggaan etnik semacam itu muncul akibat tiadanya ruang bagi pengungkapan politik perasaan kebangsaan.
Dalam negara-negara yang sedang menghadapi konflik, despotisme (kelaliman) juga berlangsung di tengah-tengah masyarakat dan antarmasyarakat. Konflik semacam ini bukan mustahil akan melahirkan “etno-demokrasi” sebagai ancaman terhadap demokrasi yang damai.
Demokrasi etnis, apabila tidak mendapatkan perhatian, justeru potensi menjadi semakin radikal dan ekstrem, lalu mengarah pada etno-nasionalisme. Nasionalisme Papua yang belum terlalu kukuh, mulai terkoyak ketika ciri etnisitas makin menonjol, yang kemudian dibungkam secara represif dengan tutup SARA.
Ketika itu pemerintah pusat melaksanakan program pembangunan, tetapi dalam kenyataan mengeruk kekayaan Papua, tetapi tidak dikembalikan ke Papua. Perasaan bahwa daerah telah diperas oleh “orang-orang pusat, tanpa menyadari bahwa orang-orang pusat yang korup itu juga berasal dari berbagai suku.
Batas-batas etnis (ethnic boundaries) yang semula hanya pada aspek kesenian menjadi batas budaya (cultural boundaries) dalam arti yang lebih luas. Kemudian hal itu semakin menguat dengan batas-batas teritorial (territory boundaries) yang setelah Soeharto jatuh perasaan itu pun berani muncul dalam isu Aceh merdeka, Papua merdeka, Riau merdeka, Bali merdeka, yang merupakan bentuk reaksi kemarahan terhadap ketidakadilan.
Hati yang terluka itu kemudian mempertebal ethnic boundaries, yang diikuti territory boundaries berdasarkan etnis serta perasaan “kami” dan “mereka” yang mengental. Demikian pula korporatisme bila tidak dikendalikan, ia pada akhirnya mengancam eksisten demokrasi dan nasionalisme Papua.
Maka salah satu jalan sebagai solusi adalah memperkuat nasionalisme di kalangan generasi muda Papua melalui media gerakan kebudayaan. Tentunya juga media cetak maupun elektronik terus menerus mempromosikan nasionalisme kebangsaan Papua, tanpa mencurigai apalagi membunuh identitas etnis yang saat ini berkembang di beberapa daerah.
Namun, yang harus dicegah adalah sikap chauvinisme demokrasi yang arogan, etnonasionalisme berlebihan, dan etno demokrasi yang berlebihan yang mengancam demokrasi dan nasionalisme Papua. Bangsa Papua sebagai bangsa beradab tentu harus memelihara peradaban dan entitas yang hidup di seluruh tanah Papua. Inilah nasionalisme Papua sesungguhnya.