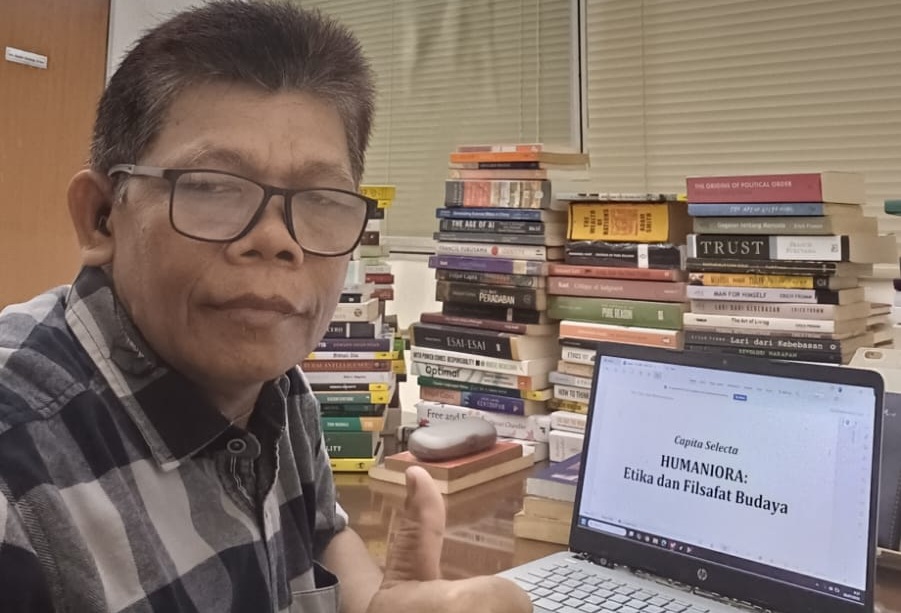Oleh Kasdin Sihotang
Dosen Filsafat Moral Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
SITUASI sosial bangsa ini belakangan kurang kondusif. Nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pancasila diingkari oleh segelintir orang dengan sikap intoleran. Kita melihat tindakan-tindakan anarkis sekelompok orang yang mengganggu bahkan merusak tempat beribadah. Kita sebutkan contoh apa yang terjadi di Bandung, lalu berlanjut di Sukabumi.
Belum lupa dari ingatan tentang Sukabumi, muncul lagi penolakan rumah ibadah di Kubu Raya Kalimantan Barat. Dan yang paling terbaru apa yang terjadi di Padang, Sumatera Barat. Tindakan mereka tidak mencerminkan manusia yang beragama, melainkan orang yang seperti kesetanan. Bringas, sangar dan menghancurkan dengan begitu ganas bangunan-bangunan yang ada. Sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas dilakukan.
Indikasi apa yang muncul dengan mempertontonkan perilaku destruktif demikian? Dari nalar sosial, bahwa Indonesia adalah masyarakat religius sebenarnya tindakan premanisme itu tidak bisa diterima nalar sehat. Bagaimana mungkin orang-orang yang dalam sisi lahiriahnya tekun menjalankan ibadah keagamaannya bersemangat bahkan berapi-api mengganggu yang lain yang menjalankan ibadahnya, bahkan merusaknya dengan bringas.
Paling menyedihkan adalah alat negara tidak hadir di sana, malah diam seribu bahasa, bahkan ada yang ikut terlibat di dalamnya sebagai pengompor tindakan bringas demikian seperti yang terjadi di Sukabumi belakangan ini.
Degradasi Etika Kebangsaan
Terhadap fakta demikian dapat dikatakan bahwa etika kebangsaan kita semakin merosot, bahkan mungkin sudah sampai pada titik yang paling mengkhawatirkan. Di akar rumput terjadi dikotomi sosial yang bersifat absolut, yakni kelompok yang berbeda dengan kelompoknya bukan dianggap sebagai sesama bangsa, melainkan sebagai orang lain, bahkan mengerikan dianggap sebagai musuh yang harus ditaklukkan.
Naluri kehewanan lebih hidup daripada naluri kemanusiaan. Mereka yang berbeda keyakinan, suku dan agama dianggap lawan. Pola pikir dikotomistik ini sungguh-sungguh membenarkan apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes dengan ungkapan “homo homini lupus”, manusia menjadi serigala bagi yang lain.
Orang-orang yang bermental demikian telah mengubur dalam-dalam hakikat kemanusiaannya sebagai homo rationale, yakni makhluk yang dibekali akal budi untuk mempertimbangkan perbuatannya, apalagi sebagai homo sapiens, manusia yang dianugerahi hati nurani untuk bersikap bijak dalam relasi sosialnya. Yang tumbuh dan berkembang adalah naluri kebinatangan yang diungkapkan dengan sikap-sikap brutal. Bahkan brutalisme itu seolah-olah menjadi bagian dari identitas kehidupannya. Sungguh memprihatinkan memang.
Tumbuh dan berkembangnya mentalitas brutalisme tersebut tidak bisa terlepas dari minimnya kesadaran tentang hukum negara yang mengatur penghargaan pada perbedaan itu. Dalam kurun waktu 80 tahun merdeka tentu aturan demi aturan tentang kehidupan bersama dalam ranah sosial dan religius sudah ada, bahkan banyak. Dan aturan itu tentunya bukan pepesan kosong, tetapi memiliki esensi yang mendasar dan punya filosofi yang kuat.
Lihatlah misalnya aturan Menteri Agama tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Di surat keputusan bersama itu ada muatan tentang tugas masing-masing kepala daerah dan peranan dari para pemuka agama yang sangat bagus dan dapat membawa kesejukan dalam hidup bersama.
Namun sosialisasi peraturan ini pada masyarakat, lebih tokoh-tokoh agama belum intensif tidak begitu besar, jika tidak mau dikatakan nihil. Sebagai RT di salah satu perumahan sudah lebih dari dua tahun, penulis belum pernah mendapat undangan tentang hal-hal seperti ini. Peraturan dua menteri itu masih sebatas hitam di atas putih dan lebih menjadi onggokan kertas yang ditempatkan di gudang.
Dalam SK Nomor 8 dan Nomor 9 2006 itu dan aturan yang berhubungan dengannya hanya diketahui oleh tataran elit, namun tidak merambah sampai ke masyarakat akar rumput. Kebanyakan tokoh agama juga jarang membaca aturan-aturan itu. Jangankan membaca.
Usaha mengetahuinya pun mungkin jarang. Dan kalaupun mungkin pernah membacanya, dia sendiri tidak merasa berkepentingan untuk mensosialisasikannya kepada umatnya. Justru sejumlah tokoh agama lebih sibuk untuk mendengungkan narasi-narasi permusuhan kepada mereka yang berbeda keyakinan di tengah-tengah umatnya.
Dan yang membahayakan bahwa apa yang disampaikan itu menjadi pegangan bagi keluarga-keluarga umatnya. Maka ceramah-ceramah itu diteruskan kepada anak-anak oleh orang tua. Bahkan anak-anak dicekoki dengan sikap eksklusif itu dalam label-label tertentu kepada anak-anak yang berbeda keyakinan dengan mereka.
Begitu juga selanjutnya, kelak anak-anak berkeluarga, meneruskan apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya sebagai penerusan dari ajaran tokoh agama itu. Jadi semangat permusuhan itu diteruskan secara berantai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sesuatu yang sangat mengkhawatirkan secara etis dan sosiologis.
Tiga Upaya
Di usia menjelang 80 tahun mentalitas kolonialisme yang merasa diri sebagai penguasa ternyata masih bercokol lekat dalam alam pikiran masyarakat. Bagaimana menyikapi situasi demikian? Menurut hemat saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara serius dan mendesak oleh berbagai kalangan.
Pertama, dari sisi pemerintah. Pemerintah memiliki peran strategis dan punya tanggung jawab untuk membuat rakyat itu sadar tentang dirinya dan kehadiran orang lain. Seperti ditegaskan oleh Maeve McKeown dalam bukunya, With Power Comes Responsibility (2025), pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.
Dia bahkan sangat memiliki andil sebagai agen dan penegak keadilan sosial itu di masyarakat. Dasarnya apa? Menurut Maeve adalah kekuatan (power) yang dimilikinya. Pemerintah adalah elemen negara yang seharusnya berdaya untuk itu. Dan dia harus menjalankan fungsi itu sebagai wujud dari tanggung jawab moralnya sebagai abdi masyarakat.
Bagi saya, dengan rujukan pada ide brilian Maeve McKeown di atas, pemerintah sebagai institusi mempunyai fungsi etis. Fungsi etis maksudnya apa? Yakni memiliki tugas dan tanggung jawab membuat masyarakat sadar dan tahu dengan baik aturan-aturan yang dibuatnya untuk kenyamanan dan keamanan serta kedamaian dalam hidup bersama. Menurut hemat penulis, kesadaran tentang fungsi etis pemerintah itulah yang belum, bahkan kurang mendapat perhatian dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Perjumpaan interpersonal di antara warga merupakan yang sangat penting menghidupkan pengakuan perbedaan. Artinya, hubungan yang baik dan empatik di antara warga yang berbeda keyakinan, suku, ras dan agama hanya terjadi kalau perjumpaan terjadi secara intensif dan berkelanjutan.
Emmanuel Levinas dan Gabriel Marcel dua filsuf mengamini bahwa perlunya perjumpaan terus menerus di antara warga masyarakat yang berbeda, demi tercipta dan hidupnya tanggung jawab satu terhadap yang lain. Ini berarti apa? Seluruh aparat pemerintah perlu lebih berdaya lagi dan menyadari sungguh-sungguh fungsi etis, dan fungsi legalnya sebagai aparat yang memberi ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat.
Kedua, semakin intensifnya pendidikan berbasis multikultural. Satu ciri masyarakat Indonesia adalah bahwa ia hidup dalam kebhinekaan dalam ragam hal. Ciri ini tidak bisa diingkari dan tidak pula bisa ditolak. Dalam kondisi demikian, tentu setiap kelompok memiliki kecenderungan untuk menghadirkan identitasnya, karena dengan identitas itulah ia menunjukkan keberadaannya.
Francis Fukuyama dalam Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment (2018) menyatakan bahwa di era teknologi digital ini, setiap orang ingin menunjukkan identitasnya. Dan itu hal yang wajar dan harus diberi ruang. Identitas yang beraneka ragam itu merupakan sebuah kekayaan yang memberi warna indah dalam hidup bersama.
Hanya saja diingatkan oleh Fukuyama agar perbedaan identitas itu dikelola dengan baik. Artinya apa? Identitas itu tidak dijadikan sebagai jalan untuk mempertentangan satu kelompok identitas dengan kelompok lain yang memiliki identitas berbeda. Fukuyama mengusulkan agar pengetahuan dan kesadaran bahwa adanya identitas berbeda itu sebagai tahap awal dalam membangunkan pengakuan terhadap yang lain.
Apa yang digagaskan oleh Fukuyama sangatlah tepat dan kontekstual dengan situasi eksistensial dan krusial bangsa ini. Seperti sudah dikatakan bahwa bangsa ini ditandai oleh pluralitas. Dan ini berarti ada berbagai macam identitas sosial yang hidup di masyarakat.
Mengikuti apa yang dikatakan oleh Fukuyama kesadaran akan situasi bangsa yang plural itu merupakan tahap awal yang perlu ditumbuhkembangkan di masyarakat demi meredam tumbuh kembangnya jiwa-jiwa intoleran yang akut seperti terjadi akhir-akhir ini. Dalam hal ini pendidikan multikultural menjadi sangat relevan dan urgen.
Ketiga, pedagogi inklusif. Dalam kuliah akhir semester Genap 2024-205 lalu di salah satu perguruan tinggi, seorang mahasiswa dari kelompok presentasi Pancasila bertopik “Nilai-nilai Sila Pertama”, seorang mahasiswa dalam penutup presentasinya mengatakan begini ”Kita generasi muda perlu bersifat inklusif, berpikir terbuka. Apalagi di zaman sekarang, di era komunikasi digital ini, tidak ada untungnya berpikir tertutup, picik dan intoleran. Yang ada justru ruginya”.
Kata-kata mahasiswi tersebut menggembirakan, karena kata-kata itu keluar dari generasi muda milenial. Apa yang dikatakan mahasiswa tersebut merupakan sesuatu yang sederhana, namun bermakna. Sikap inklusif adalah tuntutan di era komunikasi digital ini, tanpa mengabaikan berbagai ekses negatif dan ragam implikasinya.
Pentingnya Inklusivitas
Kehadiran teknologi digital telah membuat dunia bagaikan sebuah global village (kampung global), seperti ditulis oleh Marshall McLuhan, ahli komunikasi dari Kanada dalam bukunya Understanding Media: The Extensions of Man (1964). Di kampung global village inklusivitas menjadi sikap dan pola hidup yang penting.
Menurut Marshall, sesuai dengan etika deontologi Immanuel Kant, sikap inklusif itu penting demi efek yang diperoleh dan perwujudan hakikat manusia sebagai makhluk bermoral.
Etika deontologi menegaskan bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk menghargai martabat. Ini berarti ia harus keluar dari dirinya sendiri, dan membuka diri bagi orang lain. Keterbukaan ini merupakan sisi kemanusiaan yang mendasar dan kodrati alamiah manusia.
Peter L Berger dalam Homeless Mind: Modernization and Consciousness (1974) mengatakan, setiap orang ingin keluar dari dirinya, yang diistilahkannya dengan eksternalisasi. Eksternalisasi adalah modal utama bagi manusia untuk mendalami hidupnya ( internalisasi) sebelum ia berbuat atau menghasilkan sesuatu (objektivasi).
Keluar dari diri merupakan kategoris (keharusan) bagi manusia. Dalam teori deontologi Immanuel Kant, inklusivitas berkaitan dengan kewajiban moral untuk menghargai dan mengakui serta menerima nilai-nilai kemanusiaan dalam diri setiap pribadi.
Melihat intensi inklusivitas itu tepat penegasan Prof Dr Hj Siti Nur Azizah tentang pentingnya membudayakan dan penguatan budaya inklusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bukunya Negeri Inklusi, Bukan Ilusi (2025) itu putri Wakil Presiden RI 2019-2024 Ma’kruf Amin menyatakan bahwa mentalitas inklusif masih sangat lemah. Sikap ini belum menjadi sebuah karakter pribadi di masyarakat. Karena itu pembentukan karakter ini butuh proses.
Yang menarik dalam penegasan guru besar hukum itu ialah bahwa pembentukan karakter inklusif itu tidak bisa terjadi hanya dalam periode tertentu atau bersifat aksidental, melainkan harus terus menerus digaungkan dan diimplementasikan dalam ranah hidup bersama.
Menurut Nur Azizah, jati diri bangsa Indonesia terhiasi dengan keragaman yang justru akan hidup indah, ketika inklusivitas menjadi realitas yang dihidupi setiap pribadi. Nur Azizah lebih lanjut menyatakan bahwa inklusivitas harus menyeruak ke berbagai aspek kehidupan baik dalam bidang ekonomi, politik dan kehidupan beragama, lebih-lebih dalam bidang pendidikan.
Menurutnya, pendidikan merupakan kunci inklusivitas. Sebagai proses pengembangan karakter dan kreativitas, dunia pendidikan bertanggung jawab mengenalkan nilai-nilai dasar kemanusiaan, termasuk keunikan yang dimiliki setiap orang. Peserta didik perlu dibekali dengan pola pikir terbuka, yang membentuk sikap terbuka mereka.
Para pendidik pertama-tama harus memiliki pola pikir terbuka (inklusif) sebelum menanamkan sikap yang sama pada peserta didik. Dasarnya adalah budaya Pancasila. Kita harus membekali generasi selanjutnya yang akan menahkodai bangsa ini di kemudian hari dengan nilai-nila inklusivitas.
Mulai dari keluarga, berlanjut di ranah pendidikan, dan tak kalah penting dalam hidup bermasyarakat, inklusivitas urgen mendapat perhatian, agar negeri ini tidak hidup dalam ilusi.
Dari paparan di atas sangat jelas bahwa dalam menyikapi tumbuh berkembangnya tindakan destruktif kelompok-kelompok intoleran terhadap masyarakat yang berbeda keyakinan kerjasama antar elemen bangsa untuk melakukan konsientisasi atau penyadaran tentang eksistensi bangsa ini sebagai bangsa yang plural dalam bingkai kesatuan sangatlah mendesak dilakukan.
Penggerak untuk ini seperti dikatakan oleh Maeve McKeown seyogianya adalah pemerintah, karena dia punya kekuatan untuk itu. Namun tokoh-tokoh agama juga perlu mendukung upaya pemerintah itu.
Singkatnya, fungsi etis pemerintah dan fungsi legalnya haruslah semakin kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat. Jangan hanya menjadi pemadam kebakaran masalah sosial. Tindakan antisipatif jauh lebih baik daripada tindakan kuratif.
Karena itulah system of intelligence quotient (SYQ) seperti digagaskan oleh John Mackey dan Raj Sisodia dalam Conscious Capitalism (2014) haruslah dimiliki oleh para abdi negara baik di tingkat pusat maupun daerah demi terwujudnya kerukunan yang sejati di tengah masyarakat.
Inti SYQ, membuat kebijakan, mengidentifikasi masalah, mengetahui dampak negatif masalah jika terjadi, dan melakukan sesuatu agar dampak negatif itu tidak terjadi. Jadi berpikir komprehensif dan efektif. Semoga.