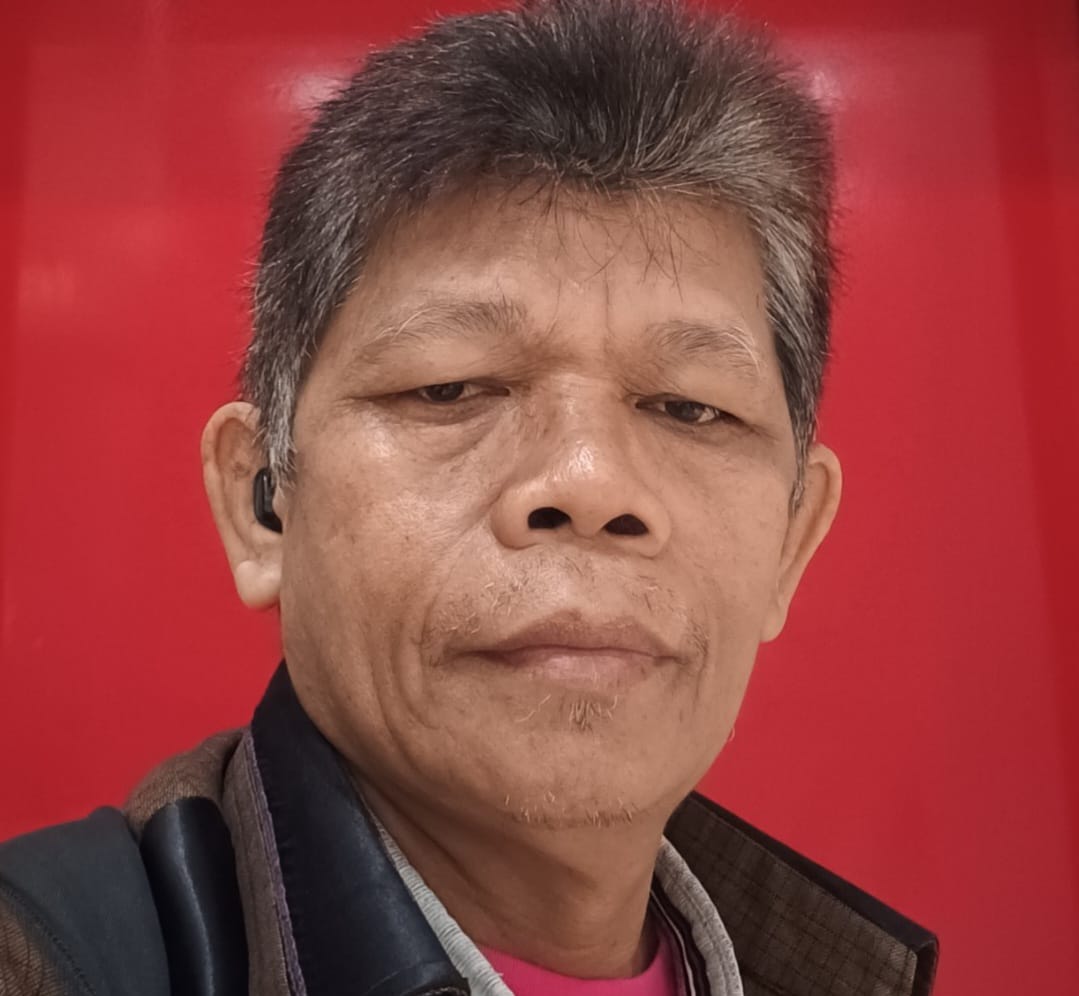Oleh Kasdin Sihotang
Dosen Filsafat Moral Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
DALAM kehidupan berbangsa dan bernegara, satu nilai etis yang minus dari kehidupan bersama, lebih-lebih pejabat publik adalah etika kepedulian. Etika ini sesungguhnya menjadi dasar bagi terwujudnya keadilan sosial.
Carol Gilligan dalam bukunya berjudul In A Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development (1996) menunjukkan secara jelas bahwa kepedulian merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Etika ini lebih-lebih dilihatnya dominan dalam diri kaum perempuan, yang membedakannya dengan kaum laki-laki. Nilai ini sesungguhnya sangat mendasar dalam mewujudkan keadilan sosial.
Logika yang dibangun Carol Gilligan adalah pola pikir induktif dan naratif, bukan deduktif dan formal teoritis. Maksudnya apa? Sebagaimana pola pikir induktif berbasis pada realitas konkrit atau pengalaman nyata sebagai titik berangkat pengambilan kesimpulan premis-premis.
Demikian halnya etika kepedulian berbasis pada pengalaman nyata dan sangat dekat dengan pengalaman kehidupan sehari-hari, lebih-lebih terejawantah dalam apa yang dilakukan oleh seorang ibu dan tentu juga pengalamannya sebagai seorang perempuan.
Bagi Gilligan seorang ibu adalah sebuah kenyataan etis yang paling konkret dalam perjalanan hidup manusia yang berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi anak-anaknya. Ia mengasuh mereka, mendidik, bahkan berkorban untuknya.
Ia bertarung nyata demi kehidupan anaknya. Di dalam dirinya ia melihat anak-anak yang dilahirkannya sebagai bagian dari tubuhnya. Sebagai bagian dari tubuhnya ia merawatnya dengan penuh penuh kasih sayang.
Apa yang tercermin dalam sikap dan pola hidup seorang ibu, yang adalah perempuan, merupakan narasi kehidupan nyata sekaligus mendasar. Karena itu pula pengalaman hidup demikian bersifat naratif. Pengalaman Carol Gilligan bersama dengan kaum perempuan justru memperlihatkan betapa etika kepedulian itu memberi warna positif dalam kehidupan bersama.
Tanggung Jawab Moral
Apa esensi etika kepedulian bagi Carol Gilligan? Seperti sudah dikatakan di atas bahwa etika kepedulian hadir dalam diri seorang ibu. Karena itu esensi etika kepedulian adalah kepekaan dan kasih sayang pada orang lain. Asumsi dasar yang melatarbelakanginya persis seperti apa yang dikomitmenkan oleh seorang ibu, yakni anak adalah bagian dari hidupnya.
Karena itu ia menyayangi dan mengasihi serta mengasuhnya hingga besar dan mandiri. Sang ibu juga berharap apa yang dilakukannya akan diteruskan oleh anak-anaknya kepada siapapun. Di sini keterhubungan dengan yang lain adalah realitas kehidupan manusia.
Dalam bingkai berpikir demikian, sesungguhnya etika kepedulian memuat kepekaan dan kesadaran bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya. Karena ia bagian dari dirinya, maka ia bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan seluruh perjalan hidupnya. Karena itu persis seperti diakui oleh Emanuel Levinas bahwa setiap orang menuntut tanggung jawab di kala ia bertemu dengan orang lain.
Karena itu pula perjumpaan dengan orang lain menurut Levinas selalu bernuansa etis, karena dalam perjumpaan itu tanggung jawab menjadi hal penting. Karena itu pula ketika seseorang menemui atau berjumpa dengan orang lain entah sengaja atau tidak, di sana ada tuntutan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain.
Hidup dalam kebersamaan adalah hal fundamental bagi manusia. Karena itu apa yang ditekankan oleh Emmanuel Levinas selaras dan sejalan dengan pemikiran Carol Gilligan. Intinya adalah jiwa kepedulian kepada orang lain. Basis dari etika kepedulian itu seperti sudah dikatakan di atas adalah kesadaran yang utama tentang keterhubungan diri dengan orang lain dan pengakuan bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya.
Dalam bingkai pemikiran demikian, kehidupan bersama yang baik akan terwujud ketika setiap individu memiliki kepedulian terhadap orang lain. Baginya orang lain adalah bagian dari dirinya, demikian sebaliknya dirinya adalah bagian dari orang lain. Di sana relasi yang terjadi adalah relasi “Aku-engkau” bukan relasi “aku-itu”.
Artinya, setiap orang adalah pribadi yang mendapat pengakuan. Setiap pribadi memiliki harga dan kedudukan yang sama. Berbeda dengan relasi “aku itu” yang ditandai dengan hubungan searah dan sepihak. Yang aktif dan bernilai hanya “aku” sedangkan “itu” hanyalah objek dan dianggap sebagai benda mati yang tidak memiliki fungsi apa, apa selain memenuhi kepentingan si aku.
Karena itulah menurut Gilligan, hubungan yang dibangun oleh seorang ibu dengan anaknya adalah hubungan kemanusiaan, bukan hubungan kebendaan. Cara pandang ini sedikit banyak beririsan dengan pandangan Martin Heidegger sebagaimana tertuang dalam Being and Time (1997) dan pandangan Martin Buber dalam bukunya I and Thou (2020).
Benang simpul pemikiran Martin Heidegger dan Martin Buber dengan Carol Gilligan adalah etika kepedulian itu. Konkritnya, apa yang dipikirkan oleh Carol Gilligan sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan pandangan Martin Heidegger dan Martin Buber tentang relasi manusia. Titik temunya adalah bahwa kehidupan bersama yang ditandai dengan kepedulian pada nilai-nilai kemanusiaan itu, yakni etika kepedulian.
Relevansi dan Aktualitas
Jika kita mengkontekskan dengan situasi bangsa ini, lebih-lebih bercermin dari sila kelima, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, pemikiran Carol Gilligan sangat relevan, aktual bahkan mendesak dijadikan sebagai penguat bagi terwujudnya keadilan sosial di tengah masyarakat. Ada beberapa alasan mengatakan demikian.
Pertama, gagasan Carol Gilligan sangat dekat dengan pengalaman hidup manusia. Kita bisa mengatakan bahwa kehidupan dunia ini hanya bermakna ketika ada kepedulian dalam hidup bersama. Kepedulian sendiri merupakan hakikat sosialitas manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah zoon politicon, yakni makhluk dalam hidup bersama seperti ditegaskannya dalam The Politics (2020).
Apatisme atau ketidakpedulian adalah sikap yang mengkaji hakikat kemanusiaan. Bisa dibayangkan jika kaum ibu tidak mau peduli pada anak-anaknya apa yang terjadi? Tidak akan ada pribadi-pribadi, lebih-lebih pribadi yang bermutu akan mengisi ruang-ruang kehidupan sosial.
Kedua, etika kepedulian mendasari perwujudan keadilan sosial. Seiring dengan pemikiran Aristoteles di atas jelaslah kehidupan bersama akan bermakna ketika di situ kepedulian menyertainya. Kepedulian bersentuhan dengan kehidupan bersama, persis seperti keadilan itu sendiri.
Artinya, kepedulian memang muncul dari pribadi, tetapi dalam ruang publik itu juga harus muncul, bahkan melandasi pribadi artifisial berupa lembaga-lembaga penyelenggara negara. Sebagaimana keadilan tidak saja dituntut dari pribadi, tetapi dituntut dari penguasa negara, demikian halnya kepedulian.
Dalam tataran sosial, tentunya keadilan sosial ini berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini diakui oleh Morris Ginsberg dalam On Justice in Society (2003) dengan definisinya sederhana tentang keadilan sebagai pengakuan hak dan kewajiban yang seimbang.
Artinya, adil terkait dengan pemenuhan apa yang harus dilakukan oleh seseorang dan apa yang akan diperoleh seseorang dari apa yang dilakukannya. Orang dewasa memiliki kepedulian terhadap persoalan ini.
Secara ideologis, keadilan sosial menjadi bagian dari nilai inti etika yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini. Rumusan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mematrikan itu.
Sasaran dan orientasi dari rumusan ini sesungguhnya cukup jelas, yakni kepentingan publik atau masyarakat luas, persis sejalan dengan prinsip ketiga utilitarisme, yakni ‘manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang”.
Ketiga, kepedulian sejalan dengan nilai-nilai religius. Jika kita mengakitkan dengan sila-sila Pancasila, lebih-lebih sila pertama dan kedua, maka kita akan menemukan irisan. Kedua sila ini memang menjadi fondasi bagi terwujudnya keadilan sosial.
Sila pertama dan sila kedua memuat hakikat manusia sebagai makhluk religius dan sebagai makhluk personal, yang tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya sebagai makhluk sosial. Ini sangat tegas diafirmasi oleh filsuf bangsa ini, Nikolas Driyarkara SJ dalam Karya Lengkap Driyarkara (2006).
Menurut Driyarkara, religiositas itu bersentuhan dengan kemanusiaan. Ini berarti orang yang beragama dengan benar mencerminkan hakikat kemanusiaannya dalam berperilaku dan bertindak. Hal ini terarah bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan lebih-pada orang lain.
Karena itu kehidupan religius yang benar memiliki dua arah, yakni arah vertikal dan arah horizontal. Arah vertikal bermaknakan hubungan yang dekat dengan Yang Ilahi dan ajaran-ajarannya, dan arah horizontal berarti hubungan yang akrab itu mewujud dalam perbuatan positif dalam kehidupan bersama.
Penguatan Humanitas
Dalam konteks keadilan sosial, esensi kehidupan religius dan penghayatan humanitas justru memperkuat dan menjadi pendorong bagi seseorang, lebih-lebih pejabat publik yang diamanati tanggung jawab moral untuk peduli kepada kehidupan orang banyak.
Jika dikaitkan dengan pemikiran Gilligan, etika kepedulian merupakan tanda hadirnya nafas dan semangat keibuan dalam kehidupan sosial. Ketika seseorang tidak memiliki semangat dan jiwa demikian, maka tidak mungkin hadir di sana keadilan sosial.
Dalam konteks hidup bernegara dan berbangsa kita, keadilan sosial merupakan prinsip etis yang sangat fundamental dalam pengelolaan kehidupan bersama yang baik dan bermartabat, lebih-lebih yang ditandai dengan identitas keragaman dan kebhinekaan. Chang menegaskan bahwa situasi multikultural membutuhkan keadilan sosial sebagai pondasinya.
William Chang dalam The Dignity of the Human Person in Pancasila and the Church’s Social Doctrine: An Athical Comparative Study (1997) mengingatkan bahwa mewujudkan keadilan sosial memang membutuhkan komitmen individu, lebih-lebih personalitas pejabat dan pengambil kebijakan yang mengurusinya.
Tetapi komitmen ini bukan serta merta cukup datang dari dirinya sendiri, melainkan itu harus dinyatakan dalam kebijakan publik. Dengan kata lain sistem yang sehat dan struktur sosial harus dibangun dengan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir keadilan itu. Akarnya adalah kepedulian.
Franz Magnis Suseno SJ, sudah memulai lama penegasan Willam Chang melalui bukunya Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan (2022). Dalam karya ini Magnis menyatakan secara tegas bahwa mewujudkan keadilan sosial bukanlah urusan individu semata. Itu adalah kepedulian dan tanggung jawab negara yang paling mendasar.
Tugas negara adalah membangun dan menciptakan struktur dan proses yang sehat dalam masyarakat dengan menyentuh segala aspeknya. Magnis bahkan menegaskan tugas negara harus diarahkan ke sini sebagai prioritas. Jadi mengusahakan keadilan sosial merupakan kewajiban paling fundamental abdi negara.
Bagaimana negara harus mewujudkan kepedulian demi terwujudnya keadilan sosial? Satu hal yang paling mendasar menurut Magnis adalah kepedulian pejabat publik akan dampak negatif dari keterlibatannya yang bukan urusan utamanya.
Secara positif dapat dikatakan, keadilan sosial hanya bisa terwujud ketika pejabat publik memiliki keberanian untuk memilah-milah mana urusan bisnis pribadi dan mana yang merupakan kepentingan publik.
Ketika aparat negara menjadikan urusan masyarakat sebagai ladang bisnisnya, maka di situ justru terjadi ketidakadilan sosial. Kendati sangat skeptis dengan pemikiran ini, bagi Magnis, keberanian untuk meninggalkan hal itu adalah cara yang paling tepat dalam mewujudkan keadilan sosial. Kalau tidak, akan terus terjadi kemiskinan struktural.
Apa yang dikatakan oleh Magnis, sesungguhnya juga sejalan dengan apa yang digagaskan oleh Plato. Dalam Republic (1998) Plato menyatakan bahwa keadilan hanya terjadi ketika masing-masing kelas dalam negara, yakni pemimpin, penjaga dan penghasil peduli pada fungsi yang sebenarnya dan menjalankannya.
Fungsi itu apa? Plato merujuk pada tiga fungsi jiwa manusia, yang menjadi dasar bagi tiga kelas negara. Pemimpin harus mengeluarkan kebijakannya secara bijaksana dan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan rasional.
Selain masing-masing status berfungsi sesuai dengan fungsi jiwa, Plato juga menegaskan bahwa keadilan dalam struktur sosial itu hanya bisa terjadi ketika setiap individu mampu menahan diri untuk tidak mencampuri apalagi mengambil alih kedudukan atau posisi yang lain.
Ketika seorang pemimpin ikut berbisnis saat dia menjadi pejabat, ketika seorang tentara aktif memiliki bisnis di mana-mana, terlibat dalam urusan ekonomi dan dekat dengan pebisnis, dan berhasrat untuk melampiaskan keberanian dan keperkasaannya menjadi seorang pemimpin politik, ketika pebisnis juga menduduki jabatan dalam politik, maka situasi ini potensial bagi Plato sebagai kondisi yang mematikan keadilan dalam tugas masing-masing.
Melihat kecenderungan demikian, sejalan dengan pemikiran Plato, benar apa yang dikatakan oleh Magnis tentang pentingnya para pejabat publik memurnikan diri dari deviasi peran dan fungsi jiwa sesuai dengan status masing-masing.
Singkatnya, keadilan sosial terjadi manakala masing-masing bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin, sebagai keamanan, dan sebagai pelaku ekonomi yang sesungguhnya. Struktur kelas dalam negara ini akan terjaga dengan baik ketika masing-masing menjalankan tugas dalam koridor masing-masing.
Salah satu wujud kepedulian pejabat negara dalam mewujudkan keadilan sosial adalah membuka akses dan kesempatan yang sama bagi setiap orang dalam kehidupan bersama. Dalam bidang ekonomi, setiap orang dijamin memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha demi mempertahankan ekonominya.
Karena itu penataan kehidupan ekonomi harus jelas dan transparan serta melibatkan rakyat dalam penentuan kebijakannya. Dalam pendidikan hal yang sama juga diberi ruang. Kepedulian negara harus lebih pada bidang ini dengan fokus utamanya adalah pemerataan.
Dalam bidang budaya, ruang-ruang berekspresi yang tersedia secara luas dan merata adalah wujud dari kepedulian sang pejabat yang perlu mendapat perhatian secara intensif dan luas.
Hal yang juga tidak kalah penting adalah dalam kehidupan beragama, perhatian dan komitmen para pejabat publik merupakan hal yang sangat diperlukan dengan tingkat yang lebih mengingat persoalan ini terus berkembang baik dari sisi gradasi persoalannya naik terus sementara penanganan dan solusinya semakin menurun.
Kewarasan Publik dan Politisi
Memaknai kemerdekaan Indonesia di usia ke 80 nampaknya sila kelima dengan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih perjuangan besar. Kalau tidak mau dikatakan sebagai sebuah utopia, perlu keseriusan dan perhatian dalam hal ini dari pejabat publik baik di legislatif maupun di eksekutif dan yudikatif.
Persis seperti yang digagaskan oleh Carol Gilligan, perlu kebangkitan etika kepedulian dari pejabat publik tentang hal ini. Kita sering menyebut nama bangsa kita ini dengan kata “Ibu Pertiwi”. Di balik dua kata tersebut sesungguhnya tuntutan tanggungjawab sebagai wujud etika kepedulian itu adalah hal yang mendasar.
Ketika seorang menjadi pejabat publik, seyogianya kepedulian itulah yang bergaung dan menggema dalam dirinya: ya kepedulian kepada kesejahteraan rakyatnya, kepedulian pada dampak dari kebijakan yang dibuatnya, ya kepedulian dampak ketika dia sendiri tidak menjalankan tugasnya, kepedulian terhadap kerusakan lingkungan karena membiarkan atau bersekongkol dengan para pebisnis, dan kepedulian kepada masa depan generasi bangsa ini ke depan.
Sikap positif yang sama juga seharusnya tumbuh dan hadir secara nyata dan meluas di tengah-tengah rakyat, bahkan harus mewarnai mentalitasnya. Juga sama lingkupnya, kepedulian masyarakat terhadap situasi politik dan jalannya pemerintahan, kepedulian kepada kebijakan dan pelaksanaan pendidikan, kepeduliannya terhadap kelestarian alam lingkungan, dan tidak kalah penting kepeduliannya terhadap hak-hak orang lain untuk beribadah dan menjalankan hak-hak konstitusionalnya.
Dalam memaknai delapan puluh tahun usia kemerdekaan ibu pertiwi ini, diperlukan kesadaran bersama bahwa negara ini dibangun tidak menjadikan golongan mayoritas, kelompok bangsawan atau kelompok masyarakat yang paling kaya sebagai fondasi sosial atau bahkan sebagai pemilik negara ini, tetapi atas dasar kehidupan bagi semua suku, ras, agama yang ada di dalamnya.
Dalam hal ini, kepedulian publik (public caring) dan kepedulian politisi atau pengelola negara (politician’s caring) mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat yang paling dekat dengan masyarakat diperlukan demi terwujudnya keadilan sosial.