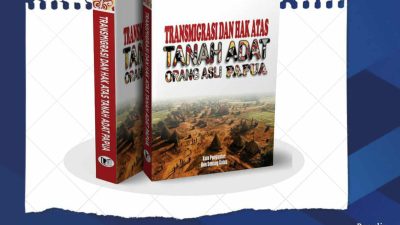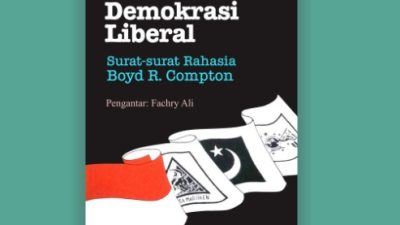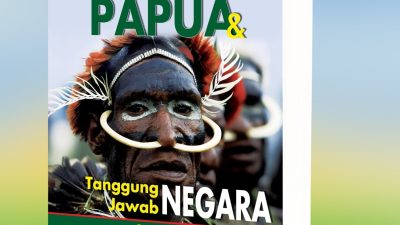Oleh Mariana Sogen
“MARIO, ayah tak memiliki apa pun untuk kautitipkan dalam bekal hidupmu. Hanya cincin ‘kea’ ini yang bisa ayah wariskan—sepotong kulit penyu yang mengeras oleh waktu dan laut. Jangan kaulepaskan dari jarimu, sampai kapan pun.”
Dengan tangan renta yang bergetar, lelaki tua itu menyarungkan cincin itu ke jari manis anaknya. Ucapannya menggema laksana guntur yang membelah sunyi malam. Lampu minyak yang temaram di sudut rumah berdinding bambu menjadi saksi bisu perjamuan batin antara ayah dan anak.
Mereka berpelukan, erat, seakan hendak menahan waktu agar tak bergerak. Air mata menetes tanpa memedulikan usia. “Ayah, terima kasih untuk cincin ini,” bisik Mario di telinga ayahnya yang mulai rabun oleh suara dunia. Sang ayah tak berkata-kata; ia hanya mengangguk perlahan dan menepuk bahu anaknya, seolah menanamkan restu lewat sentuhan.
Di tenda, para juventuda telah berkumpul di bawah dentum musik yang memecah udara malam. Aroma daging kus-kus, hidangan kesukaan orang-orang muda, memenuhi ruang dengan kehangatan kampung.
Tetangga berdatangan membawa sukacita, melepas seorang anak desa yang hendak menapaki jalan seminari, merajut panggilan menjadi imam. Tiba-tiba suasana mereda; musik dihentikan seperti memberi ruang bagi sebuah perpisahan yang sakral.
Seorang sahabat mendekat, berbisik, “Mario, Madre sudah datang. Hapus air matamu, ia akan mendoakanmu.” Mario menyeka pipinya, lalu menggandeng ayahnya menuju tenda, melangkah pelan di antara harap dan duka.
Ayah berjalan dengan tongkat, tak lagi setegap ketika Mario kecil dulu bertengger di bahunya menuju kebun. Dalam ingatan, lelaki itu memanjat lontar, memeras tuak putih dari bunga yang disadap, sementara Mario kecil bernyanyi di bawahnya tentang Desa Tutuala di Lospallos, ujung timur Pulau Timor, tentang laut biru dan cinta yang tak lekang.
Di tengah riuh perang dan getir sejarah, dunia mereka terasa utuh. Matahari pernah naik tinggi menyinari langkah-langkah kecil yang pulang menyusuri bukit, dan kemesraan ayah-anak itu adalah kebahagiaan paling sederhana bagi sang ibu.
Kini, di mana pun Rio berada, gema suara ayahnya tak pernah benar-benar reda. Sejak fajar menyingsing hingga malam menutup mata, setiap kali jemarinya bergerak—saat mandi, makan, belajar, bahkan sebelum tidur—pandangannya selalu jatuh pada cincin ‘kea’ yang melingkar di jari manis tangan kanannya.
“Mengapa ayah memberiku cincin ‘kea’ ini?
Mengapa harus cincin?
Mengapa bukan baju atau kain sarung Timor?”
Namun di lubuk hatinya ia berbisik lirih: “Ayah, tanpa tanda mata pun aku takkan lupa pada kasih dan jasamu.”
***
Di sudut kamar sempit itu, Fr Mario da Silva Guterres —yang akrab disapa Frater Rio— menekap wajahnya dalam sunyi. Tangisnya tak boleh pecah menjadi suara; ia adalah lelaki muda yang sedang ditempa menjadi imam.
Di seminari tinggi, pada tahun pertama filsafat, segala sesuatu harus dipertanyakan dengan rapi: apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana. Hidup dibedah seperti teks yang menuntut analisis.
Namun di antara definisi dan silogisme, ada luka yang tak pernah selesai dirumuskan: perpisahannya dengan ayah dan ibu di Timor Leste. Empat tahun telah berlalu sejak ia meninggalkan tanah kelahirannya, tetapi nama Tutuala tetap datang seperti ombak, mengiris diam-diam dinding hatinya.
“Ayah, aku berjanji akan kembali jika aku sudah menjadi imam. Aku akan menikahkan ayah dan ibu agar hidup sebagai pasangan yang sah.”
Ia tahu kalimat itu lebih menyerupai mimpi daripada janji. Dalam khayalnya ia melihat dirinya berjubah putih berdiri di belakang altar. Di hadapannya, ayah dan ibunya yang telah renta berdiri bersisian, tongkat di tangan, wajah mereka diterangi cahaya yang lembut.
Keluarga dari kedua pihak duduk berdampingan tanpa curiga, tanpa luka. Suasana terasa seperti serpih surga yang jatuh ke bumi. Pesta dirayakan sederhana, namun penuh sukacita.
Lagu tebe bergema, tangan-tangan saling bertaut, langkah-langkah menari melingkar dalam damai. Di pelaminan kecil itu, ayah dan ibunya tersenyum, seakan segala badai telah lewat.
Tiba-tiba lonceng kapela berdentang, memutus jalinan khayalnya. Fr Mario bangkit; ia harus ke kapel untuk mendaraskan brevir.
Filipina memang tak terlampau jauh dari Timor Leste, tetapi rindu mampu menjadikan jarak sekecil apa pun terasa tak terjangkau. Kerinduan itu selalu memuncak setiap 02 November, ketika keluarga-keluarga berkumpul dan makan di kuburan, merayakan hari arwah dengan cara yang akrab dan hangat.
Ia teringat suatu siang masa kecilnya. Bersama ibu dan saudara-saudaranya, ia duduk di dekat sebuah makam tua, dengan ketupat dan lauk sederhana tersaji di atas tikar.
“Mana, ini kuburan siapa?” tanya Mario kecil polos.
“Ini ayah kita,” jawab Siska pelan.
“Ayah?”
“Ya, ayah kita.”
“Lalu yang sekarang bukan ayah kita?”
“Ia juga ayah kita. Ayah sambung.”
“Lalu ayah sambung punya anak juga?”
“Ya,” sahut Mana Siska singkat, lalu memalingkan wajahnya, menutup percakapan yang mulai menggetarkan dadanya.
Hati Siska bergetar, takut adiknya membaca kepedihan yang ia simpan: bahwa ayah yang kini mereka panggil ayah pun memiliki anak dan cucu, namun memilih tinggal bersama mereka.
Ia membungkuk dan berbisik, “Jangan tanya lagi. Kita sedang di kuburan ayah kita. Nanti ayah marah karena ibu menikah lagi.” Kalimat itu lebih untuk membungkam tangisnya sendiri daripada menakuti adiknya.
Matahari merambat tegak di atas kepala. Area kuburan riuh seperti pasar. Musik berdentang, anak-anak berlari dan tertawa, makanan dibagi di atas pusara, dan siapa pun boleh menyantapnya.
Di tengah kegembiraan yang ganjil itu, Mario kecil terdiam. Baginya, ayah kandung atau ayah sambung tak terlalu penting; kasih yang ia terima terasa tulus dan utuh.
Ia belum mengerti arti ditinggalkan. Baru setelah SMP ia memahami bahwa ia memiliki saudara-saudara tiri dari dua istri ayah yang terdahulu. Dan setelah SMA, kesadaran itu datang lebih pahit: kebahagiaan masa kecilnya mungkin berdiri di atas penderitaan yang diam-diam dipikul oleh saudara-saudaranya.
Malam semakin larut. Madre telah kembali ke biara, meninggalkan Mario dengan gema homili yang masih bergetar di udara: tentang panggilan, tentang kesetiaan, tentang salib yang harus dipanggul dengan rela.
Di tengah riuh pesta perpisahan, Mario justru tenggelam dalam sunyi. Tatapannya kosong, seakan tubuhnya berada di tenda, tetapi jiwanya tertahan pada peristiwa sore itu—di rumah ayah sambungnya, di kampung sebelah.
Ia datang dengan niat sederhana: berpamitan. Namun yang menyambutnya bukan pelukan, melainkan bara lama yang tak pernah padam.
“Mana Novia, bolehkah aku menemui ayah?”
“Ayah siapa?”
“Ayah Jeje.”
Sejak kalimat itu meluncur, jarak di antara mereka mengeras. Novia berdiri sebagai penjaga luka masa lalu. Baginya, Mario adalah anak dari kebahagiaan yang dibangun di atas serpihan hidupnya sendiri.
Kata-katanya meluncur tajam, menguliti kenyataan yang selama ini tak pernah sungguh dipahami Mario: tentang masa kecil yang dirampas, tentang adik-adik yang dibesarkan dengan tangan sendiri, tentang sekolah yang ditempuh dari hasil menjual ayam kampung, tentang seorang ayah yang semakin tua namun tak pernah benar-benar menjadi milik utuh siapa pun.
Mario diam. Untuk pertama kalinya ia melihat Novia bukan sebagai saudara tiri yang pemarah, melainkan sebagai perempuan yang terlalu lama memanggul beban orang dewasa sejak kanak-kanak.
Ketika ia hendak pergi, suara lemah memanggil dari balik kaca nako.
“Mario…”
Ia menoleh. Mata mereka bertemu hanya sedetik—mata seorang ayah yang rapuh dan mata seorang anak yang gamang. Namun Novia telah mendorong ayahnya kembali masuk. Pertemuan itu terhenti sebelum sempat menjadi pelukan.
Sepanjang jalan pulang, pertanyaan-pertanyaan tumbuh liar dalam dirinya. Apa salahku? Mengapa aku tak boleh memanggilnya ayah? Mengapa kasih harus dibagi seperti tanah warisan?
Malam itu Mario berangkat ke Filipina dengan hati yang terbelah—antara panggilan imamat dan panggilan darah.
Empat tahun berlalu. Cincin kea tetap melingkar di jari manisnya, menjadi saksi kesetiaan seorang ayah dan kebimbangan seorang anak. Namun di balik doa-doa brevir dan diskursus filsafat, hatinya tak pernah sungguh damai.
Ia belajar tentang hakikat kebenaran, tentang etika, tentang cinta sebagai agape. Tetapi hidupnya sendiri tak kunjung menemukan bentuk yang utuh.
Hingga akhirnya ia mengakui satu hal yang paling sulit: panggilan itu bukan miliknya. Ia lebih sering mengingat rumah daripada altar, lebih sering memikirkan ayah daripada homili. Dengan berat hati, Frater Rio melepaskan jubahnya. Ia pulang bukan sebagai imam, melainkan sebagai anak.
Kabar pertama yang menyambutnya di Tutuala adalah kematian Novia.
“Novia sudah meninggal beberapa bulan lalu,” kata ibunya lirih. “Ayah Jeje tak bisa lagi berjalan.”
Dunia seperti berhenti sesaat. Mario merasa kehilangan kesempatan yang tak akan pernah kembali: kesempatan untuk berdamai.
Ia pergi ke makam Novia saat senja merunduk. Di pusara itu ia tak lagi melihat musuh, hanya seorang perempuan yang terlalu lama memendam luka.
“Mana,” bisiknya, “kita hanyalah anak-anak yang tak pernah memilih badai orangtua kita. Jika ada yang salah, itu bukan kita. Malam ini aku menyalakan lilin bukan untuk membuka luka, tetapi untuk menutupnya dengan doa.”
Angin laut berhembus pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sedang melawan siapa pun.
Dari makam, ia menuju rumah ayahnya. Di pendopo, lelaki tua itu duduk dengan tubuh yang semakin ringkih.
Mario berlutut dan mencium tangannya. Ia mengangkat tangannya sendiri, menunjukkan cincin kea yang masih setia melingkar.
“Ayah, aku sudah pulang.”
Tak ada pidato panjang. Tak ada penjelasan tentang kegagalan atau cita-cita yang runtuh. Hanya pertemuan dua manusia yang akhirnya memilih saling menerima apa adanya.
“Aku tidak menjadi imam,” katanya pelan.
Ayahnya menatap cincin itu, lalu menatap wajah anaknya. Dalam diam itu, Mario mengerti: cinta tak pernah gagal, hanya berubah bentuk.
Ia memang tak berhasil menikahkan ayah dan ibunya di altar gereja seperti mimpinya dulu. Namun ia belajar sesuatu yang lebih sunyi dan lebih dalam—bahwa menjadi anak yang kembali, yang berani berdamai, yang tidak lari dari luka, mungkin adalah panggilan sejatinya.
Cincin kea itu tak lagi sekadar warisan. Ia menjadi lingkaran pengampunan—tak terputus, tak bersyarat.
Dan di bawah langit Tutuala yang biru dan luas, Mario akhirnya memahami: menjadi utuh bukan berarti menjadi sempurna, melainkan berani pulang dan merangkul semua serpihan sejarahnya sendiri.
Sr Mariana Sogen, ADM (Avelina Evi Sogen) lahir 15 Desember 1966 di Tenawahang, Kabupaten Flores Timur, ujung timur Pulau Flores. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga Katolik yang sederhana, yang menanamkan nilai iman, ketekunan, dan semangat pelayanan sejak usia dini.
Pendidikan dasarnya diselesaikan di SD Kalike, Solor Selatan, Pulau Solor, Flores Timur, tahun 1979. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Pamakayo, Solor Barat, dan lulus pada tahun 1982. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri Larantuka dan diselesaikan pada tahun 1985.
Pada tahun yang sama, 1985, ia memutuskan untuk memasuki Biara ADM di Yogyakarta, menapaki panggilan hidup bakti yang telah ia gumuli sejak masa remaja. Komitmennya untuk mengintegrasikan iman dan pendidikan mendorongnya melanjutkan studi tinggi. Pada tahun 1997, ia meraih gelar Sarjana Pendidikan Agama Katolik dari Sadhar Yogyakarta.
Sejak tahun 1997 hingga 2014, Sr Mariana mengabdikan diri sebagai pendidik di SMPK St Aloysius Weetebula. Selama kurang lebih tujuh belas tahun, ia terlibat aktif dalam karya pendidikan dan pembinaan iman generasi muda, menanamkan nilai-nilai Kristiani melalui pengajaran dan keteladanan hidup.
Memasuki babak baru panggilannya, pada tahun 2016 ia diutus sebagai misionaris pastoral ke Tutuala, Lospalos, Timor Leste. Hingga saat ini, ia terus melayani dalam karya pastoral dan pendampingan umat, menghadirkan semangat misioner Gereja di tengah masyarakat yang sederhana dan penuh dinamika sosial.
Dengan latar belakang pendidikan agama, pengalaman panjang sebagai pendidik, dan komitmen misioner lintas batas, Sr Mariana menjalani panggilannya sebagai religius yang setia melayani Gereja dan umat, khususnya di wilayah-wilayah perifer yang membutuhkan kehadiran kasih dan pengharapan.