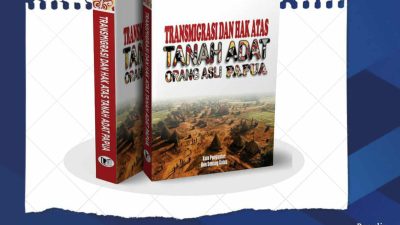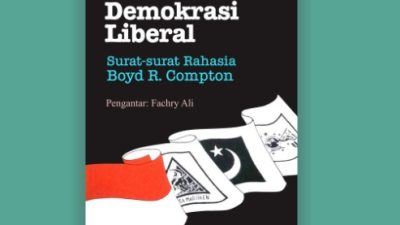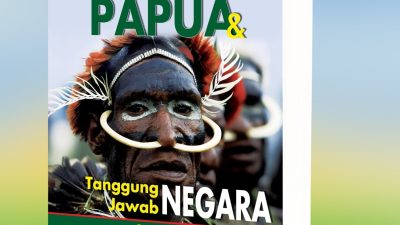Oleh Mariana Sogen
Misionaris asal Indonesia; Berkarya di Timor Leste
SASTRA yang besar tidak pernah benar-benar menua dan usai. Ia justru semakin bermakna ketika dibaca ulang di tengah zaman yang berubah. Novel Burung-Burung Manyar karya YB Mangunwijaya, yang pertama kali terbit pada tahun 1981, adalah salah satu contoh karya yang terus menemukan relevansinya.
Meski berlatar Indonesia tahun 1930-an hingga pasca-kemerdekaan —dengan puncak pergulatan ideologis pada dekade 1950-1960-an— novel ini berbicara tentang persoalan yang masih kita alami hari ini: konflik ideologi, polarisasi identitas, dan pencarian makna kemanusiaan di tengah pembangunan dan pertarungan kepentingan.
Konflik Ideologis
Indonesia pada 1950-an hingga awal 1960-an adalah ruang pertemuan ideologi yang keras dan sering kali saling meniadakan. Nasionalisme pascakolonial berhadapan dengan sisa-sisa kolonialisme Belanda, trauma pendudukan Jepang, serta pertarungan ideologi global Perang Dingin.
Dalam konteks inilah muncul konfigurasi Nasakom —nasionalisme, agama, dan komunisme— sebagai upaya politik untuk merajut mencoba persatuan, namun dalam praktiknya sering menimbulkan ketegangan dan kecurigaan di masyarakat.
Burung-Burung Manyar tidak secara dogmatis mengajarkan preferensi ideologi tertentu. Mangunwijaya justru menampilkan keragaman ideologi sebagai sesuatu yang hidup dalam tubuh manusia, dalam ingatan, luka, dan pilihan moral. Tokoh Teto tumbuh dari keluarga yang dekat dengan Belanda.
Trauma keluarganya akibat kekerasan perang —terutama oleh pendudukan Jepang— membentuk sikap ideologisnya yang rasional, keras, dan cenderung skeptis terhadap nasionalisme yang emosional.
Sementara itu, Atik mewakili nasionalisme Indonesia yang idealis, berakar pada keyakinan akan kemerdekaan dan pengabdian tanpa kompromi pada kekuatan kolonial mana pun.
Benturan ideologi antara Teto dan Atik adalah konflik politik, dan lebih-lebih konflik batin tentang bagaimana mencintai tanah air, bagaimana memahami sejarah, dan bagaimana menyikapi kekerasan atas nama bangsa.
Cinta yang Dewasa
Kisah cinta Teto dan Atik adalah inti emosional novel ini. Cinta mereka tumbuh sejak kecil, polos dan jujur, tetapi tidak pernah menemukan ruang aman untuk bersatu dalam mahligai perkawinan.
Ideologi, pilihan hidup, dan tanggung jawab sejarah memaksa mereka berjalan sendiri-sendiri di jalur yang berbeda. Atik menikah dengan pria lain yang sejalan dengan perjuangan nasionalnya, sementara Teto memilih jalan hidupnya sendiri, bahkan harus meninggalkan tanah air.
YB Mangunwijaya tidak meromantisasi kegagalan cinta ini sebagai tragedi tak bermakna. Justru di sanalah refleksi terdalam novel ini muncul. Ketika Atik meninggal dunia, Teto membesarkan anak Atik dengan penuh tanggung jawab.
Cinta yang tidak memiliki tubuh akhirnya menemukan wujud etisnya. Ia berubah dari cinta romantik menjadi cinta agape —cinta yang setia pada kehidupan, bukan pada kepemilikan.
Kita dan Burung-Burung Manyar
Burung manyar dikenal sebagai burung yang dengan sabar dan tekun merajut sarangnya dari bahan-bahan rapuh: rumput kering, serat, dan ranting kecil. Metafora ini menjadi kunci pembacaan novel.
Burung-burung manyar melambangkan rakyat Indonesia —manusia-manusia biasa yang hidup di bawah bayang-bayang ideologi besar, tetapi tetap berusaha membangun kehidupan yang harmonis dan bermakna.
Dalam pertarungan ideologis yang sering kali elitis dan keras, Mangunwijaya memilih berpihak pada yang rapuh. Ia menegaskan bahwa bangsa tidak dibangun oleh slogan ideologi, melainkan oleh kesetiaan manusia pada nilai kemanusiaan.
Seperti burung manyar, identitas Indonesia dirajut perlahan dari luka, perbedaan, dan kesediaan untuk tetap hidup bersama secara harmonis. Konflik ideologis hari ini tentu berbeda wajahnya dengan era Nasakom.
Kita tidak lagi berhadapan dengan komunisme versus nasionalisme secara terbuka. Namun polarisasi tetap hadir dalam bentuk baru: politik identitas, radikalisme agama, liberalisme pasar yang ekstrem, serta pertarungan narasi di media sosial yang sering memecah belah.
Jika pada masa Mangunwijaya ideologi dipertarungkan lewat senjata dan kebijakan negara, hari ini ideologi itu bertarung lewat ujaran kebencian, algoritma, dan pembelahan wacana. Burung-Burung Manyar mengingatkan bahwa tanpa kesadaran etis, konflik ideologi apa pun —lama atau baru— akan selalu melahirkan korban manusia.
Romo Mangun tidak hanya seorang novelis. Ia adalah salah satu Bapa Bangsa, sahabat intelektual dan spiritual Gus Dur, serta pejuang kemanusiaan yang konsisten membela kaum kecil. Wafatnya pada tahun 1999 —dalam pelukan Mohamad Sobari— menjadi simbol kesetiaan hidupnya pada kemanusiaan yang konkret, bukan retorika.
Nilai-nilai itulah yang menghidupi Burung-Burung Manyar. Novel ini bukan propaganda ideologi, melainkan kesaksian bahwa di atas semua isme, ada martabat manusia yang harus dijaga.
Burung-Burung Manyar mengajarkan bahwa perbedaan ideologi tidak harus berakhir pada saling meniadakan. Seperti burung manyar, manusia dipanggil untuk merajut kehidupan dari fragmen sejarah yang rapuh dengan benang cinta, kesadaran, dan tanggung jawab moral.
Di tengah konflik kekinian yang kian bising, novel lama ini justru berbicara dengan suara yang jernih: bahwa bangsa hanya akan bertahan jika manusia memilih setia pada kemanusiaan. Di sanalah cinta, ideologi, dan sejarah menemukan kedewasaannya.