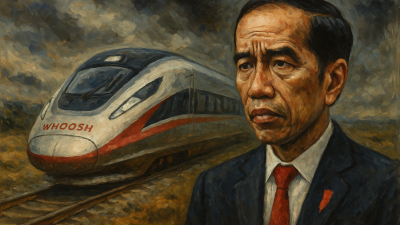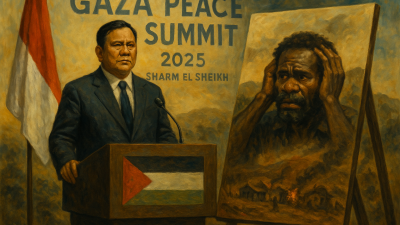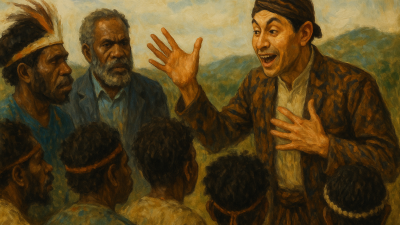![]()
SEJAK Kamis pekan lalu, Indonesia diguncang oleh gelombang demonstrasi yang dimulai di depan Gedung DPR RI. Ribuan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil turun ke jalan menuntut pembatalan sejumlah kebijakan kontroversial—mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan pelemahan KPK, hingga pemberian tunjangan rumah puluhan juta rupiah bagi anggota DPR yang dinilai tidak masuk akal di tengah penderitaan rakyat. Selain itu, massa juga mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, sebuah instrumen hukum penting untuk memberantas praktik korupsi dan mengembalikan kekayaan negara yang selama ini dinikmati segelintir elit. Aksi ini dengan cepat menyebar ke berbagai kota, namun Jakarta menjadi episentrum kemarahan: gedung-gedung pemerintahan diserang, arus lalu lintas lumpuh, dan bentrokan keras pecah antara aparat keamanan dan massa.
Dalam eskalasi yang mengejutkan, beberapa rumah politisi turut menjadi sasaran amarah rakyat. Kediaman Menteri Keuangan, sejumlah anggota DPR, hingga tokoh publik yang kini duduk di parlemen digeruduk, dirusak, bahkan dijarah. Dari peralatan rumah tangga, barang elektronik, hingga perhiasan pun raib digondol massa. Aksi-aksi tersebut menandakan bahwa kebencian rakyat sudah melampaui batas, menjadikan simbol-simbol kekuasaan dan kemewahan elit sebagai target pelampiasan. Jakarta pun berubah menjadi panggung amarah kolektif rakyat yang menolak lagi untuk diam.
Gelombang protes ini bukanlah peristiwa spontan tanpa alasan. Ia merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan dan sakit hati rakyat terhadap elit politik yang semakin hari semakin menunjukkan arogansi. Janji perubahan tinggal slogan, sementara kenyataan yang dirasakan rakyat adalah hidup yang makin sulit, harga-harga melambung, dan kesempatan kerja yang kian menyempit. Di sisi lain, mereka menyaksikan elit politik sibuk mengatur fasilitas untuk diri sendiri, menumpuk privilese, dan melupakan fungsi utama sebagai wakil rakyat.
Amukan rakyat kali ini menjadi peringatan keras bahwa demokrasi tidak bisa dipelihara hanya dengan pemilu lima tahunan. Demokrasi menuntut adanya ruang partisipasi nyata, keterbukaan terhadap kritik, dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat kecil. Sayangnya, yang terlihat justru sebaliknya: kritik dibungkam, kebijakan dibuat untuk melayani kepentingan segelintir orang, dan rakyat hanya dijadikan komoditas suara ketika musim pemilu tiba.
Dalam kondisi seperti ini, ledakan sosial nyaris tidak terhindarkan. Rakyat yang lama diam akhirnya bangkit, bukan semata-mata untuk membuat kerusuhan, melainkan untuk menyuarakan rasa frustrasi yang tidak lagi mendapat ruang. Mereka ingin didengar, ingin dihargai, dan ingin keadilan ditegakkan. Pertanyaan sederhana pun muncul: sampai kapan rakyat harus bersabar sementara elit terus bersikap pongah?
Tugas besar kini berada di tangan pemerintah dan DPR. Apakah mereka akan merespons dengan jalan represif, atau berani membuka pintu dialog yang sejati? Jalan keras hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan. Sebaliknya, kesediaan untuk rendah hati, mendengar jeritan rakyat, dan membenahi akar persoalan adalah satu-satunya jalan untuk meredakan badai.
Presiden memang telah mengambil langkah dengan mencabut tunjangan parlemen dan menghentikan sejumlah fasilitas mewah. Namun, rakyat menilai itu belum cukup. Yang dituntut bukan sekadar pencitraan sesaat, melainkan reformasi struktural yang nyata: pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat banyak.
Akhirnya, amukan rakyat Indonesia adalah cermin dari kegagalan elit menjalankan mandatnya. Jika cermin ini tidak dijadikan bahan perenungan, maka kemarahan rakyat akan terus berulang dengan skala yang lebih besar. Elit politik kini dihadapkan pada pilihan tegas: berubah dan kembali ke jalan rakyat, atau bersiap ditinggalkan dan digilas oleh gelombang amarah yang semakin tak terbendung. (Editor)