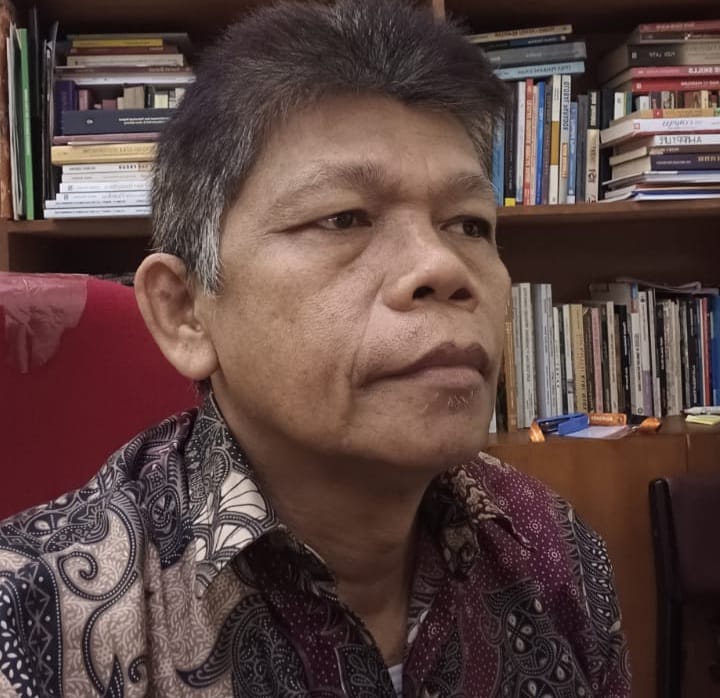Ole Kasdin Sihotang
Dosen Filsafat Moral Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
DALAM memaknai perayaan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, merefleksikan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting. Refleksi diperlukan sebagai cermin untuk melihat apa yang dilakukan di masa lalu, dan menatap jauh ke depan dengan hasil refleksi itu. Pandangan etika dapat menjadi salah satu titik berangkat dalam refleksi itu.
Dalam sejarah pemikiran etika, ada dua teori etika yang selalu menjadi pokok diskusi di dunia akademik. Kedua teori etika itu adalah teleologi dan deontologi. Kedua teori etika ini menjadi topik diskursus, karena digunakan sebagai moral reasoning atau dasar argumen untuk memberikan bobot sebuah keputusan atau tindakan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
Etika teleologi adalah teori etika yang pertama. Makna etika teleologi bisa disisir dari etimologi kata “teleologi”, yakni telos, artinya “jauh”, “tujuan” dan logos, yang artinya ilmu atau paham. Dari penelusuran etimologis ini, kata “teleologi” berarti paham yang mendasarkan diri pada tujuan atau sesuatu yang ingin disasar atau dicapai. Sedangkan etika artinya adalah pemikiran yang membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan prinsip-prinsip moral.
Jika kata “etika” dan “teleologi” dipadukan, maka dapat dirumuskan satu definisi yang memuat keduanya, yakni paham atau teori yang meletakkan ukuran baik buruknya suatu perbuatan atau keputusan pada sesuatu yang akan dicapai. Secara lain dapat dikatakan, etika teleologi adalah teori yang mengukur baik buruknya sebuah perbuatan atau keputusan berdasarkan tercapai tidaknya tujuan. Dalam bingkai berpikir demikian, yang baik adalah hal-hal yang sesuai dengan tujuan, sedangkan yang buruk adalah hal yang tidak mendukung tercapainya tujuan itu.
Kewajiban Moral
Pokok diskursus etika kedua adalah deontologi. Etika deontologi berbeda dari etika teleologi. Perbedaannya terletak pada dasar dan cara dalam kedua pandangan tersebut. Kata ‘deontologi’ bersumber dari bahasa Yunani, yang merupakan gabungan dari dua kata deon, artinya kewajiban, dan logos, artinya paham atau pandangan.
Dari etimologi ini kita dapat merumuskan pengertian dari deontologi sebagai paham yang meletakkan kewajiban sebagai dasar dalam menilai suatu perbuatan atau keputusan. Kewajiban apa yang dimaksudkan? Tentu kewajiban dalam konteks moral, yakni prinsip-prinsip moral dasar.
Kalau disandingkan kata “deontologi” dengan kata “etika”, maka etika deontologi adalah paham yang menempatkan kewajiban moral sebagai kriteria atau dasar penilaian sebuah perbuatan/keputusan. Konkritnya, baik adalah sesuai dengan kewajiban moral, buruk adalah hal yang melanggar kewajiban moral itu. Etika ini menempatkan hal-hal yang prinsipial tentang kemanusiaan sebagai kriteria atau ukuran sebuah perbuatan.
Dari penelusuran etimologi dan narasi esensi kedua teori di atas terlihat dengan jelas bahwa perbedaan etika teleologi dan etika deontologi sangat mencolok. Jika etika teleologi meletakkan dasar ukuran penilaian pada tercapai tidaknya sebuah tujuan, maka deontologi justru melihat nilai perbuatan itu sendiri.
Jika etika teleologi membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan, maka etika deontologi justru menolaknya, sebab cara demikian tidak sesuai dengan esensi etika itu sendiri. Manusia memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi kewajiban moralnya.
Karena itu penganut etika deontologi, khususnya Immanuel Kant membedakan imperatif kategoris dan imperatif hipotetis. Imperatif kategoris adalah prinsip-prinsip etis yang dilaksanakan tanpa harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kejujuran, hormat pada martabat manusia, keadilan dan kewajiban moral lainnya.
Bagi penganut etika deontologi, sebuah perbuatan yang dijalankan demi tujuan atau maksud tertentu bukanlah bernilai etis tinggi, melainkan bernilai etis rendah. Mengapa? Karena di situ orang bisa saja bersikap munafik demi tercapainya tujuan itu. Jika tujuan tidak tercapai maka orang demikian tidak akan menjalankannya lagi, atau menganggap apa yang dilakukan itu buruk.
Bagi penganut deontologi orang seperti ini justru melakukan apa yang disebut dengan imperatif hipotetis. Imperatif hipotetis memiliki nilai etis yang kurang berbobot, karena imperatif ini mengandung motif tertentu dalam setiap tindakan.
Pentingnya Etika Utilitarisme
Etika teleologi dan etika deontologi selalu hadir mewarnai kehidupan manusia baik secara pribadi maupun secara sosial. Kedua prinsip itu sama-sama penting. Namun dalam refleksi ini penulis memberikan perhatian pada etika teleologi, khususnya utilitarisme, karena etika ini sangat relevan dan kontekstual dalam memotret perjalanan bangsa di usia delapan dekade kemerdekaannya.
Cabang etika teleologi yang banyak diperbincangkan adalah utilitarisme, di atas urutan egoisme dan hedonisme. Mengapa utilitarisme menjadi perhatian banyak orang? Sebenarnya jawabannya terletak pada makna kata “utility” itu. Kata utilitarianisme berasal dari kata Latin, yakni “utilis/e”, atau bahasa Inggris, utility, artinya manfaat, berguna”. Inti etika utilitarisme terletak dalam pengertian kata tersebut.
Pengertian itu diturunkan menjadi tiga prinsip etika utilitarisme, yakni (i) manfaat, (ii) manfaat terbesar, dan (iii) manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Ketiga prinsip ini dirasakan sangat dekat dan umum serta menyertai kehidupan keseharian manusia. Manfaat itu bisa dilihat dari berbagai segi, ya ekonomilah, ya kesehatanlah, atau manfaat yang lainnya. Manfaat itu menjadi tujuan, karenanya dijadikan sebagai standar penilaian baik buruknya suatu perbuatan atau keputusan.
Seperti sudah dipaparkan bahwa etika teleologi meletakkan ukuran perbuatan pada tujuan suatu tindakan. Para pemikir seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menyadari bahwa kehidupan manusia selalu mengarah ke depan.
Edmund Husserl, seorang filsuf fenomenologi membahasakan dengan intensionalitas, yakni keterarahan terhadap sesuatu. Dalam bingkai berpikir demikian tujuan menjadi sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Salah satu tujuan dimaksudkan adalah mencari dan mendapatkan hal-hal yang berguna atau bermanfaat dari berbagai aspek kehidupan nyata manusia.
Dengan pandangan ini Jeremy Bentham dan Stuart Mill menyodorkan cara pandang baru dalam menilai sebuah perbuatan atau tindakan, yakni manfaat atau kegunaannya, yang berbeda dengan cara pandang yang lazim pada masa itu, yakni kriteria nilai transendental. Inilah inti dari etika utilitarisme. Jadi, etika utilitarisme menghadirkan sebuah standar baru dalam memberikan penilaian pada perbuatan atau keputusan, yakni manfaat.
Relevansi dan Aktualitas
Dalam pembangunan bangsa, teori etika utilitarianisme sangat relevan. Secara tidak sadar, teori etika ini sesungguhnya telah hadir di republik ini, kendati hanya dalam bentuk jargon atau ungkapan. Belakangan esensi itu bahkan bergeser ke kepentingan parsial atau kelompok tertentu. Bagaimana hal itu terlihat? Jargon “kepentingan umum” adalah salah satu contohnya. Jargon ini persis mengakomodir prinsip utilitarisme, lebih-lebih prinsip ketiga, yakni “kebaikan atau manfaat yang terbesar bagi sebanyak mungkin orang”.
Seperti sudah disinggung di atas, ada tiga prinsip etika utilitarisme: manfaat, manfaat terbesar, manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip pertama pada umumnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan apapun yang kita lakukan.
Artinya, sebelum melakukan sesuatu atau dalam memutuskan sesuatu, perhatikan manfaat yang terkandung di dalamnya, ada atau tidak. Jika Anda merasa tidak ada kegunaan atau manfaat suatu tindakan, ya jangan lakukan. Sebaliknya, jika ada manfaat akan Anda dapatkan, ya jalankan.
Namun kadang kita berhadapan dengan dua jenis kegiatan yang sama-sama memiliki manfaat. Mana yang dipilih? Menurut etika utilitarisme, yang dipilih adalah manfaat yang lebih besar atau lebih banyak. Selain kuantitas manfaat, jumlah subjek yang terlibat di dalamnya perlu juga diberi perhatian.
Artinya, sebuah keputusan atau kebijakan harus mempertimbangkan kuantitas subjek yang akan merasakan manfaat kebijakan atau keputusan itu. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merumuskannya dengan ungkapan “the greatest happiness for the greatest numbers”, manfaat yang paling banyak bagi sebanyak mungkin orang.
Artinya, jika sebuah kebijakan atau keputusan hanya menguntungkan segelintir orang, sebaliknya merugikan lebih banyak orang, maka kebijakan atau keputusan itu buruk. Sebaliknya jika manfaat dari keputusan itu dirasakan sebanyak mungkin orang, maka keputusan itu adalah baik adanya. Kata “kepentingan umum” merepresentasikan prinsip ketiga utilitarisme demikian.
Dalam konteks pembangunan di Indonesia, seperti sudah dinyatakan di atas, prinsip ketiga etika utilitarisme tersebut sangat relevan dan aktual. Relevansi dan aktualitas prinsip demikian dapat dihadirkan minimal dalam tiga hal berikut.
Pertama, perlunya kepentingan rakyat luas sebagai dasar pengambilan keputusan. Prinsip ketiga mengisyaratkan agar sebelum mengambil keputusan, kuantitas subjek yang merasakan kebijakan atau keputusan haruslah diperhatikan.
Artinya, jumlah masyarakat yang merasakan sebuah kebijakan harus menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Sesuai standar ini, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang dalam hal-hal yang positif. Sebaliknya, kebijakan yang buruk adalah kebijakan yang hanya memenuhi kepentingan kelompok tertentu yang jumlahnya kecil.
Tidak bisa dimungkiri bahwa rancangan kebijakan entah berupa undang-undang atau peraturan bermotifkan kepentingan tertentu dari berbagai kalangan, terutama pebisnis. Kondisi demikian seyogyanya harus ditinggalkan oleh pengambil kebijakan.
Pertimbangan pengambil keputusan haruslah kepentingan masyarakat lebih luas, bukan kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. Secara lain dapat dikatakan, kepentingan rakyat haruslah menjadi dasar pertimbangan penentuan kebijakan di seluruh lini pemerintahan.
Rusaknya bangsa ini justru disebabkan oleh kebijakan yang dibuat lebih berpihak pada kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi, sementara kepentingan masyarakat dipinggirkan, bahkan dikorbankan.
Plato, seorang filsuf Yunani dalam Republic (1980), sudah mengingatkan hal itu. Plato mengatakan bahwa ketidakadilan justru terjadi ketika pemimpin dan pengambil kebijakan hanya berpihak kepada kelompok tertentu.
Karena itu Plato tidak setuju jika seorang pemimpin merangkap seorang pebisnis atau sebaliknya pebisnis merangkap sebagai pemimpin atau berada dalam lini pengambil kebijakan.
Situasi ini sangat membuka peluang bagi ketidakadilan atau keberpihakan. Sama halnya juga ketika aparat keamanan negara berbisnis. Di sana juga pasti ada konflik kepentingan sehingga fungsi utama menjadi alat negara yang memberi keamanan dan kenyamanan bagi rakyat secara menyeluruh akan sulit terjadi.
Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari esensi prinsip “the greatest happiness for the greatest numbers” itu. Franz Magnis Suseno dalam Etika Politik (2023) telah menunjukkan hal itu. Menurut Franz Magnis, tidak mungkin keadilan sosial terwujud, kalau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berpihak kepada rakyat luas.
Secara positif dapat dikatakan, keadilan sosial hanya akan menjadi kenyataan jika pemerintah dalam kebijakannya menjamin bahwa kepentingan masyarakat di atas segala-galanya, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Bagi Magnis keadilan sosial tidak tergantung pada pribadi, tetapi pada sistem yang diciptakan oleh pemerintah. Ketika sistemnya tidak baik, maka di situ tidak mungkin keadilan sosial akan menjadi kenyataan.
Hal yang sama juga ditegaskan oleh Iris Marion Young dalam Justice and the Politics of Difference (2011). Young menyatakan secara tegas bahwa ketidakadilan justru terjadi ketika ada pembeda-bedaan dalam muatan kebijakan, dan dasar pembedaan itu adalah keberpihakan pada kepentingan kelompok kecil.
Penegasan Young ini di kemudian ditekembangkan oleh Maeve Mckeown dalam konteks kekuatan pemerintah sebagai penegak keadilan. Dalam bukunya With Power Comes Responsibility (2025), Maeve menyatakan bahwa pemerintah merupakan agen bagi terwujudnya keadilan sosial.
Mengapa? Karena mereka memiliki kekuatan untuk itu. Bahkan mereka diberi otoritas mewujudkan itu. Karena itulah bagi Maeve, fungsi utama dari pemerintah adalah menjamin keadilan itu dengan menggunakan kekuasaannya.
Kedua, mengelola hasil-hasil bumi agar hasilnya dapat dinikmati oleh oleh masyarakat yang luas. Dalam hal ini pemerintah perlu berpikir ulang tentang prinsip swastanisasi dalam berbagai hal terkait dengan pengelolaan hasil bumi Indonesia ini.
Roh yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus menjadi pijakan pemerintah dalam mengelola bangsa ini. Hasil-hasil bumi harus dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat secara absolut.
Bagaimana cara mengupayakan hal itu? Negara sesungguhnya punya orang-orang untuk itu. Toh negara menghabiskan uang untuk menyekolahkan begitu banyak kaum akademisi dan keilmuan baik ke manca negara maupun di dalam negeri.
Mereka harus “dimanfaatkan”, tanggung jawab mereka harus ditumbuhkembangkan demi kemajuan negeri. Secara lain dapat dikatakan negara harus menggugah mereka untuk ambil bagian dalam upaya itu sebagai sumbangsihnya bagi negeri ini
Ketiga, mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Apa yang dinyatakan oleh Franz Magnis Suseno, Marion Irish Young dan Maeve Mckeown masih jauh dari yang sebenarnya. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, namun kesejahteraan secara luas belumlah dirasakan oleh masyarakat secara merata.
Pengalaman hidup berbangsa dan bernegara hingga di usia delapan dekade menunjukkan bahwa setiap kali pergantian pemerintahan, selalu saja keberpihakan pada kelompok tertentu lebih menonjol daripada keberpihakan kepada masyarakat secara umumnya.
Lihatlah penguasa lahan-lahan bisnis strategis. Mereka yang punya akses di sana hanya kelompok tertentu, yang berpartner dan memiliki jaringan. Yang tidak punya? Jangan berharap bisa tembus.
Atas situasi demikian, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah ada. Peraturan-peraturan yang bernuansa keberpihakan kepada kelompok tertentu harus dibatalkan. Kriteria “the greatest happiness for the greatest number” haruslah menjadi perhatian serius.
Sekali lagi meminjam pendapat Maeva Mckeown, pemerintah memiliki “power” untuk itu. Kekuatan itu harus diperlihatkan sebagai wujud tanggung jawab moralnya bagi masyarakat. Ini merupakan salah satu buah dari perayaan 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini.
Pemerintah seyogyanya memiliki komitmen untuk itu. Mewujudkan keadilan sosial identik dengan prinsip etika utilitarisme, “the greatest happiness for the gratest numbers” sebagai wujud janji dan sumpah para elite bagi negeri ini. Semoga.