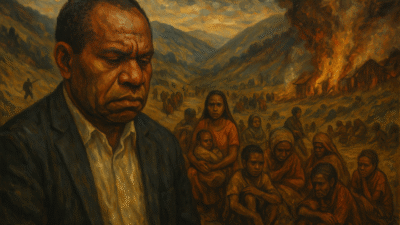![]()
DALAM konflik berkepanjangan di Timur Tengah, terutama yang melibatkan Israel di satu pihak dan Iran beserta proksi-proksinya di pihak lain, media massa Indonesia sering kali tidak netral. Pemberitaan dan analisis yang muncul di berbagai platform media menunjukkan kecenderungan yang berat sebelah: membela Iran dan kelompok-kelompok militan Islam, sembari mencerca Israel tanpa mempertimbangkan konteks geopolitik dan fakta lapangan secara objektif.
Fenomena ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari warisan historis, sentimen agama mayoritas, dan konstruksi ideologis yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Israel sejak lama dipandang sebagai simbol penjajah dan penindas rakyat Palestina, sementara lawan-lawannya—termasuk Iran, Hamas, dan Hizbullah—dilihat sebagai pejuang pembebasan. Sayangnya, pembacaan semacam ini kerap mengabaikan dimensi kekuasaan, politik identitas, dan strategi ekspansi dari pihak-pihak yang dibela.
Iran, misalnya, bukan sekadar negara Islam. Ia adalah kekuatan regional yang aktif menyebarkan pengaruh melalui berbagai proksi bersenjata di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Banyak dari kelompok tersebut terlibat dalam aksi kekerasan yang juga menargetkan warga sipil. Namun dalam narasi media Indonesia, hal ini sering kali diabaikan atau dibingkai ulang sebagai “perlawanan terhadap penjajahan”.
Kecenderungan ini diperparah oleh para pengamat yang tampil di ruang publik dengan tafsir-tafsir simplistik dan sarat ideologi. Alih-alih mendorong pemahaman yang jernih, sebagian justru memperkuat polarisasi dan menyebarkan opini yang tidak adil. Ironisnya, mereka sering dianggap sebagai sumber kebenaran hanya karena narasi mereka sesuai dengan emosi publik.
Kita perlu mengkritisi bias ini, bukan karena ingin membela satu pihak, tetapi karena kita butuh media yang jujur, adil, dan rasional. Media yang hanya melayani emosi publik akan gagal memberikan pencerahan. Publik Indonesia tidak boleh terus-menerus dicekoki dengan narasi yang menyederhanakan konflik menjadi hitam-putih. Dunia nyata jauh lebih rumit dari itu.
Dalam menghadapi konflik internasional, media dan pengamat seharusnya menjadi jembatan pemahaman, bukan corong propaganda. Jika Indonesia ingin berperan dalam perdamaian global, maka sikap yang dibangun di dalam negeri pun harus mencerminkan keberimbangan, ketelitian, dan tanggung jawab moral. (Editor)